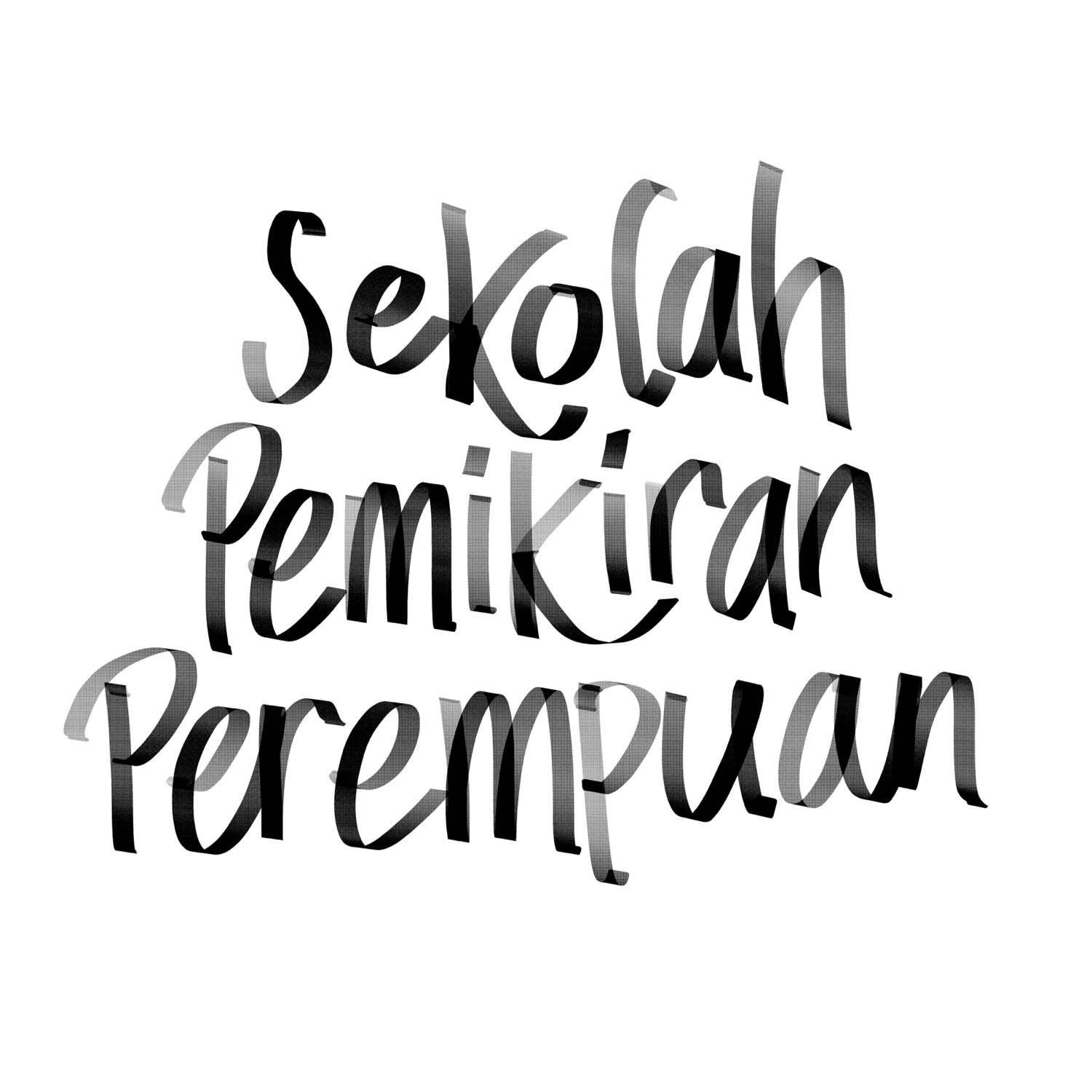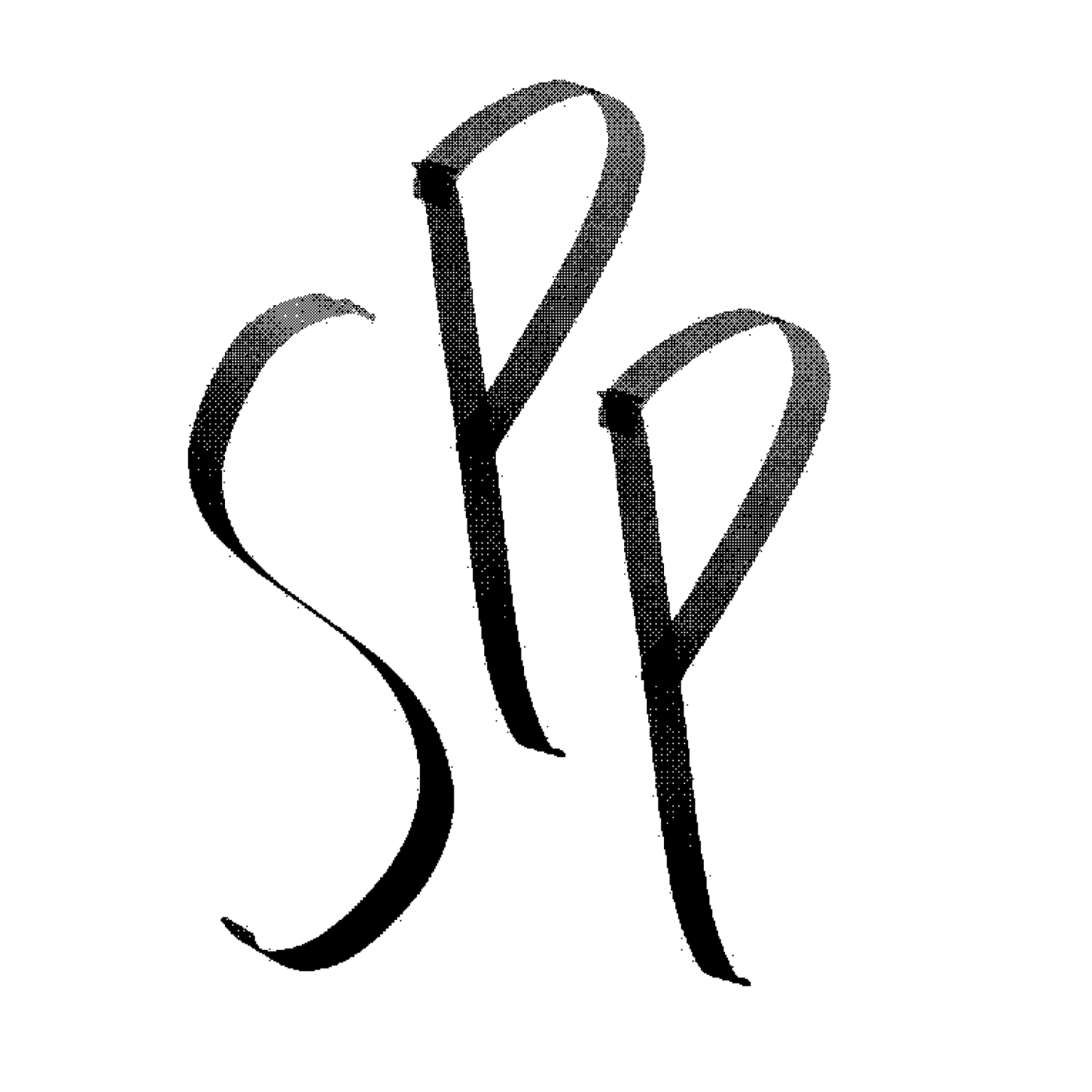Klub Cerap: Perkara Keramat
Pada 19 Oktober 2024 lalu SPP mengadakan diskusi daring Klub Cerap untuk membahas novel terbaru Raisa Kamila, Perkara Keramat. Diskusi ini dipantik oleh Ratih Fernandez serta dipandu oleh Himas Nur.
Klub Cerap merupakan forum diskusi karya–yang kritis berperspektif feminis, suportif, aman, serta empatik–bagi alumni Sekolah Pemikiran Perempuan. Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi salah satu perawat ekosistem tumbuhnya karya-karya kawan dengan keikutsertaan kita semua sebagai haranya.
Perkara Keramat terbit pada 15 Mei 2024 oleh Gramedia Pustaka Utama. Novel ini berkisah tentang Hasan dan Husein yang berupaya merajut dan merawat kenangan tentang Ayah dan Mamak, serta rumah mereka di Banda Aceh selepas tsunami 2004, melalui peristiwa di Kedai Mieso H. Idris–tempat makan langganan semasa kanak.
Dalam diskusi, Ratih Fernandez menjabarkan bagaimana "masa remaja" diposisikan di sejumlah prosa karya Raisa Kamila. Masa tersebut, dalam karya Raisa, memperlihatkan kebingungan manusia terhadap proses tumbuh: perubahan tubuh serta cara pandang. Mengerucut pada novel "Perkara Keramat", masa “di antara” tersebut tampak pada perjalanan hidup Hasan dan Husein sebagai tokoh utama. Mereka dihadapkan pada perubahan besar kota Banda Aceh pasca tsunami, yang kemudian menggerakkan mereka untuk menggali lalu merawat sisa-sisa kenangan. Raisa menempatkan tokoh remaja untuk menguatkan momentum transisi sebuah peristiwa. Tak hanya itu, tokoh remaja kembar yang tumbuh jadi pribadi berbeda pun diniatkan untuk mengantitesis perspektif mapan terhadap anak-anak kembar, bahwa anak kembar identik mesti melulu identik (atau mirip) penampilannya.
Dalam perjalanannya, mereka tumbuh menjadi pribadi yang berbeda meskipun tinggal bersama; begitu pula orang-orang di sekitar mereka. Namun, ada yang tak berubah: sejarah di dalam museum serta perpustakaan di kota tersebut. Penggambaran serupa memantik sebuah tafsir, bahwa sejarah disikapi sebagai hal yang tak berhubungan dengan masa kini. Hal itu pun tampak pada hubungan antara para tokoh yang selamat dari tsunami. Kita disuguhkan relasi yang dingin antara Hasan dan Husein (dan paman mereka, Om Jack), juga H. Idris dan anaknya, Laila. Kehangatan hanya hadir pada relasi romantik Om Jack dan Putri Sanubari (Riri) yang penuh penerimaan atas kerapuhan dan trauma masing-masing. Selain itu, adalah satu pusaran konflik yang kemudian menjadi motif para tokoh untuk merawat sejarah hidup mereka, yakni kehadiran Poetroe Faradiba yang ingin mengambil lahan H. Idris demi eksistensi makam leluhurnya.
Ratih mengamati kecenderungan Raisa dalam beberapa prosa karyanya, yakni minimnya penggarapan suatu lokasi. Hal tersebut berulang dalam novel ini di satu aspek lain, yaitu penggarapan kedalaman karakter sejumlah tokoh: Laila, Riri, dan Faradiba; juga relasi Om Jack-Riri serta H. Idris-Laila. Kami melihat kritik ini berangkat dari kepercayaan Ratih bahwa Raisa mampu mengeksplorasi tokoh-tokoh tersebut secara lebih lanjut, sebab kompleksitas para tokoh sebetulnya sudah tampak dalam teks.
Bicara soal sisa ingatan pasca tsunami, Raisa menempatkan makanan sebagai mesin waktu yang mampu mengantarkan siapa pun pada ingatan masa lalu. Alhasil, muncullah warung mieso H. Idris; berlokasi di pasar, yang dipilih Raisa sebagai latar utama peristiwa sebab mampu memuat tegangan antara yang lokal dan yang universal.
Tak hanya itu, ia pun mengonsepkan eksplorasi cara manusia menempatkan eksistensi anggota keluarga. Mengapa orang bisa merasa begitu dekat dan mesti "merawat" anggota keluarganya yang telah meninggal, sedangkan kepada yang masih hidup mereka tak saling memberi perhatian, sehingga kehadiran satu sama lain kerap tipis dirasakan. Kontradisi tersebut menyebabkan banyak luka dalam keluarga yang tak dibicarakan. Secara kolektif dan meluas, itu berefek pada cara pandang masyarakat (lalu dikekalkan oleh pemerintah) terhadap sejarah: sejarah resmi tidak boleh diganggu-gugat.
Novel "Perkara Keramat" secara kritis memantik pertanyaan teknis soal ruang (seberapa besar fungsi "ruang" dalam cerita?), pun merefleksikan upaya Raisa dalam menempatkan tokoh laki-laki yang mampu melakukan kerja perawatan, menampilkan perempuan yang bukan objek, serta bagaimana hubungan manusia dan sejarahnya melalui peristiwa sehari-hari.
Kawan-kawan SPP yang hadir turut menyampaikan pengalaman membaca mereka. Beberapa pembaca menanggapi teknik bercerita Raisa yang mengingatkan mereka pada pengalaman menelusuri Aceh ditemani penuturan pemandu lokal. Mereka merasakan teknik bercerita yang serupa antara narasi yang Raisa hadirkan dengan cerita lisan orang Aceh yang pernah mereka temui: kemampuan bercerita yang luwes tanpa dramatisasi berlebih atau melodrama. Raisa menanggapi, “audience-ku adalah teman-temanku yang mengalami.” Pendekatan pembaca spesifik alih-alih umum ini Raisa gunakan sebagai siasat untuk menulis sejarah tanpa menciptakan fiksi yang bersifat mendikte. Tidak hanya mengkritik sejarah resmi, Perkara Keramat memang menentang pakem genre fiksi sejarah dengan berfokus pada masa masa “di antara”.
Diskusi dari para pembaca membuat kami dapat menemukan kecanggihan teknik menulis Raisa lainnya. Raisa memiliki pemahaman jelas bahwa estetika dan substansi berjalan beriringan dalam teks. Contohnya, Raisa kerap menggunakan pasar sebagai latar karena pasar membuatnya dapat menuliskan sesuatu yang sangat lokal tetapi juga universal: pasar ada di mana-mana, tetapi isinya berbeda. Pasar dalam narasi mengulik kehidupan dan resiliensi orang yang harus bertahan, misalnya bagaimana pasar segera kembali muncul pasca bencana dan konflik. Kemudian, Raisa juga berhati-hati dalam memilih sudut pandang narator. Raisa yakin bahwa dalam menceritakan Perkara Keramat, ia perlu menggunakan narator yang dapat membuntuti dan mengintip pikiran tokoh, tetapi pada saat yang sama tidak masuk ke kepala tokoh perempuan.
Obrolan berlanjut sampai ke bagaimana cara merawat ruang yang mendukung proses berkarya perempuan penulis. Kami mengingat bahwa dalam “Perempuan Meretas Sastra” Etalase Pemikiran Perempuan 2020, Raisa sendiri pernah berkata, yang perlu diretas di sastra Indonesia adalah ekosistem belajar yang tidak inklusif. Raisa menyebutkan bahwa ruang belajar menulis di berbagai daerah seringkali sangat rentan terhadap opresi dengan praktik belajar yang sangat maskulin, hanya membahas karya laki-laki, dengan pandangan laki-laki. Sepaham dengan pendapat Raisa kala itu, para peserta diskusi setuju bahwa kita juga perlu ruang aman dan nyaman untuk mendukung karya kawan yang sedang berjalan, sehingga mereka dapat mendapatkan masukan tanpa pandangan dan standar penilaian maskulin. Kami dari Klub Cerap pun masih kerap mendengar pengalaman kawan-kawan perempuan penulis yang mendapatkan tanggapan berpandangan dan berstandar maskulin dalam proses mereka berkarya.
Proses merencanakan dan menyelenggarakan Klub Cerap, serta pembahasan karya Raisa membuat kami belajar beberapa hal tentang apresiasi karya berperspektif feminis. Pertama-tama, dalam pemilihan karya yang akan dibahas, kami ditantang untuk memilih satu di antara berbagai karya kawan yang tak kalah penting dan menarik. Kami tetap harus melakukan voting, dipandu “kepedulian” dalam mempertimbangkan berbagai aspek seperti sistem pendukung yang pencipta karya miliki, dan isu penting yang dibahas dalam karya. Penentuan waktu penyelenggaraan, pencerap atau pembahas, dan pemandu diskusi pun dituntun oleh kepedulian untuk merayakan karya Raisa dengan sebaik-baiknya. Kemudian, dalam proses pemilihan pencerap, Ratih memberi masukan agar Klub Cerap memberi kesempatan kepada Raisa untuk memilih siapa yang akan mencerap karyanya, sehingga Raisa dapat merasa aman dan nyaman. Tak disangka, Raisa mengajukan dua nama, yang di antaranya adalah Ratih. Alasan pemilihan Raisa adalah karena Ratih juga menulis fiksi, lulusan Ilmu Sejarah, dan sudah hadir di dua diskusi Perkara Keramat sebelumnya. Klub Cerap memutuskan pilihan pada Ratih karena melihat bagaimana Raisa merasakan kepedulian Ratih untuk membaca karyanya secara mendalam dan reflektif.