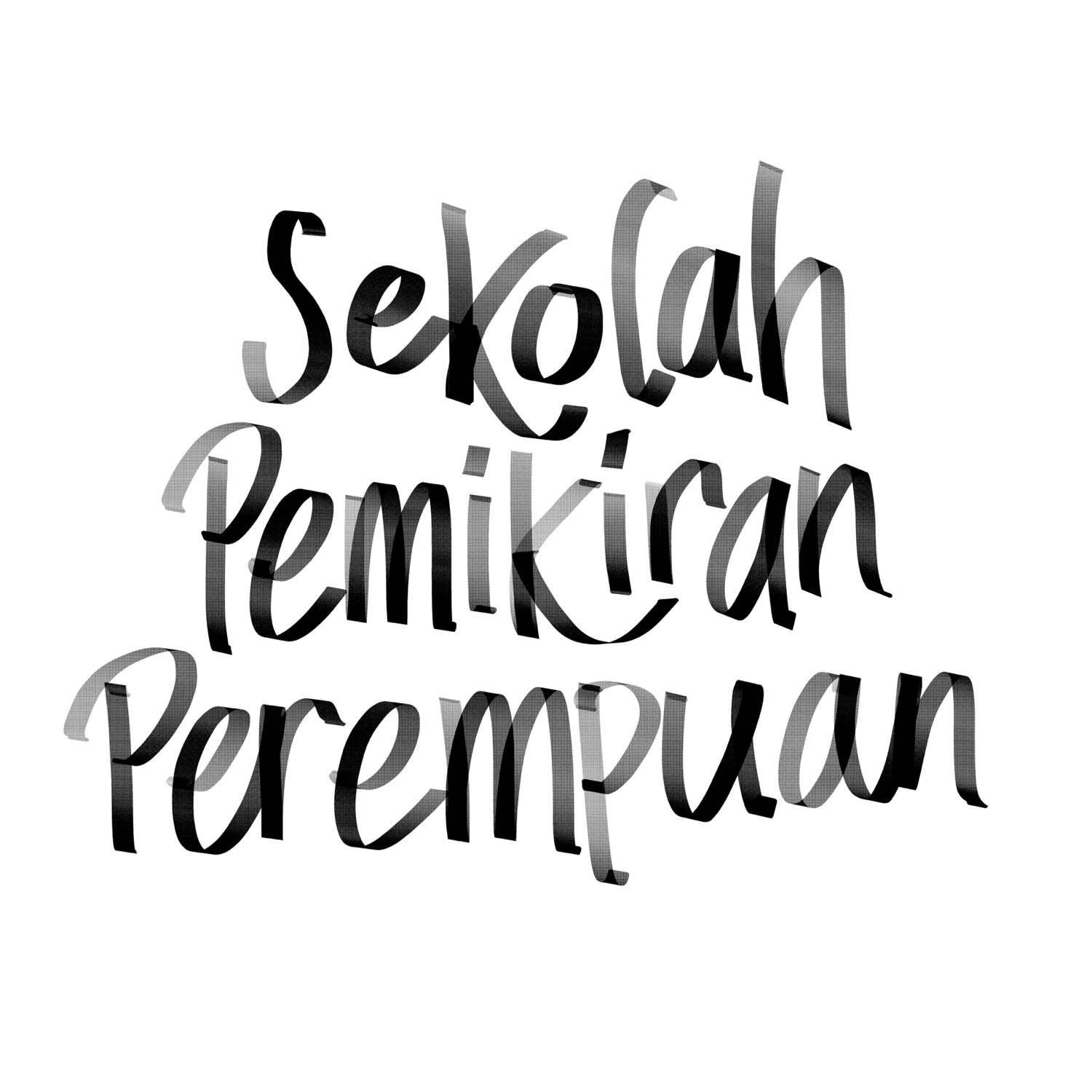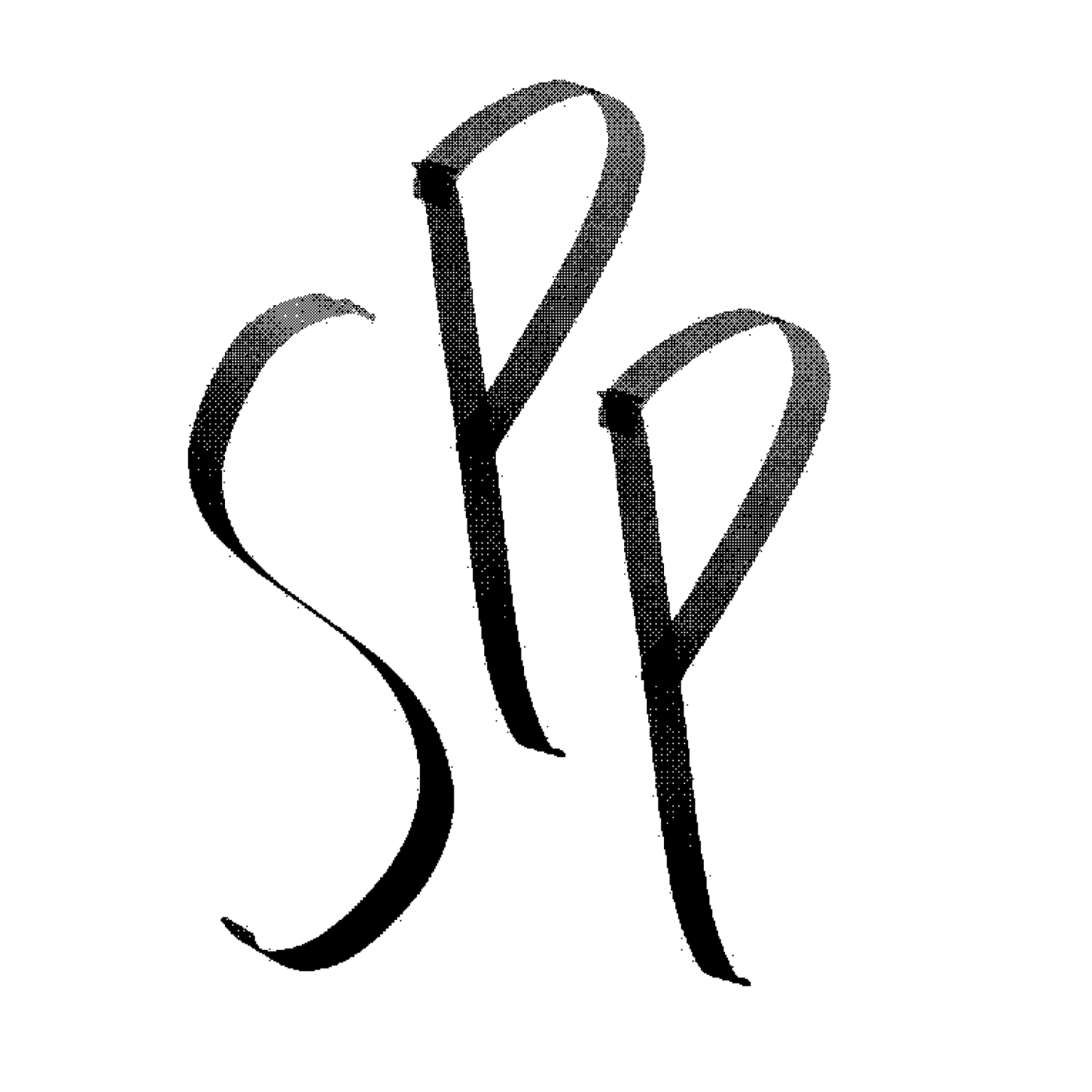SPP Goes to School di MIWF 2024: Pentingnya Sebuah Intervensi
Pada 20 Mei lalu, Sekolah Pemikiran Perempuan (SPP) berkolaborasi dengan Makassar International Writers Festival (MIWF) 2024 menyelenggarakan program SPP Goes to School—sebuah workshop pengenalan para pemikir perempuan kepada anak-anak muda di sekolah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di SMA Negeri 9 Gowa, dihadiri oleh 24 siswa perempuan dari kelas X dan XI; serta diampu oleh tiga perwakilan SPP, yaitu Margareth Ratih Fernandez, Reski Ciki, serta Ilda Karwayu.
Sejatinya, program ini lahir sebagai perpanjangan napas dari Seri Pemikiran Puan—serangkaian tulisan hasil belajar di Ruang Kelas Sekolah Pemikiran Perempuan. Tulisan tersebut memuat biografi serta warisan pemikiran para pemikir perempuan; dan seluruh tulisan dapat dibaca secara gratis oleh siapa saja yang mengakses situs pemikiranperempuan.org. Namun, berhadapan dengan tingginya gelombang informasi di internet, ditambah dengan algoritma yang bekerja sesuai preferensi pengguna internet, tulisan-tulisan tersebut memerlukan intervensi supaya lebih cepat terakses.
Kita dapat melihat bahwa langkah intervensi tersebut tepat dilakukan setelah mengobrol cukup lama dengan murid-murid perempuan di SMA Negeri 9 Gowa sepanjang SPP Goes to School berlangsung. Sebagai pembuka, seluruh murid diminta membentuk satu lingkaran besar; tersedia satu bola mainan—terbuat dari kertas bekas yang diremas membentuk bola—yang akan dilemparkan ke salah satu murid. Barang siapa mendapat lemparan bola, ia mesti menangkap bola tersebut, dan menyebutkan satu perempuan idolanya. Mereka banyak menyebut nama-nama yang kerap muncul di media sosial, seperti penyanyi populer atau influencers. Selain itu, tak sedikit pula yang menyebut nama ibu yang mengasuh mereka, atau pun guru mereka di sekolah. Motivasi para murid perempuan mengidolakan nama-nama yang disebutkan tiada lain adalah ingin jadi seperti mereka ketika dewasa nanti.
Melalui percakapan di atas, kami membaca bahwa di dunia nyata, ibu dan guru—sebagai orang tua di sekolah—punya peran vital sebagai role model. Pun, sama halnya dengan sejumlah nama yang mereka kenal dari dunia maya: tindak tanduk idola bakal jadi acuan bersikap serta berpikir. Di titik inilah keyakinan kami tentang pentingnya intervensi referensi kepada para murid semakin kuat.
Selanjutnya, empat pemikir perempuan yang diperkenalkan dalam workshop ini adalah Charlotte Salawati (asal Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara), Saparinah Sadli (asal Kendal, Jawa Tengah), Saadah Alim (asal Padang, Sumatera Barat), dan Marianne Katoppo (asal Tomohon, Sulawesi Utara). Keterbatasan waktu, yang hanya dua jam, menjadi salah satu pertimbangan mengapa hanya memilih empat nama. Kami ingin jumlah yang sedikit ini memantik rasa ingin tahu para murid untuk mengenal lebih banyak pemikir perempuan Indonesia.
Pengenalan keempat pemikir perempuan dilakukan bergiliran. Kami bertiga membacakan sedikit biografi mereka, menceritakan latar belakang keluarga dan pendidikan mereka, lalu menjabarkan warisan pemikiran yang penting untuk diperbincangkan lebih luas. Satu hal menarik pada sesi ini adalah keterkejutan para siswa terhadap Charlotte Salawati yang tak lain adalah Salawati Daud. Bagi orang-orang Makassar, nama Salawati Daud tidaklah asing sebab beliau merupakan Walikota Makassar—sekaligus perempuan Indonesia pertama yang menduduki jabatan ini—periode 1949-1950. Kisah Charlotte Salawati adalah satu dari sekian banyak contoh pembelokan narasi sejarah pemikir perempuan.
Sembari bergiliran memperkenalkan, kami menyiapkan potongan-potongan informasi tentang Charlotte Salawati, Saparinah Sadli, Saadah Alim, dan Marianne Katoppo. Seluruhnya ditandai menggunakan empat warna berbeda dan diletakkan di satu meja secara acak. Setelah sesi pengenalan selesai, para para murid dibagi menjadi empat kelompok berdasarkan nama-nama pemikir perempuan Indonesia tersebut. Sesudah itu, satu orang perwakilan kelompok diminta mengumpulkan informasi yang terkumpul acak di meja depan kelas.
Setiap kelompok lalu merancang infografik pemikir perempuan yang mereka dapatkan. Mereka bebas menambahkan ilustrasi atau pun informasi tambahan hasil googling di internet. Selain itu, masing-masing kelompok ditugaskan membuat lima pertanyaan terkait pemikir perempuan tersebut; pertanyaan yang sekiranya tidak mereka dapatkan jawabannya di internet. Kami senang antusiasme para murid tampak dari cara mereka menggarap infografis di kertas karton (secara berkelompok) serta daftar pertanyaan yang terkumpul.
Pada awalnya, kami meminta para murid meletakkan gawai di meja depan kelas supaya perhatian mereka fokus pada pengenalan pemikir perempuan dan aktivitas kelompok. Pada sesi pengenalan, ia berjalan efektif, tapi ternyata di sesi aktivitas kelompok tidak demikian. Belakangan kami menyadari bahwa akses internet barangkali dibutuhkan untuk menggali lebih dalam informasi terkait para pemikir perempuan—sebab kami pun tak menjabarkan seluruhnya di sesi pengenalan.
Sayangnya, pemberian akses itu tak hanya membuka jalan bagi para murid menuju informasi tentang para pemikir perempuan tersebut, tapi juga “menguji” fokus mereka untuk tidak mengakses informasi selain yang sedang diperbincangkan. Temuan ini kami kantongi sebagai bahan refleksi workshop; ke depannya, perlu ada siasat supaya fokus tetap prima pada topik perbincangan.
Aktivitas beranjak ke pembahasan ragam pertanyaan dari para peserta. Satu pertanyaan yang bagi kami penting dibahas saat itu adalah—kira-kira berbunyi begini, “Apakah kita harus berasal dari keluarga menengah untuk bisa menghasilkan pemikiran seperti keempat pemikir perempuan ini?”
Pertanyaan di atas mengarah pada kesadaran atas privilese yang kita atau orang lain miliki. Penting untuk menyadari hal tersebut, sebab menghasilkan pikiran-pikiran bernas serta bergerak mengadvokasi sebuah masalah memerlukan ekosistem yang suportif. Charlotte Salawati, Saparinah Sadli, Saadah Alim, dan Marianne Katoppo, lahir dan tumbuh dalam didikan keluarga yang mendukung mereka belajar sesering mungkin.
Berbekal pengetahuan dan perangkat berpikir yang empatik, mereka mampu membaca masalah yang ada di masyarakat kala itu, seperti sempitnya kesempatan berpolitik bagi perempuan, tafsir kitab suci yang intimidatif terhadap perempuan, ketidakmerataan akses pendidikan bagi anak-anak perempuan, dll. Oleh karenanya, mereka mengupayakan penyebaran pengetahuan melalui tulisan-tulisan. Tak hanya itu, mereka pun bergerak secara kolektif bersama perempuan lainnya; juga menjelajahi belahan dunia lain untuk mengasup serta menguji pengetahuan diri. Para pemikir perempuan sadar bahwa ilmu mereka, serta gerakan yang dilakukan, penting sebagai salah satu solusi dari berbagai masalah di masyarakat.
Beralih kepada para peserta workshop, kami lantas melakukan refleksi terhadap hidup masing-masing. Apakah saya termasuk yang punya privilese?
Kami pun bersepakat bahwa mengenyam pendidikan adalah salah satu privilese yang dimiliki para murid SMA. Kami membahas apa yang menarik untuk dilakukan anak-anak SMA supaya lebih berwawasan. Sejalan dengan zamannya, mereka bisa memulai dari mana saja; salah satunya adalah mengikuti akun-akun media sosial yang mengajak mereka belajar. Asupan konten alternatif—lain dari yang biasa mereka asup—pun diharapkan dapat memperluas cakrawala wawasan mereka. Dalam jangka panjang, bagi para murid yang gemar menciptakan konten kreatif di media sosial, bakal menciptakan konten yang lebih menantang berpikir—tidak sekadar menghibur belaka.
Di akhir kegiatan, SPP, bekerja sama dengan Penerbit Marjin Kiri, menyumbangkan buku Yang Terlupakan dan Dilupakan sejumlah empat eksemplar ke perpustakaan SMA Negeri 9 Gowa sebagai manifestasi kerja merawat pengetahuan. Terima kasih kepada MIWF serta BASAsulsel Wiki yang telah menjembatani SPP menjalankan SPP Goes to School. Semoga program ini bisa konsisten dijalankan dan diadaptasi oleh semakin banyak gerakan kolektif.