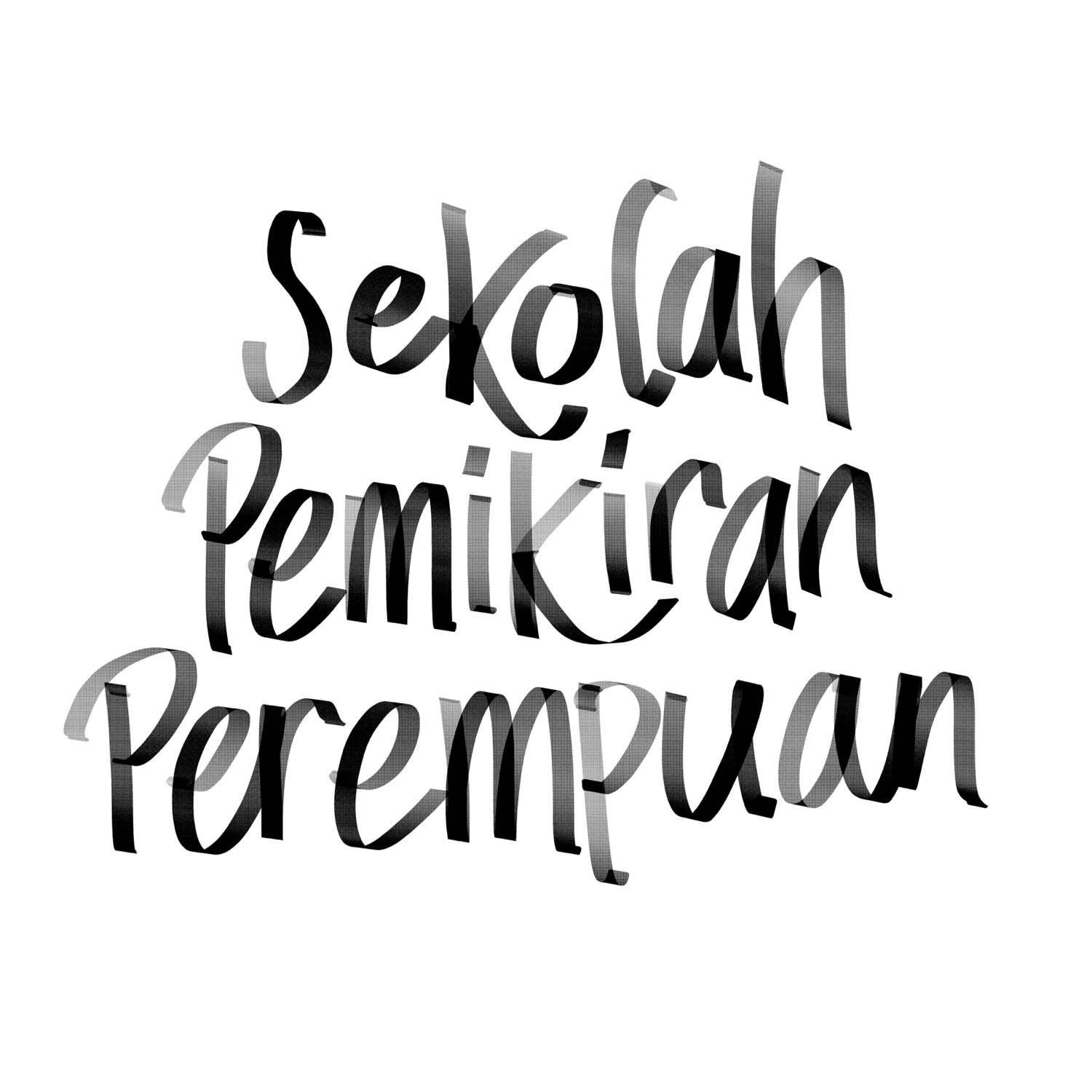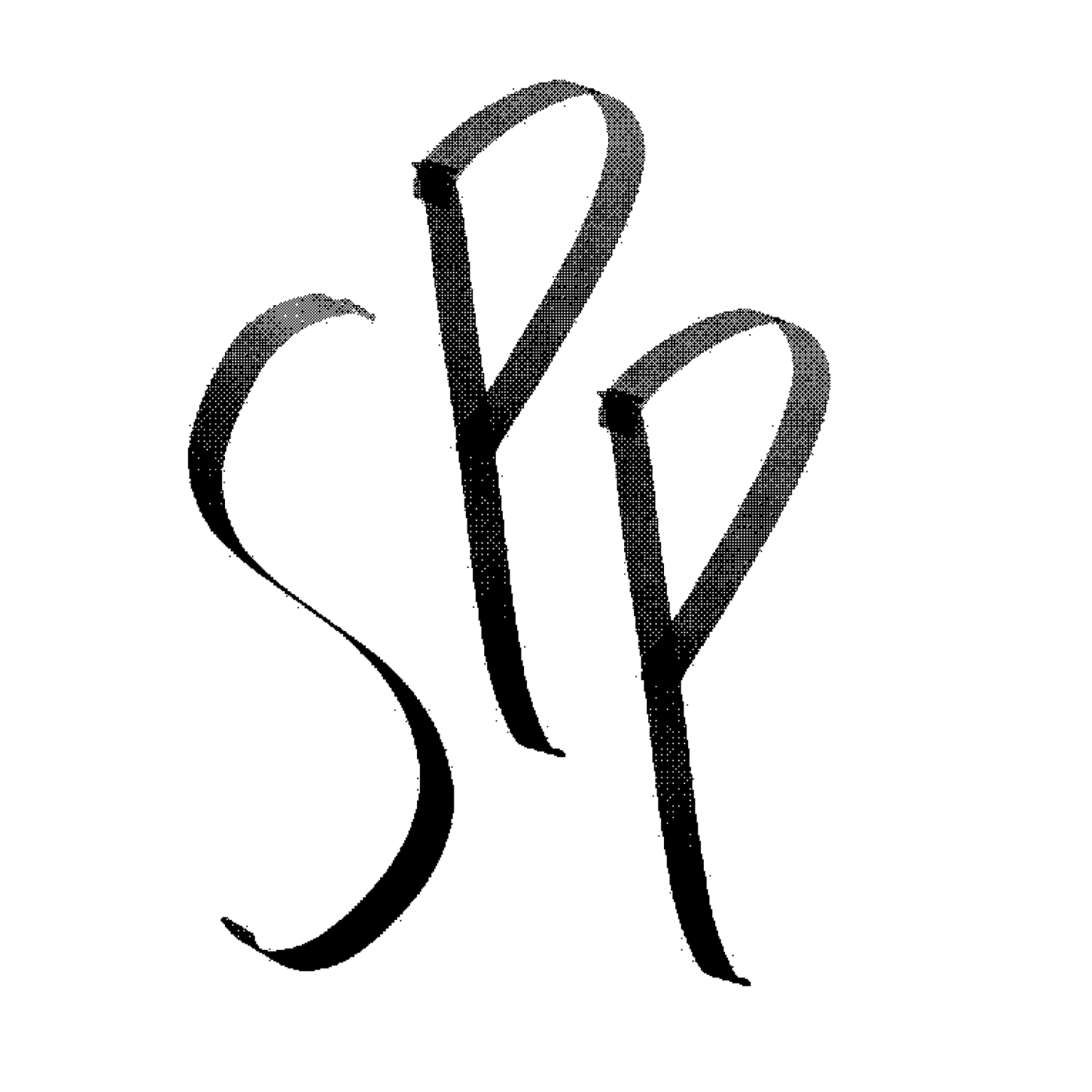Françoise Vergès: Bertempur dengan Cara Merawat, Melawan dengan Cara Membenahi
oleh: Raisa Kamila, Rezky Chiki, dan Putu Sridiniari
“Feminisme dekolonial menerima keberadaan feminisme lain; ia tidak ingin menjadi teori, ia ingin memudahkan aliansi lintas batas dan internasional.”
(Bohrer dalam pengantar A Decolonial Feminism, hal. viii)
Françoise Vergès adalah seorang aktivis politik, kurator independen, produser film, dan akademisi. Pusaran pemikiran Vergès kerap berpijak pada kritik-kritik pascakolonial dan feminisme dekolonial. Vergès bergelar PhD dalam Ilmu Politik dan Kajian Perempuan dari University of California, Berkeley, dan telah menulis banyak buku, di antaranya: Resolutely Black: Conversations with Aime Cesaire (Polity, 2019), The Wombs of Women: Race, Capital, Feminism and Monsters and Revolutionaries: Colonial Family Romance and Metissage (Duke University Press, 2020, 1999), dan A Decolonial Feminism (Pluto Books, 2019).
Vergès lahir di Paris, 23 Januari 1952, lalu tumbuh besar di Pulau Reunion dan Aljazair sebelum akhirnya kembali ke Prancis untuk melanjutkan pendidikan sebagai seorang jurnalis. Dalam wawancaranya dengan PEN International, Vergès menyebutkan bahwa hubungannya dengan Pulau Reunion di masa muda sangat memberi pengaruh pada caranya memahami dunia. Pulau Reunion yang nyaris tak terlihat di peta, di antara Madagaskar dan Mauritius, di tengah Samudra Hindia, membuat Vergès terbiasa dengan kekayaan aroma dan rasa, keberadaan sungai dan gunung berapi, hamparan laut dan badai yang muncul tiba-tiba.
Besar dengan orang tua yang mendedikasikan hidup pada agenda politik komunisme, sejak kecil Vergès mulai membaca buku sejarah, filsafat, dan sastra dari berbagai belahan dunia. Dari pengalaman masa kecilnya pula, ia merasakan bagaimana pemikiran Marxisme mendorong perubahan dan dekolonisasi di Dunia Selatan, di pulau kecil dalam wilayah jajahan Prancis. Keadilan epistemik diperjuangkannya melalui pengamatan bahwa praktik pemberadaban (civilizing mission) adalah warisan politik kolonial yang hingga saat ini masih digunakan untuk melegitimasi penindasan di Global Selatan dan buruh kulit berwarna, perempuan, dan queer yang hidupnya terpinggirkan di Global Utara.
Kerentanan hidup perempuan pekerja kebersihan adalah sumber perenungan utama Vergès, yang ia tuangkan dalam A Decolonial Feminism. Ia mengaitkannya secara struktural sebagai kapitalisme yang ekstraktif. Alih-alih feminisme pemberadaban (civilizational feminism) sebagai gerakan arus utama, ia menawarkan suatu ‘feminisme yang dekolonial’ sebagai senjata perlawanan kontrarevolusioner terhadap sistem kapitalisme yang eksploitatif dan destruktif. Vergès dengan jeli mengaitkan kerja sama sistemik kapitalisme dengan ampas-ampas kolonialisme, rasisme, dan kuasa heteropatriarkal. Dengan kata lain, kapital adalah penjajah, sifatnya heteropatriarkal, dan hampir selalu rasis.
Pada misi pemberadaban, perempuan berkulit putih menggunakan pengalaman mereka, utamanya pengalaman borjuis, sebagai basis pandangan yang membagi dunia menjadi dua: beradab/barbar, hitam/putih, dan laki-laki/perempuan sebagai konsep oposisi biner yang universal. Vergès menambahkan bahwa feminisme semacam ini juga kerap mengandung kecenderungan Islamofobia dan menyandingkan markah-markah Islam, seperti cadar atau hijab, secara sejajar dengan kungkungan opresif. Seiring berjalannya waktu, feminis dan perempuan kulit putih Global Utara menjadi dekat dengan ekstremis sayap kanan ataupun dengan paham neoliberalisme. Kapitalisme pun hanya akan mengintegrasikan feminisme dalam korporasi dengan syarat: ketimpangan antara perempuan dan laki-laki berada di batasan pola pikir atau pendidikan, bukan pada penekanan struktur yang opresif.
Di Indonesia sendiri, berbagai contoh ketimpangan dilanggengkan sebagai hasil reproduksi dan normalisasi sejak zaman kolonial. Poros perputaran modal masih saja berada di Jawa (terutama Jakarta), sehingga kepentingan pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia di seantero Indonesia didasarkan atas kebutuhan pusat. Buruh, baik dalam negeri maupun migran, hidup di bawah kerentanan tanpa perlindungan hukum yang memadai. Orang-orang di luar pusat dan minoritas menanggung berbagai jenis bentuk diskriminasi; rakyat dan kemiskinan dijadikan objek kontestasi politik. Bagaimana kita merenungkan posisi ini di ruang hidup masing-masing? Bagaimana hendaknya kita menyembuhkan diri, memperbaiki sistem? Vergès berulang kali mengingatkan bahwa untuk membuat sistem kapitalis bekerja kita tak perlu satu tubuh, tapi jutaan tubuh. Lantas, bagaimana kita dapat semakin menyadari bahwa variabel dari kapitalisme dan imperialisme adalah fabrikasi tubuh dan alam sebagai objek? Bagaimana dekolonisasi sebagai kerangka kerja membantu kita untuk memikirkan kembali lintasan gerakan perlawanan dan menjauhkan dari pemahaman tentang kebebasan sebagai sesuatu yang tunggal? Bagaimana hal itu dapat membantu kita berpikir secara jamak tentang apa misi selanjutnya?
Spasialitas dalam Ruang Perjuangan
Keterhubungan teknologi membuat gerakan perempuan kian bertumbuh. Representasi perempuan yang semakin majemuk, tentu harus didukung. Ketika perempuan semakin keluar dari jalur yang heteronormatif dan patriarkal, tantangan akan semakin besar. Normalisasi yang menjadi kerangka kehidupan harus diretas menggunakan imajinasi secara terus-menerus. Kehidupan dipenuhi dengan gambaran yang seakan-akan imajinatif tapi sejatinya hanya mengkolonisasi pikiran kita, sehingga, pertanyaan mengenai representasi menjadi penting: apakah representasi tersebut benar-benar diceritakan oleh perempuan, untuk perempuan, dan siapa yang kita sebut “perempuan”? Sejarah yang dimutilasi harus diakui, tapi kita harus tetap hati-hati mengisi kekosongan. Hal ini termasuk perjuangan-perjuangan reparasi oleh perempuan, queer, dan minoritas lainnya. Ia menekankan bahwa jangan sampai tindakan perjuangan sebatas menjadi performativitas baru yang menyesatkan dan malah menjadi “misi penyelamatan” seakan lebih superior karena merasa paling “beradab”.
Dalam esai "Invisible, They ‘Open the City’ " Vergès menggambarkan bahwa, setiap pagi, di setiap kota-kota besar Eropa (terutama yang ia amati di Paris), perempuan-perempuan kulit berwarna berusia paruh baya bekerja membersihkan gedung-gedung perkantoran, gym, dan pertokoan, sebelum akhirnya para pekerja kantoran menjalani keseharian. Oleh sistem kapitalisme, tubuh-tubuh perempuan kulit berwarna yang bekerja membersihkan segala sesuatu tampak tak kasat mata (invisible), meski keringat, kantuk, dan rasa lelah yang mereka alami itu nyata adanya. Sementara tubuh perempuan dan laki-laki kulit putih, yang penuh keringat setelah dari gym atau rasa lelah karena bekerja seharian dianggap ada (visible), lantas dirayakan sebagai “kerja keras” atau “simbol kesuksesan” dalam sistem kapitalisme.
Dengan diagnosis yang jeli, Vergès mengaitkan kata “limbah” dalam kapitalisme dengan trauma yang diwariskan dari masa perbudakan dan kolonialisme. “Limbah mengambang” adalah frasa yang ia tawarkan untuk konsekuensi eksploitasi dan penjarahan tanah serta manusia yang menempatinya. Alih-alih menjawab kebutuhan manusia, ragam rupa perbudakan, kolonialisme, dan kapitalisme justru menciptakan keinginan untuk segala sesuatu yang tidak kita butuhkan, dan merusak akses atas apa yang nyatanya kita butuhkan (udara bersih, air bersih, makanan bersih, kota bersih). Melalui ekses eksploitasi, Vergès seakan menegaskan kembali bahwa revolusi sehari-hari dapat menjadi sumber aktivisme radikal yang diperjuangkan oleh para feminis dekolonial. Tawaran Vergès adalah kritik atas kapitalisme yang berpusat pada reproduksi sosial yang sensitif terhadap gender, kelas dan ras, alih-alih kritik yang sifatnya afterthought dari kritik kapitalisme. Metodenya sederhana: dimulai dari satu elemen untuk membongkar ekosistem politik, ekonomi, kultural, dan sosial agar terhindar dari segmentasi yang seringkali disematkan metode ilmu sosial ala Barat.
"Analisis paling produktif dan mencerahkan dalam beberapa dekade terakhir adalah analisis yang mampu menarik berbagai benang secara bersamaan untuk menggarisbawahi jejaring subjektif dan konkret dari penindasan yang merajut jala eksploitasi dan diskriminasi.”
(Vergès, 2021: hal. 22)
Menamai diri sebagai feminis dekolonial berarti memegang komitmen untuk berjuang, memahami kompleksitas, ambivalensi, tantangan, pengalaman penuh frustrasi; dengan hati terbuka menerima warisan perjuangan para perempuan yang telah datang sebelum kita; mendengar dan mencatat, merajut satu per satu benang-benang opresif yang membentuk jejaring eksploitasi dan diskriminasi.
Meramu Gerakan Radikal-Dekolonial dalam Museum Tanpa Objek
Tak hanya berhenti di tulisan akademis, minat Vergès pada film dan seni rupa menjadi medium untuk membagi pemikirannya bagi publik yang lebih luas. Pada 1996, ia bekerja dengan Isaac Julien, seorang seniman dan pekerja film, dalam “Frantz Fanon, Black Skin, White Mask” . Dalam perhelatan Paris Triennal, yang dikurasi oleh Okwui Enwezor (2012), Vergès turut berperan dalam kurasi The Slave in Le Louvre, An Invisible Humanity, serta menjadi penasihat proyek “Créolité and Creolization”. Ia juga menjadi penulis dalam film Aimé Césaire (2013) dan Maryse Condé (2011). Secara rutin, Vergès bekerja sama dengan seniman, aktivis, maupun akademisi kulit berwarna.
Salah satu gagasan yang ia gaungkan adalah “museum tanpa objek”. Bagi Vergès, kita tidak punya objek tapi kita punya hidup untuk diceritakan. Dalam kesenian, kita tidak harus berpegang pada objek, karena objek dalam sejarah banyak yang sudah dirampas. Seringkali artefak material yang tersisa tak dapat menceritakan kisah-kisah yang terjajah secara utuh. Jejak-jejak perampasan tertutup rumput-rumput liar yang membuat penelusuran kembali terasa sulit dan samar. Gagasan “museum tanpa objek” lahir dari perenungan mengenai peresmian Maison des civilisations et de lunit runionnaise (MCUR) pada 2000 di Pulau Reunion. Permenungannya sejalan dengan perdebatan panjang mengenai identitas nasional, pascakolonial, dan gagasan kreolisasi.
"We would not seek to fill up a void, to compensate for the absence, we would work from the absence, embracing it fully, for we understood that this absence was paradoxically affirming a presence.”
Sejak 1663, hanya sedikit objek yang mampu menjadi saksi bagi masifnya migrasi paksa yang menyebabkan displacement manusia di Pulau Reunion. Tentu saja sejarah tidak mencatat apa pun mengenai hidup mereka. Vergès mengajak kita untuk memaklumi kekosongan ini, an unknown past, guna berpulih bersama. Manusia dalam statusnya sebagai budak adalah sesosok figur politik, bukan hanya manusia yang tak berdaya, tetapi juga yang hidupnya berkontestasi dengan kapitalisme, suatu sistem ekonomi, kultural, dan politis yang eksploitatif terhadap tubuh dan alam. Rasialisasi menyebabkan tubuh terdegradasi menjadi objek. Ekspresi budaya Creol secara radikal mempertanyakan dunia yang digiring ke dalam politik identitas warna kulit. Karena warisan material terampas, warisan immaterial tumbuh berdaya dan berkembang dalam tradisi oral, adat-istiadat, seni pertunjukan, ritual, dan kerajinan tangan. Vergès menawarkan kisah-kisah perjalanan, ritual, rahasia dapur, dan irama melodi untuk membuka setapak baru dalam menelusuri masa lalu. Ia seakan ingin menunjukan bahwa peradaban manusia dan kesejarahan terbentuk dari ragam lapisan yang saling bertumpang-tindih satu sama lain dalam temporalitas dan durasi yang berbeda-beda, bagaimana kelompok-kelompok yang pinggiran memiliki dunia sendiri, aturan, ritual, tradisi, yang diwariskan secara turun-temurun. Begitu menyedihkan, ketika mereka diklaim telah "ditemukan" oleh para penjajah yang membentuk tataran pengetahuan ilmu sosial. “Apa yang ditemukan? Apa yang membuat gestur menyingkap (unmasking, unveiling) ˆbegitu atraktif?” tanya Vergès.
Dengan semangat dekolonisasi terhadap pengetahuan hegemonik yang berbasis penyebaran akademi dan museum yang Eurosentris, Vergès mencontohkan kontekstualisasi kritis dan transmisi budaya Reunion yang didasari bukan hanya untuk "menyelamatkan warisan budaya". Ia melihat museum bukan hanya tempat untuk suatu "budaya yang sudah kuno atau mati", melainkan juga ruang transformatif untuk menumbuhkan gerakan sosial, menantang stereotipe, memberikan alternatif, dan untuk ruang berdiskusi. Dengan kata lain, dapat menangkap semangat budaya masa kini.
“Reality is polymorphic, formed by multiple identities and constant metamorphoses.”
Dalam beberapa kesempatan, Vergès berbicara dan menulis mengenai politik reparasi dan perjuangan. Selain rajin bertanya mengenai masa lampau, apa yang kita miliki di masa kini, dan apa yang ada untuk masa depan, Vergès juga tak henti-hentinya menekankan ekses atau sampah-sampah yang dihasilkan oleh kapitalisme mengorbankan bumi dan manusia-manusianya. Pun secara internal, sampah itu ada pada batin kita masing-masing. Konsekuensi dari sistem saat ini adalah kekosongan, kehilangan, dan alienasi. Ada diskoneksi dengan diri dan lingkungan. Dengan menyadari bahwa kita berada dalam dimensi temporer yang selalu berkelindan dengan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, kita dapat merenungkan kontribusi dalam pergerakan.
Lantas, bagaimana bergerak di antara invisibility dan visibility? Terlihat dan tak terlihat? Kekuatan untuk tak terlihat juga penting. Feminisme tak perlu tokoh atau istilah-istilah yang diklaim perorangan atau kolektif tertentu, kita perlu perjuangan lintas-narasi, lintas-dimensi, ruang-ruang aman yang terbentuk secara otonom. Kita harus lebih sering melempar pertanyaan mengenai sejarah, cara sejarah diceritakan, periodisasi, dan lain-lain. Harus ada kehati-hatian dalam bergerak dan sensitivitas ketika menggunakan kata-kata dan pengetahuan yang selama ini digunakan dalam eksploitasi/militerisasi, yang cenderung maskulin. Perempuan dapat bertempur dengan cara merawat, serta melawan dengan cara membenahi.
Vergès mengingatkan bahwa kerja-kerja perempuan akan terasa seperti mengumpulkan kepingan. Di antara bergerak dan meramu strategi, negosiasi dan diskusi tetap terjadi. Strategi di antaranya dapat berupa sastra, seni (termasuk mengembangkan yang sering dianggap sekadar “hobi”), teater, sinema, makanan, musik, dan penelitian. Karya-karya yang tidak hanya indah, tetapi juga dapat menantang representasi.
Perlawanan tidak harus memiliki hasil final. Ia cenderung unfinished, incomplete. Ungkapan yang sejalan dengan langkah-langkah Vergès agaknya akan berbunyi begini: lakukan apa yang harus kamu lakukan, di mana pun kamu berada, dan niscaya perjuangan ini akan terhubung dengan orang lain.
Kepustakaan
Vergès, F., & Bohrer, A. J. (2021). A decolonial feminism. London: Pluto Press.
Vergès, F., & Olufemi, L. (2021, April 21). A Decolonial Feminism | Pluto Live. Pluto Press. https://www.youtube.com/watch?v=FE9FR1jfo5U&t=308s&ab_channel=PlutoPress
Walker, G., & Vergès, F. (2021, October). Another Imagination, Decolonial and Feminist: An interview with Francois Vergès. Episteme. https://positionspolitics.org/another-imagination-decolonial-and-feminist-an-interview-with-francoise-Vergès/
Vergès, F. (2019, July 25). Françoise Vergès: Capitalocene, Waste, Race, and Gender. The Architectural League. https://www.youtube.com/watch?v=0cw0s0AyQiI&t=763s&ab_channel=TheArchitecturalLeague
Vergès, F. (2019). Capitalocene, waste, race, and gender. e-flux journal, 100.
Vergès, F. (2021). Like a Riot: The Politics of Forgetfulness, Relearning the South, and the Island of Dr. Moreau. https://www.documenta14.de/en/south/25_like_a_riot_the_politics_of_forgetfulness_relearning_the_south_and_the_island_of_dr_moreau
Vergès, F. (2022, February 3). Itinerant Imaginaries Session : The Object of the Feminist Decolonial Archive. British Art Network. https://www.youtube.com/watch?v=tdXMec_Sjhg&ab_channel=BritishArtNetwork
Vergès, F. (2021, April 30). Decolonial Feminisms_ An Interview with Françoise Vergès. PEN Transmissions. https://pentransmissions.com/2021/04/30/decolonial-feminisms-an-interview-with-francoise-Vergès/
Vergès, F. (2016). A Museum Without Objects. In The Postcolonial Museum (pp. 25-38). Routledge.
Vergès, F. (2021, April 30). Museum Without Objects. CriticalTheoryConsortium. https://criticaltheoryconsortium.org/wp-content/uploads/2018/07/Museum_Without_Objects_by_Franc%CC%A7oise_Verge%CC%80s-1.pdf
Vergès, F., Methodology for a Creole Museum, For a Postcolonial Museum of the Living Present, in J. Trant and D. Bearman (eds.). Museums and the Web 2008: Proceedings, Toronto: Archives & Museum Informatics. Published March 31, 2008. Consulted December 4, 2022. http://www.archimuse.com/mw2008/papers/Vergès/Vergès.html