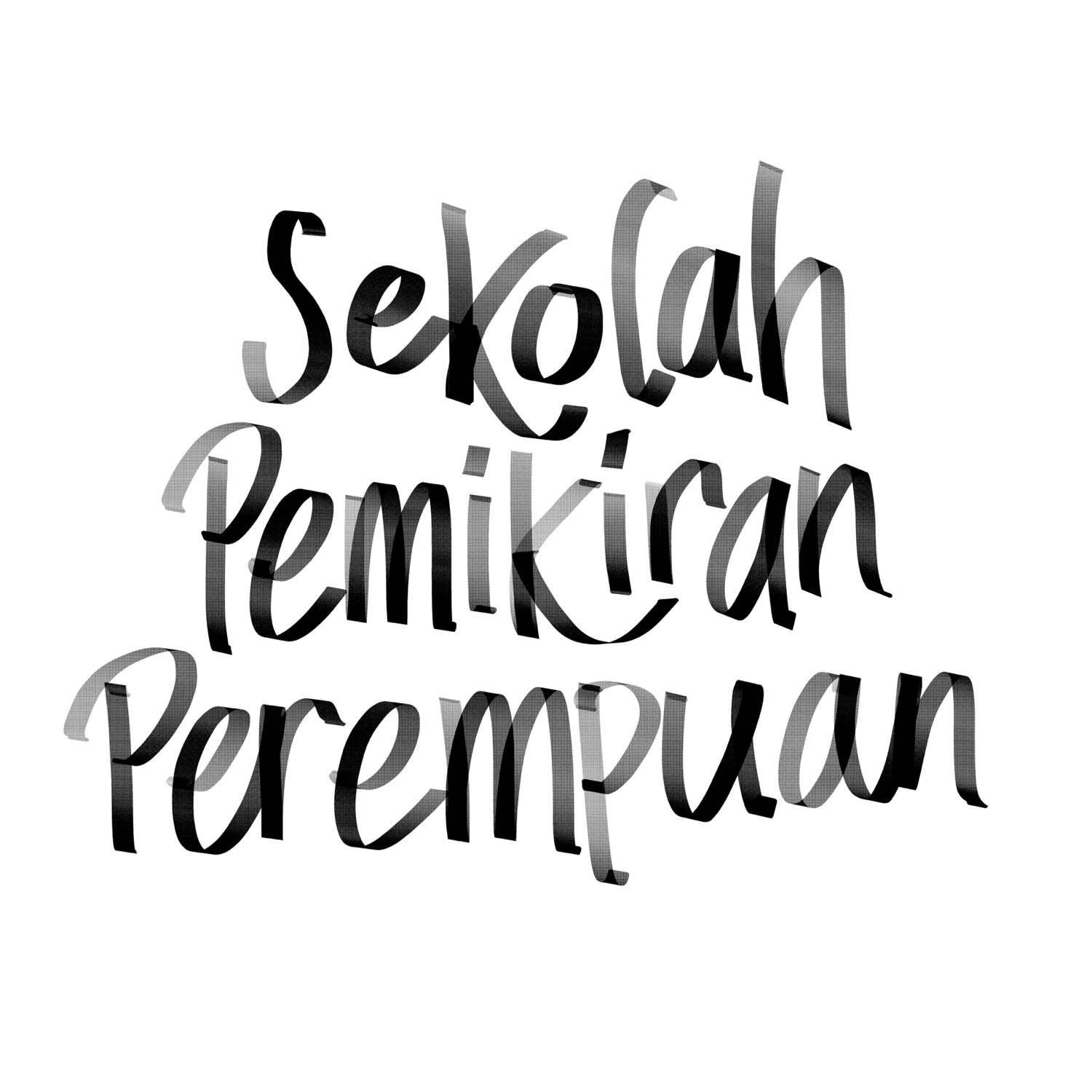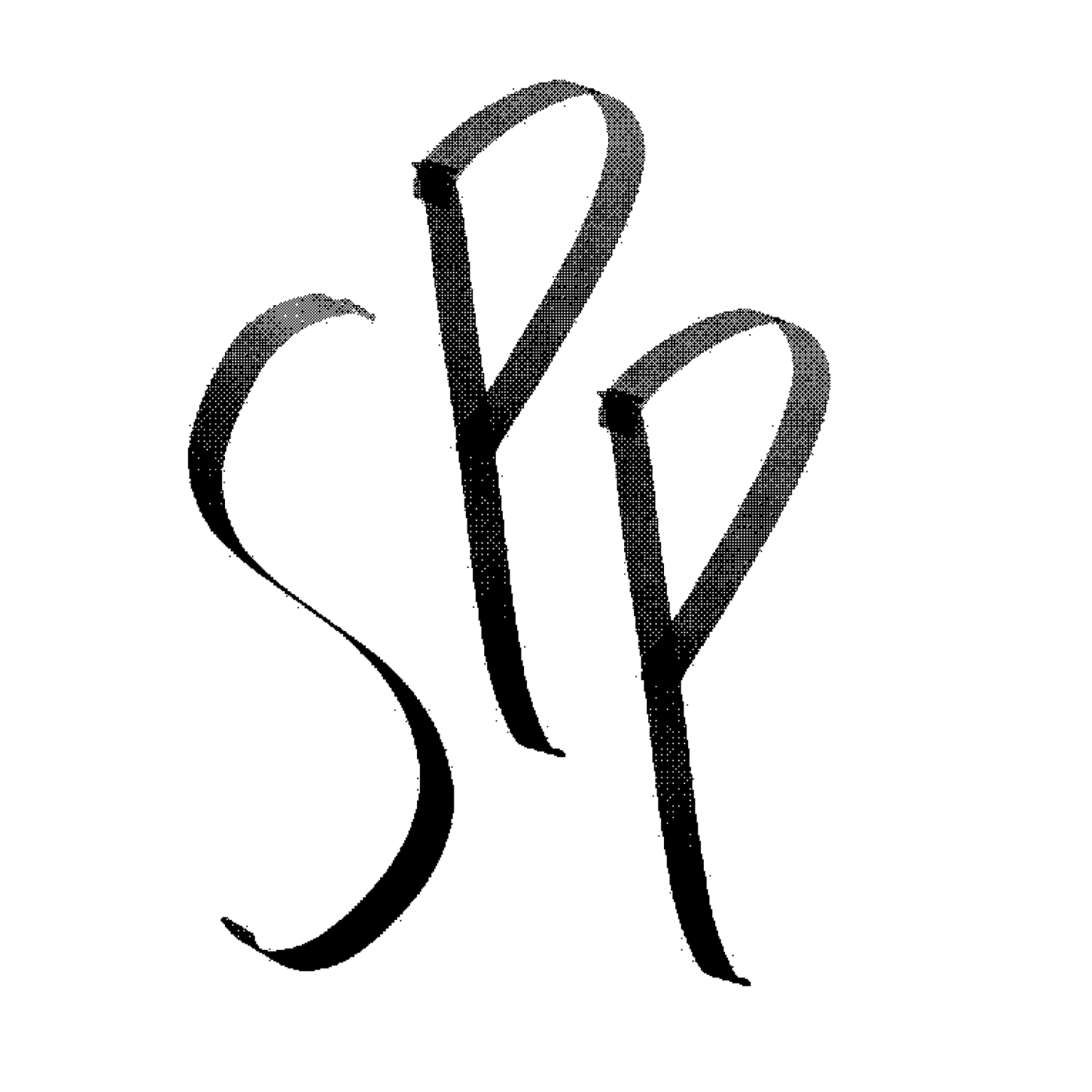Saparinah Sadli: Kiprah dan Pemikirannya
oleh: Fathimah Fildzah Izzati, Luna Kharisma, Maria Pankratia, dan Raudhatul Jannah
Mengenal Sosok Saparinah Sadli
Saparinah Sadli lahir di Tegalsari, Jawa Tengah, 24 Agustus 1927 dari pasangan R.M. Soebali, Bupati Kudus, dengan R.A. Mintami. Sepanjang hidupnya, Saparinah1 dikenal sebagai akademisi, motivator, mediator dan penggerak masyarakat, sekaligus pejuang HAM, khususnya menyangkut hak-hak perempuan.
Pada 1954, Saparinah menikah dengan Mohammad Sadli, seorang dosen muda di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, yang kemudian menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja (1971-1973) dan Menteri Pertambangan (1973-1978).
Saparinah meniti karier sebagai akademisi di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI), tempat ia meraih gelar doktor di bidang yang sama. Kariernya terus meningkat hingga ia diberi amanat sebagai Dekan Fakultas Psikologi UI pada periode 1976-1981. Empat tahun setelahnya, Saparinah juga dikukuhkan menjadi Guru Besar universitas dengan pidato pengukuhan yang berjudul Psikologi di Indonesia: Sumbangannya Kepada Masyarakat Serta Masalah-Masalah dalam Perkembangannya.
Latar belakang dan kehidupan Saparinah ini tentu membuatnya memiliki privilese lebih dari para perempuan lainnya. Namun, ia menggunakan privilese tersebut dengan sangat baik untuk kepentingan kemanusiaan, khususnya perjuangan hak-hak perempuan.
Gagasan-Gagasan Saparinah Sadli tentang Analisis Gender
Banyak gagasan/pemikiran dan kiprah yang ditorehkan Saparinah semasa hidup. Dalam tulisan ini, kami hendak menyoroti kiprah dan pemikiran/gagasan Saparinah, khususnya di tengah dinamika perkembangan ilmu pengetahuan yang penuh dengan tantangan pada masa Orde Baru. Secara spesifik, kami ingin membahas Saparinah ke dalam dua fokus, yakni: pertama, peran Saparinah mengenalkan kesadaran baru tentang analisis gender. Analisis tersebut menjadi penting karena berbeda dari yang dikenal masyarakat secara umum ketika itu. Kedua, kontribusi dan warisan Saparinah dalam gerakan perempuan serta dunia akademik di Indonesia hingga saat ini.
Sebagaimana diketahui, masa Orde Baru adalah masa yang menantang bagi gerakan sosial dan dunia akademik di Indonesia. Di bawah rezim otoritarian Soeharto, teknokrasi menjadi kata kunci dan pengetahuan-pengetahuan yang “berbeda” dianggap subversif. Pengetahuan mengenai analisis gender adalah satu di antaranya. Keberpihakan yang tinggi pada perkembangan ilmu pengetahuan membuat Saparinah tak gentar memperkenalkan analisis gender yang dapat dikatakan tidak familier ketika itu. Analisis gender a la Saparinah tidak dapat dilepaskan dari pendekatan psikologi sebagai bidang kajian yang ia dalami. Melalui kajian ilmu psikologi inilah ia mendalami terminologi perbedaan individual yang membawanya pada konsep perbedaan gender. Ia menentang konsep Freud “anatomi adalah takdir” (anatomy is destiny) yang mencampuradukkan kenyataan biologis dan hubungan gender sekaligus meletakkan laki-laki dan perempuan dalam posisi tidak setara. Bertolak dari hal tersebut, ia mengkritisi konstruksi sosial mengenai perempuan yang dianggap oleh masyarakat patriarkis memiliki “takdir kodrati”, yakni hanya boleh berada di ruang domestik. Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya bersifat biologis, melainkan semua orang telah tergenderkan.2 Sejak dilahirkan, perempuan dan laki-laki telah diperlakukan berbeda sesuai identitas dan peran gendernya oleh orang tua maupun lingkungan terdekatnya.
“Contohnya, di lingkungan budaya kita, sifat lembut, sabar, berpenampilan rapi, dan senang melayani kebutuhan orang lain dianggap sebagai karakteristik positif dari feminitas. Perilaku tersebut diperkuat dengan cara anak perempuan didandani dan mainan yang dibelikan. Itu masih ditambah dengan peringatan bila si anak perempuan berperilaku yang oleh lingkungannya dianggap tidak feminin. Artinya, sebagai anak perempuan, ia belajar sifat-sifat yang dianggap pantas sebagai perempuan.”
(Saparinah Sadli, Identitas dan Peran Gender dalam buku Berbeda Tetapi Setara, 2010)
Beberapa kajiannya dengan cermat merefleksikan pengalaman dirinya semasa anak-anak hingga dewasa, seperti yang ia tulis dalam esai-esainya “Perempuan di Mata Remaja Putri”, “Persiapan untuk Masa Senja”, dan “Menuju Jakarta yang Ramah Lansia”.3 Bersama para pemikir lainnya, Saparinah menulis dan menjadi editor buku Di Atas 40 Tahun (Sinar Harapan, 1984) yang berisi kajian atas tahapan hidup manusia dalam rentang usia dewasa madya, yaitu 40-60 tahun. Dalam buku tersebut, esai Saparinah membahas kondisi psikologis perempuan yang sedang mengalami proses menjadi tua. Ia juga menguraikan pengalaman dan perjalanannya sebagai lansia dalam buku Menjadi Sehat dan Produktif di Usia Lanjut (Kompas, 2014) sebagai sebuah penghayatan subjektif atas dirinya.
Kajian-kajian Saparinah yang berangkat dari refleksi perjalanan hidupnya menjadi penting karena kajian tersebut kemudian dipantulkan pula pada kenyataan kehidupan perempuan di Indonesia, terutama pada persoalan bagaimana perempuan mengembangkan identitas dirinya. Melalui artikelnya “Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Jati Diri Perempuan” (Sunan Kalijaga Press, 2001), ia menceritakan amatannya mengenai pemikiran dan pengalaman R.A Kartini yang merefleksikan kehidupan perempuan, khususnya di Jawa. Faktor kodrat dengan ketat dijadikan alasan untuk menentukan apa yang perlu diajarkan bagi pengembangan perilaku perempuan (Saparinah, 2010: 41). Uraian Kartini tersebut mengantarkan Saparinah untuk merefleksikan pengalamannya sebagai perempuan. Seturut amatan Saparinah, perempuan membangun identitasnya melalui apa yang sejak mula diajarkan dan dipilihkan untuknya.
“Supaya pemikiran saya (baca: perempuan) dapat dipahami oleh orang lain, saya diharapkan berperilaku sesuai gender. Selain itu saya juga belajar dikotomi feminin-maskulin, rasional-intuisi, publik-domestik, dan adanya asosiasi simbolis antara gender dan berbagai bidang lain dalam kehidupan sehari-hari.”
(Saparinah Sadli. “Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Jati Diri Perempuan” dalam Berbeda tetapi Setara, 2010)
Kategori-kategori yang direfleksikan Saparinah juga menentukan citra “benar/baik” sebagai perempuan dan laki-laki di masyarakat, yang kemudian menempatkan yang “maskulin” lebih tinggi nilai sosialnya daripada yang “feminin”, sehingga pada akhirnya perempuan ditempatkan—atau bahkan menempatkan dirinya—inferior terhadap laki-laki. Ketegangan tersebut dialami perempuan sejak anak-anak, ketika menempuh masa pendidikan, hingga kembali menerjunkan diri pada kenyataan sosial masyarakat. Proses tersebut secara terus-menerus melanggengkan diskriminasi dan penindasan seksis pada perempuan.
Analisis tentang perbedaan gender memperkuat pemahaman Saparinah mengenai feminisme sebagai sebuah kesadaran atas ketimpangan antara laki-laki dan perempuan yang sangat merugikan perempuan. Dalam konteks Indonesia, feminisme baginya merupakan sebuah prinsip untuk saling menghormati perbedaan sebagai bagian dari kesadaran kebhinekaan. Sebagai perwujudan pemikirannya, Saparinah mengenalkan konsep “kemitrasejajaran” yang mengandung arti bahwa hubungan gender harus berlangsung setara, bahwasanya salah satu gender tidak merasa lebih baik dari yang lain (Saparinah, 2010: 51). Melalui konsep ini pula, ia membukakan kemungkinan untuk mendukung pengembangan jati diri perempuan yang positif, serta melakukan reevaluasi mitos dan stereotipe atas perempuan.
Kontribusi Saparinah Sadli dalam Dunia Akademik dan Gerakan Perempuan di Indonesia
Keberanian Saparinah dalam mendobrak pewajaran budaya patriarki pada masa itu pun tidak berhenti sampai di situ. Pada 1989, ia mendirikan Kajian Wanita di UI yang merupakan pusat kajian wanita pertama di Indonesia. Pada 1998, ia juga turut mendirikan Komnas Perempuan. Pemikiran/gagasan serta kontribusi-kontribusi penting dan berharga Saparinah di dunia akademik dan gerakan perempuan di Indonesia inilah yang hendak kami rayakan dalam tulisan ini.
Sejak November 1990 hingga Mei 2000, Saparinah diberi kepercayaan oleh Rektor Universitas Indonesia untuk memegang tampuk kepemimpinan Program Studi Kajian Wanita Pascasarjana UI. Kajian perempuan atau women’s studies telah menjadi fenomena global yang berkembang pesat sekitar tahun 1960-an, terutama di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Saparinah sendiri telah menelaahnya melalui esai berjudul “Studi Wanita: Pengembangan dan Tantangannya.”4 Dalam esai tersebut, Saparinah menjelaskan berbagai pro dan kontra dalam perkembangan women’s studies atau kajian perempuan, seperti kekhawatiran bahwa perjuangan memajukan nasib perempuan akan tenggelam di bawah perdebatan akademik semata, hingga pandangan positif mengenai kajian perempuan yang menunjukkan perjuangan untuk merefleksikan pengalaman perempuan yang berbeda-beda di setiap lini.
Melihat polemik mengenai kajian perempuan dalam wacana global, tak mengherankan jika perjalanan awal Program Studi Kajian Wanita ini juga mengalami banyak kendala dan tantangan, terutama karena keraguan para akademisi akan pohon ilmu yang digunakan Kajian Wanita. Stigma yang dilekatkan pada identitas “feminis” juga menyelimuti hari-hari Saparinah sepanjang perjalanan memegang tampuk kepemimpinan ini. Pada saat itu, istilah gender apalagi feminisme masih asing bagi para akademisi maupun masyarakat umum di Indonesia.
Pada titik inilah, Saparinah kemudian mencari cara agar dapat mengaplikasikan sistem yang tepat untuk menyampaikan berbagai materi tentang kajian perempuan. Salah satu cara yang digunakan untuk memberikan fondasi dan pengertian secara tepat kepada para mahasiswa angkatan baru kala itu adalah dengan mengadakan Latihan Sensitivitas Gender selama lima hari berturut-turut. Program tersebut sangat membantu para mahasiswa baru yang berasal dari berbagai latar belakang bidang ilmu sehingga lebih mudah memahami materi-materi terkait gender.
Saparinah juga menyadari pentingnya meningkatkan mutu/kualitas para pengajar dan staf Kajian Wanita di UI demi mengatasi berbagai keterbatasan. Ia pun berinisiatif untuk membuka program kerja sama dengan Memorial University, Kanada pada periode 1992-1996. Dalam refleksi yang ia tuliskan bersama Marilyn Porter (1999), terlihat bahwa visi Kajian Wanita UI untuk mengembangkan Kajian Wanita Indonesia “yang sesungguhnya” menghadapi banyak tantangan, terutama untuk mengenali kondisi perempuan di Indonesia melalui perspektif feminis dalam struktur dan budaya Indonesia (termasuk dengan melihat ulang sejarah pergerakan perempuan di Indonesia), sedangkan pengetahuan yang mencakup teori dan kajian mengenai feminisme banyak didapatkan dari barat (western feminism) seturut dengan persoalan-persoalan dalam konteks budaya barat beserta segala gejolak dan perkembangan-perkembangannya. Kerja sama yang dibangun dengan Memorial University ini telah membuka banyak dialog kritis sebagai langkah awal Kajian Wanita UI untuk mengembangkan visi tersebut.
Selain itu, bersama mahasiswa dan rekan-rekannya di Program Kajian Wanita—juga dengan PKP2 (Pusat Kajian dan Perkembangan Perempuan) di Universitas Djuanda serta universitas-universitas lainnya—Saparinah terus mengembangkan riset berbasis kajian perempuan dengan tujuan agar pengalaman serta kehidupan perempuan (beserta permasalahan-permasalahannya) dapat lebih kasat mata. Sebagaimana yang ia pelajari dari Shulamit Reinharz, riset-riset mengenai perempuan tentu saja diarahkan oleh teori-teori feminisme, dengan menjadikan feminisme sebagai sebuah perspektif, bukan metode. Artinya, periset feminis menganggap bahwa pendekatan yang dipilih adalah suatu perspektif yang berdasarkan pada metode-metode tertentu dalam pelaksanaan suatu penelitian (Saparinah, 2010: 75). Perspektif beragam terkait definisi feminisme pada saat yang sama membutuhkan metode yang beraneka ragam demi dapat memahami perempuan. Tentu saja, dalam konteks itu, Saparinah tidak berkutat pada metode dalam pengertian riset konvensional yang mengasumsikan objektivitas absolut.
Dengan demikian, periset dapat menggunakan berbagai macam pendekatan yang secara sengaja melibatkan diri periset dan berangkat dari pengalaman personal untuk mendekati permasalahan. Tentu saja, ini dianggap melanggar ketentuan riset konvensional yang menganggap kenetralan sebagai bentuk dari objektivitas. Namun, hal itu ditujukan untuk melibatkan responden dan demi menghindari eksploitasi, juga melibatkan pembaca laporan untuk menumbuhkan hubungan/empati terhadap apa yang sedang diteliti. Riset-riset ini diharapkan dapat membuat perubahan sosial yang lebih berkeadilan gender serta membuka kritik berkelanjutan atas konsep-konsep yang non-feminis atau melanggengkan diskriminasi seksis.
Menurut Saparinah, universitas dan lembaga-lembaga pendidikan yang menjadi pusat pengembangan studi pelbagai bidang ilmu semestinya dapat lebih berperan dalam mengkaji permasalahan konkret yang dihadapi perempuan—tentunya dengan menimbang kesejarahan gerakan perempuan yang teramat panjang. Metodologi yang dipilih pun harus mengikuti kaidah-kaidah ilmiah yang berkembang. Salah satunya adalah dengan memilih pendekatan interdisipliner, yang dimaksudkan agar kajian terhadap permasalahan-permasalahan perempuan dapat melampaui batas-batas disiplin ilmiah tertentu. Pengalaman perempuan yang kompleks menuntut peneliti untuk dapat melihatnya tidak semata berdasar satu disiplin keilmuan saja, tetapi dapat melihat kemungkinan persimpangannya dengan disiplin keilmuan yang lain, termasuk juga dengan latar belakang bidang ilmu peneliti yang berbeda-beda. Itulah mengapa pendekatan yang digunakan ini sedikit-banyak mengguncang kemapanan pohon ilmu yang mengutamakan jalur linear keilmuan.
Pendekatan interdisipliner juga diterapkan mengingat perempuan adalah makhluk biopsikososial; yang dibesarkan dengan berbagai dimensi nilai, baik sosial-budaya-agama, yang umum berlaku ataupun yang secara khas diterapkan padanya karena ia berjenis kelamin perempuan. Semua nilai itu secara kompleks akan membentuk identitas dan peran gender, sekaligus memberi pengaruh pada sikap, perilaku, dan pilihan-pilihan perempuan dalam hidupnya. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa gender adalah sebuah konstruksi sosial yang tidak absolut. Maka, hal-hal ideal yang dikonstruksikan dan dibebankan—atau dapat disebut stereotipe—pada perempuan sebenarnya adalah sebatas persepsi hegemonik di tengah masyarakat.
Di institusi pemerintahan, Saparinah juga berjasa besar terhadap pendirian Komnas Perempuan. Lembaga tersebut berhasil terbentuk setelah melalui proses yang berliku. Bermula dari peristiwa Mei 1998, perempuan Indonesia dengan garis keturunan Tionghoa menjadi korban pemerkosaan yang sistematis. Tidak tinggal diam, Masyarakat Anti Kekerasan terhadap Perempuan (selanjutnya disebut MAKtP) menuntut pertanggungjawaban negara. Tuntutan tersebut dimuat dalam Signatory Campaign—sebuah surat yang mencakup permintaan agar negara menginvestigasi, menghukum pelaku kekerasan seksual, dan meminta maaf kepada para korban. Sayang, Signatory Campaign yang sudah ditandatangani oleh 4.000 perempuan tersebut tidak digubris pemerintah.
Alih-alih menaungi, negara justru menyangkal fakta dengan menyatakan bahwa tidak ditemukan satu pun korban perkosaan dalam peristiwa tersebut. Hal ini disampaikan oleh Panglima TNI, Wiranto, dan ditayangkan stasiun televisi nasional. Tidak berhenti sampai di situ, MAKtP kembali bersiasat. Kali ini, kelompok tersebut menghubungi 22 orang tokoh perempuan senior, termasuk di antaranya Saparinah. Harapannya, 22 perempuan tersebut dapat menuntun pada “jalan ninja” untuk bertemu Presiden, yang saat itu di bawah kepemimpinan B.J. Habibie. Saparinah yang mengetahui pernyataan Wiranto, sontak meminta MAKtP menarik surat yang telah diajukan kepada Panglima TNI dan meminta surat baru ditujukan langsung kepada Presiden B.J. Habibie.
Pucuk dicinta ulam pun tiba, pada 15 Juli 1998, Presiden Habibie menerima audiensi bersama MAKtP yang diwakili oleh Ny. Hartarto, Ita Fatia Nadia, Shinta Nuriyah, Saparinah Sadli, Kuraisin Sumhadi, Mayling Oey, Mely G. Tan, Kamala Chandrakirana, dan Smita Notosusanto.5 Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut, Presiden merilis konferensi pers di media mengenai permintaan maaf atas kejadian yang menimpa korban. Di lain pihak, banyak yang tidak menerima pengakuan tersebut dan jajaran aparat negara lagi-lagi melakukan pelbagai penyangkalan atas kasus-kasus perkosaan yang terjadi. Pada 23 Mei 1998, Presiden B.J. Habibie membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menyelidiki kasus tersebut. Saparinah ikut tergabung di dalamnya bersama para feminis antara lain Nursyahbani Katjasungkana, Ita Fatia Nadia, dan Ruth Indiah Rahayu.
Singkat cerita, sebagai perpanjangan tangan dari MAKtP, Saparinah berkomunikasi secara intensif dengan Presiden, baik ketika pemaparan bukti pemerkosaan yang telah ditemukan TGPF hingga mengusulkan pembentukan Komisi Nasional yang bergerak dalam isu perempuan. Tidak main-main, Saparinah dan MAKtP bahkan membuat prasyarat bahwa lembaga tersebut haruslah bersifat independen. Usulan tersebut disambut baik oleh Presiden melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 yang dibuat pada 9 Oktober 1998. Sejak saat itu, Komnas Perempuan terus berjuang menegakkan hak asasi perempuan Indonesia.
Dari upaya yang telah dilakukan, kami menyimpulkan bahwa Saparinah memiliki cara tersendiri dalam memperjuangkan hak-hak perempuan Indonesia. Ia barangkali bukan aktivis yang bekerja di tingkat akar rumput, ia bahkan sempat menolak disebut sebagai aktivis.6 Namun, dengan jejaringnya dan kerja-kerja bersama para aktivis/pemikir perempuan, Saparinah berhasil membuka ruang dan menciptakan peluang dalam sebuah sistem yang mapan. Urusan perempuan yang semula disepelekan, kini menjadi bagian penting dalam institusi pendidikan dan pemerintahan. Lika-liku perjalanan panjang Komnas Perempuan dan Program Kajian Wanita pada masa itu merupakan bukti dari upaya-upaya Saparinah bersama para perempuan lain yang hingga saat ini terus memberikan dampak penting bagi perjuangan pemenuhan hak dan keadilan bagi perempuan di Indonesia.
Penutup: Catatan Kritis dan Refleksi
Sebagaimana Saparinah yang belajar dan berefleksi dari para pemikir perempuan lainnya—seperti Shulamit Reinharz, Bernice Lott, Liz Stanley, Naomi Black, Roberta Johnson, Dorothy Ross, Rosemarie Putnam Tong, Nancy Chodorow, dan juga para cendekia perempuan Indonesia yang banyak berdiskusi dengannya seperti Siti Musdah Mulia, Dr. Mely G. Tan, dan Prof. Dr. T.O Ihromi—dalam proses ini, kami juga meninjau pemikiran-pemikiran dan gerakan Saparinah. Adapun catatan kritis ini dibuat bukan dengan semangat untuk menjatuhkan atau menjelekkan melainkan untuk mengisi celah dan tidak menegasikan pemikiran/gagasan serta kontribusi penting dan berharga Saparinah.
Seperti yang dikatakan oleh Saparinah bahwa manusia selalu berada dalam proses “menjadi,” catatan kritis ini dapat dilihat sebagai sebuah tahapan untuk terus memajukan pemikiran perempuan agar senantiasa tepat dalam menggambarkan kenyataan dan menjawab setiap tantangan yang hadir di tengah masyarakat.
Meski Saparinah menyadari dan menekankan pentingnya pendekatan lintas disiplin dalam studi kajian perempuan, akan tetapi dalam bukunya Berbeda tetapi Setara, analisis Saparinah cenderung masih terbatas pada analisis psikologis dan behavioralis. Hal ini menyebabkan adanya beberapa keterbatasan. Dalam menganalisis pembangunan, misalnya, Saparinah belum terlalu banyak mengeksplorasi Kajian Wanita kaitannya dengan dimensi kritis dari ekonomi politik sehingga ia masih cenderung menggunakan cetak biru pembangunan arus utama sebagai rujukan. Selain itu, meski Saparinah menekankan pentingnya mengenali peran perempuan dalam pembangunan, ia masih belum banyak mengelaborasinya, terutama dalam kaitannya dengan peran perempuan kelas pekerja sebagai pilar dari pembangunan itu sendiri. Keterbatasan tersebut juga terlihat pada konsep kemitrasejajaran, Saparinah belum mengelaborasi dinamika posisi kelas, struktur, dan hierarki sosial dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan memang dibutuhkan, tetapi bukan kesetaraan semu yang mengasumsikan perempuan sebagai entitas tunggal. Dalam hal ini, misalnya, perempuan terbagi ke dalam kelas sosial yang kemudian menyebabkan terbentuknya pengalaman berbeda-beda.
Selain itu, meski telah menekankan kesadaran atas kebhinekaan, kajian-kajiannya tentang pengalaman-pengalaman perempuan di Indonesia masih terpusat di Jawa. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa tulisannya yang hampir selalu menempatkan Kartini sebagai tokoh sentral pelopor feminisme di Indonesia dan cenderung tidak mengelaborasi pemikiran perempuan lainnya di luar Jawa. Jika ditinjau kembali dari tulisan-tulisannya, trajektori intelektual Saparinah sebagian besar mengacu pada pemikiran feminis kulit putih, meski telah ada kesadaran atas perbedaan pengalaman perempuan yang berdasar pada ras dan kelas, serta menolak upaya dominasi pemikiran feminis kulit putih (dijelaskan melalui tulisan refleksinya bersama Marilyn Porter). Kedekatan Saparinah pada pemikiran feminis kulit putih membuat beberapa kajiannya bias atas kenyataan-kenyataan perbedaan dan kompleksitas pengalaman perempuan dalam konteks ras dan kelas, atau konteks kedaerahan, dengan mengasosiasikan pengalaman Kartini—termasuk dirinya sendiri yang juga Jawa—sebagai pengalaman semua perempuan. Hal ini juga seturut dengan absennya nama-nama pemikir feminis kulit berwarna, feminis interseksional, dan feminis transnasional seperti bell hooks, Audre Lorde, Gloria Anzaldúa, dan Nawal El Saadawi dari tulisan-tulisan Saparinah. Pada tahun-tahun yang hampir sama dengan perkembangan Kajian Wanita (1980-an), tokoh-tokoh tersebut banyak melayangkan kritik terhadap feminisme kulit putih yang cenderung mereduksi pengalaman perempuan, melanggengkan ideologi dominasi yang meresap di berbagai tingkatan tanpa melihat ulang ras, kelas, gender, batas wilayah, ekonomi, politik, bahkan konstruksi sejarah, yang mempengaruhi kondisi perempuan.
Menyoroti hubungan pusat dan daerah, Saparinah kerap mengkritisi Peraturan Daerah (Perda) Syariah yang membelit perempuan. Walaupun lagi-lagi yang disoroti adalah Perda di tanah Jawa, persisnya di Tangerang. Menurut Saparinah, banyak Perda Syariah yang mengatasnamakan agama guna menyasar perempuan, sedangkan pemerintah pusat tidak memiliki wewenang untuk menidakkan atau mengiyakan (Irawati, 2006). Di satu sisi, kami sangat setuju dengan pernyataan Saparinah mengenai Perda yang diskriminatif. Apalagi beberapa teman di Sekolah Pemikiran Perempuan—khususnya yang berasal dari Aceh—masih mengalami hal serupa. Namun, di sisi lain, kami lebih berhati-hati untuk memaknai perkataan Saparinah terkait wewenang pemerintah pusat.
Memang benar Perda Syariah cenderung tidak inklusif, tetapi “apakah benar, pusat sama sekali tidak ikut campur soal Perda yang menyengsarakan itu?” Pertanyaan seperti ini muncul ketika kami membaca pengakuan Plt. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri7 yang mengatakan bahwa Kemendagri memiliki upaya preventif, sehingga setiap Perda wajib disampaikan kepada Kemendagri terlebih dahulu. Jika bertentangan, akan dikoreksi untuk diperbaiki. Namun, jika sesuai akan diberi nomor register untuk Perda tersebut. Tidak hanya itu, pemerintah pusat juga melakukan upaya represif, yakni pengawasan terhadap Perda setelah ditetapkan. Kedua upaya tersebut telah dilakukan pemerintah pusat sejak tahun 2004.8 Menyalahkan Perda Syariah tanpa melihat keterlibatan pusat dalam proses pembentukannya adalah hal yang mencerabut. Namun demikian, kami sangat mengapresiasi langkah berani Saparinah mengkritik Perda Syariah yang dasar hukumnya adalah hukum agama Islam—hukum yang sulit dikritik di negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan masih melanggengkan norma patriarki.
Oleh karena itu, penting untuk melihat lebih lanjut proses pembentukan Perda Syariah dalam rangka melanjutkan estafet perjuangan Saparinah demi mewujudkan kebijakan-kebijakan daerah yang adil gender.
Kami juga membayangkan posisi Saparinah dalam peta gerakan feminisme di Indonesia. Pada masa Orde Baru dan awal reformasi, kami berargumen, Saparinah adalah salah satu pelopornya. Posisi Saparinah sebagai seorang akademisi mendorong terwujudnya penelitian-penelitian dengan perspektif adil gender di Indonesia. Sebagai seorang aktivis yang mengadvokasi hak-hak perempuan, ia mengusahakan agar hasil penelitian-penelitian tersebut dijadikan bahan masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan menetapkan berbagai keputusan politik yang relevan bagi masa depan perempuan Indonesia.
Latar belakang, pemikiran, dan gerakan Saparinah juga membantu kita dalam melihat kemungkinan-kemungkinan yang sekiranya bisa kita lampaui di zaman ini. Berjejaring dan berkolaborasi dalam gerakan perempuan adalah salah satu cara yang dapat terus kita lakukan dalam mengupayakan keadilan dan kesetaraan gender di tengah masyarakat.
“Mengubah keyakinan dan kebiasaan yang merugikan salah satu gender memerlukan agen-agen perubahan perempuan dan laki-laki. Artinya, pengembangan potensi perempuan dan laki-laki sama pentingnya agar terjadi transformasi sosial yang berkeadilan gender. Jelaslah bahwa untuk mencapai tujuan ini diperlukan manusia-manusia, perempuan dan laki-laki, yang profesional di bidangnya, dan sebagai peneliti, peka terhadap isu-isu perempuan dan gender.”
(Saparinah Sadli)
Catatan Kaki
1] Di sepanjang tulisan, kami akan menyebut nama depan Saparinah Sadli, yakni Saparinah, dengan tujuan agar atribusi Saparinah tidak semata dilekatkan pada suaminya.
2] Wawancara Saparinah Sadli: Why Fight for Gender Equality, Channel YouTube Project Tirai, 2018.
3] Ketiga esai dimuat dalam Berbeda tetapi Setara (Kompas, 2010).
4] Saparinah Sadli, Studi Wanita: Pengembangan dan Tantangannya dalam buku Berbeda tetapi Setara, Kompas, 2010.
5] Siti Nurwati Hodijah, dkk. Komnas Perempuan 1998-2001: Proses Pembentukan Lembaga Negara untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Pencariannya, dalam Rekam Juang Komnas Perempuan, 2014.
6] Purwanti, "Prof. Dr. Saparinah Sadli dan Kesetaraan Gender” dalam pesona.co.id.
7] Dwiastono, “Perda syariah di Indonesia: antara kearifan lokal, politik elektoral dan ancaman terhadap kebhinekaan” dalam bbc.com.
8] Keterlibatan pemerintah pusat terhadap Perda juga termuat dalam Pasal 145 UU No. 32 Tahun 2004–yang masih dimuat dalam prosedur penyusunan produk hukum daerah di tahun 2006–bahwa Perda bisa dibatalkan oleh pemerintah bilamana bertentangan dengan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pada praktiknya pemerintah pusat, melalui Departemen Dalam Negeri (Depdagri), menemukan sebanyak 930 Perda yang bermasalah sepanjang tahun 1999-2006. Sebanyak 156 di antaranya perlu dilakukan revisi, 506 dibatalkan oleh Depdagri, dan 24 lainnya dibatalkan langsung oleh pemerintah daerah (R. Siti Zuhro dan Eko Prasojo, 2010).
Kepustakaan
Afifah, Neng Dara, dkk. 2014. Rekam Juang Komnas Perempuan: 16 Tahun Menghapus Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan.
Hestia, Ainun Fintari. 2018. “Studi Fenomenologi Feminis: Esensi Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)”. Skripsi, Semarang: Universitas Diponegoro.
Irawati, Henny. 2006. "Saparinah Sadli: Women's Studies di Indonesia". Jurnal Perempuan. (48): 119-124
R. Siti Zuhro dan Eko Prasojo. 2010. Kisruh Peraturan Daerah: Mengurai Masalah dan Solusinya. Yogyakarta: Penerbit Ombak dan The Habibie Center.
Sadli, Saparinah, Marylin Porter. 1999. “Importing/Applying Western Feminism: A Women’s Studies University Linkage Project.” Women’s Studies International Forum, Forum, Vol. 22, No. 4, hh. 441–449.
Sadli, Saparinah. 2010. Berbeda tetapi Setara: Pemikiran tentang Kajian Perempuan. Jakarta: Kompas.
Sadli, Saparinah, dkk. 1984. Di Atas 40 Tahun: Kondisi Problematik Pria Wanita. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
Situs web
Dwiastono, Rivan. 2019. “Perda syariah di Indonesia: antara kearifan lokal, politik elektoral dan ancaman terhadap kebhinekaan” bbc.com. (https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49332135)
Purwanti, Tenni. “Prof. Dr. Saparinah Sadli dan Kesetaraan Gender” pesona.co.id.(https://www.pesona.co.id/read/prof-dr-saparinah-sadli-dan-kesetaraan-gender-)
Tirai, Project. 2018. Saparinah Sadli: Why Fight for Gender Equality? Perjuangan Demi Kesetaraan Gender. Channel Youtube Project Tirai. (https://www.youtube.com/watch?v=qIfRiDn6uG4)