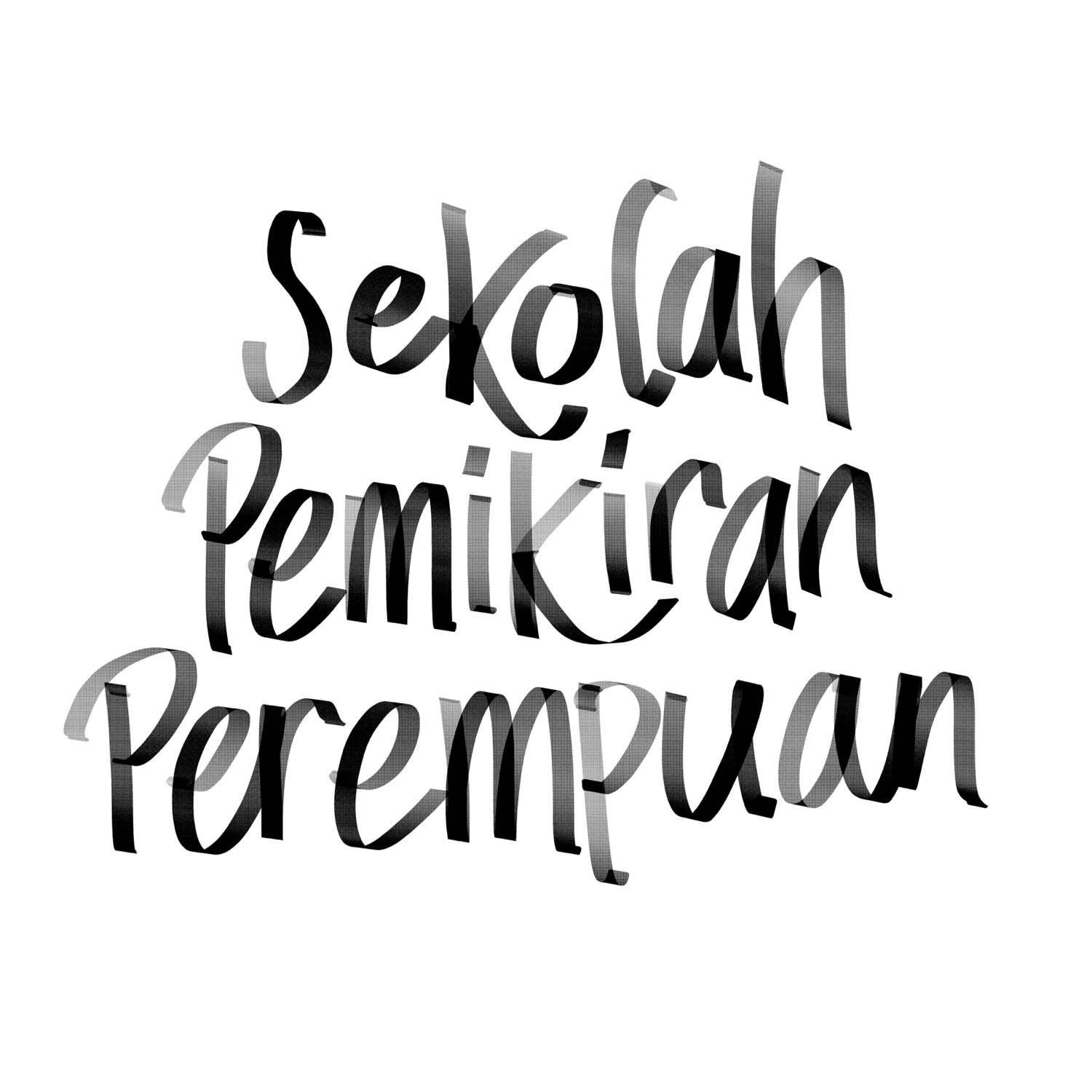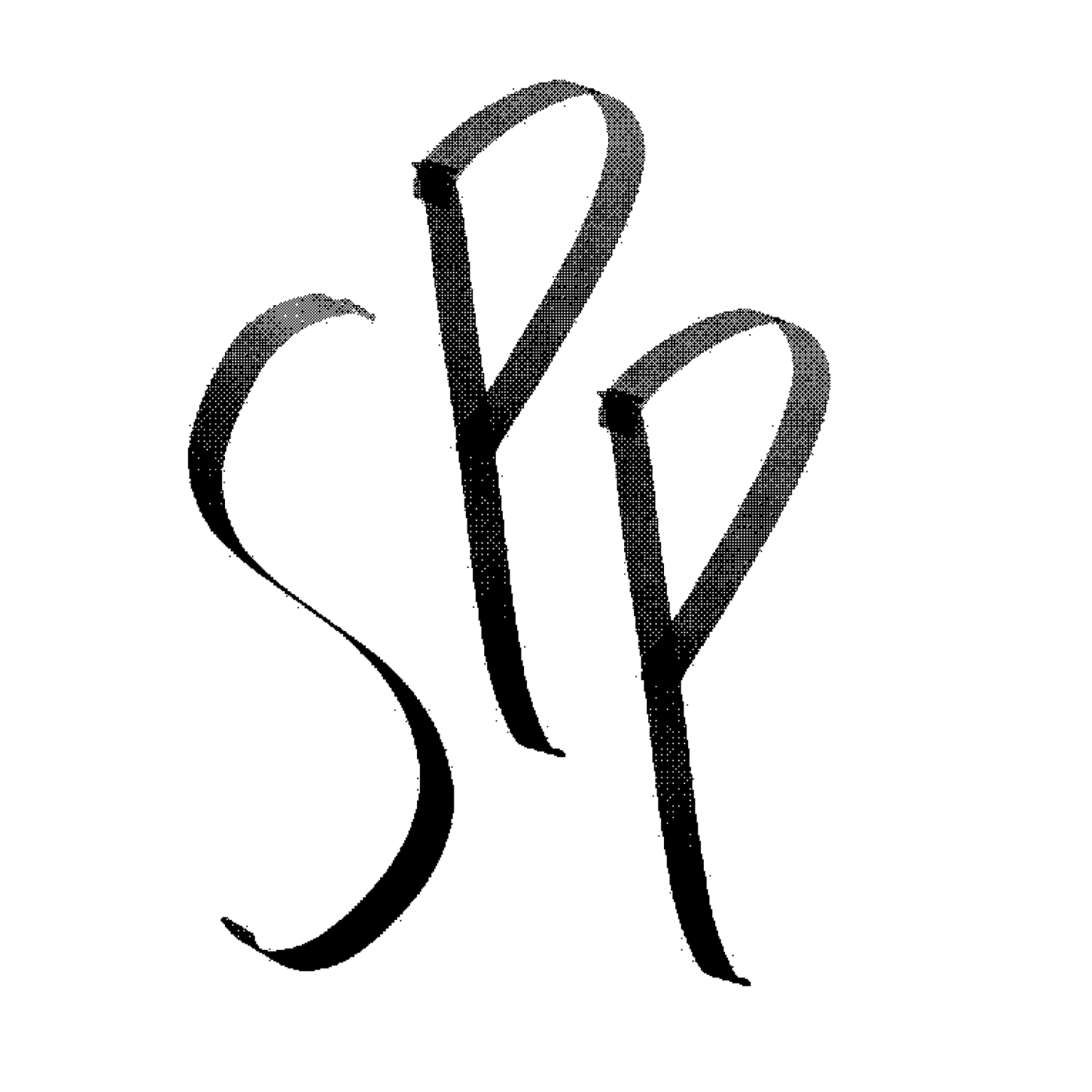Gloria Anzaldúa: Wacana Pengalaman Ketubuhan dan Aktivisme Spiritual
oleh: Dewi Rosfalianti Azizah dan Himas Nur
Perjalanan Kehidupan dan Warisan Karya
Delapan puluh tahun lalu, tepatnya 26 September 1942, Gloria Evangelina Anzaldúa lahir di Raymondville, Rio Grande Valley, Texas. Ia merupakan sulung dari empat bersaudara. Kedua orang tuanya merupakan buruh petani migran. Sejak dini ia membantu menghidupi keluarganya dengan bekerja di peternakan dan pertanian.
Perjumpaannya dengan wacana ketubuhan dan diskriminasi selaras dengan perjalanan hidup Anzaldúa sebagai seorang perempuan1 Meksiko-Amerika. Ia mengenal trauma ketubuhan sejak masih sangat muda. Anzaldúa didiagnosis memiliki ketidakseimbangan hormon (hormone imbalance) yang menyebabkannya mengalami menstruasi di usia enam tahun. Keadaan tersebut juga menyebabkan pertumbuhan tulangnya berhenti lebih awal.
Pengalamannya selama tumbuh besar di perbatasan Meksiko-Texas juga membentuk perspektifnya atas korporasi kulit putih. Anzaldúa menyaksikan sendiri bagaimana keluarganya dieksploitasi dan diperlakukan tidak adil oleh pemangku kebijakan terkait. Kesadaran penuh akan realita ketubuhan dan ketidakadilan yang melingkupi, baik itu secara fisik, mental, maupun sosial, ia refleksikan pada banyak karya-karyanya. Anzaldúa mengembangkan konsep tentang kebudayaan, marginalisasi sosial, queer, feminisme, sastra, serta bentang kehidupan di sepanjang perbatasan.
Ia menempuh pendidikan sarjana di jurusan English, Art, and Secondary Education, University of Texas–Pan American (sekarang University of Texas at Rio Grande Valley). Perjalanan Anzaldúa selama bersekolah pun tidak mudah; sebagai seorang imigran, ia kerap mengalami diskriminasi dari sistem pendidikan yang bias kulit putih. Pada tahun 1972, Anzaldúa memperoleh gelar master dari Universitas Texas at Austin dalam bidang Bahasa Inggris dan Pendidikan. Dua tahun selanjutnya, ia menempuh program doktor dalam bidang Sastra. Pada masa itu pula Anzaldúa terjun di dunia aktivisme feminis, keadilan sosial, kepenulisan, dan sastra. Ia menorehkan sederetan prestasi dan memperoleh banyak penghargaan, antara lain National Endowment for the Arts Fiction Award (1991) dan Lambda Lesbian Small Book Press Award (1991).
Anzaldúa meninggal dunia pada 15 Mei 2004 karena komplikasi diabetes yang sudah ia derita selama hampir 12 tahun. Kala itu Anzaldúa tengah menyelesaikan disertasinya untuk program doktor Sastra dari University of California Santa Cruz. Gelar tersebut kemudian diberikan secara anumerta pada 2005. Sepanjang hidupnya, Anzaldúa menggugat banyak hal; esensialisme gender dan ekspektasi sosial akan imaji ideal perempuan, sistem patriarki dan heteronormativitas, kebijakan imigrasi perbatasan yang kejam dan eksploitatif, serta implikasi dari kolonialisme yang merenggut imajinasi-imajinasi alternatif akan kebebasan.
Dalam perjalanan karirnya sebagai seorang penulis, aktivis, dan pendidik, Anzaldúa pernah menetap di berbagai kota di Amerika Serikat seperti Austin, San Francisco dan Northfield. Selama itu pula ia hidup di lingkungan beragam dan dikelilingi orang-orang dari pelbagai latar etnis dan kepercayaan, seperti Puerto Rico, Yahudi-Amerika, dan Rusia. Anzaldúa mengidentifikasi perbedaan-perbedaan yang ia temukan dalam hidupnya dan menegosiasikan identitasnya untuk berbaur, memilah dan menginterogasi berbagai label dan kategori yang secara sosial disematkan kepada dirinya dan orang lain, serta berupaya menemukan ruang liminal yang memungkinkannya berinteraksi dengan cara yang “membebaskan.”
Tujuh Langkah Conocimiento Menuju Aktivisme Spiritual
“Identitas bersifat relasional. Siapa dan apa kita bergantung pada orang-orang di sekitar kita, campuran interaksi kita dengan alrededores/lingkungan kita, dengan narasi baru dan lama. Identitas itu berlapis-lapis, terbentang ke segala arah, dari masa lalu ke masa kini, vertikal dan horizontal, kronologis dan spasial.”
— (Anzaldúa, 2015: 69)
Hidup dalam identitas yang beragam kerap membuat individu merasa gamang atas posisinya. Hal ini disebabkan karena sekian perjumpaan identitas yang berkelindan, barangkali tak selaras. Struktur sosial yang dibangun di atas ketidakadilan juga menentukan ekspektasi dan prasangka akan identitas-identitas tersebut. Anzaldúa mengungkapkan walau terdapat aspek-aspek dalam identitas yang tak dapat diganti, kita dapat mengubah kepercayaan, laku, dan sikap kultur atas arti identitas tersebut.
Sekian kategori sosial yang ada—utamanya berdasarkan konteks historis, biologis, dan geografis—adalah aspek penting dalam identitas personal maupun kolektif. Namun kategori yang ada tidak pula memuat diri kita secara keseluruhan. Identitas konvensional seringkali menempatkan kita dalam posisi biner, menjadikan kita terjebak dalam sangkar yang menghambat diri untuk berkembang. Kita perlu melampaui batasan tersebut dan membiarkan kumpulan identitas yang melekat dalam diri kita saling berinteraksi—melahirkan sudut pandang baru yang memuat seluruh kompleksitas dan potensi diri.
Berdasarkan pengalamannya dalam membangun solidaritas di ruang interaksi tersebut, Anzaldúa merumuskan konsep yang ia namakan tujuh langkah conocimiento atau tujuh langkah menuju aktivisme spiritual. Conocimiento merupakan istilah Spanyol yang bermakna pengetahuan dalam bentuk kesadaran dan familiaritas, pengetahuan yang tidak hanya berada di gedung-gedung universitas atau tebal buku akademik. Conocimiento adalah praksis; pengetahuan yang dipelajari, dihidupi, dan diterapkan dengan tujuan nyata perubahan.
Ilustrasi oleh Gloria Anzaldúa dalam Light in the Dark/Luz en Lo Oscuro: Rewriting Identity, Spirituality, Reality, 2015
Namun menuntut akuntabilitas dan tanggung jawab dari penindas, tentu bukan hal mudah. Akan ada kontestasi narasi yang berbenturan—Anzaldúa menamakannya sebagai the blow up. Peristiwa tersebut menandai fase keenam di mana Anzaldúa berpendapat bahwa proses ini menantang sekaligus transformatif, sebab di sinilah perubahan termanifestasi. Butuh keberanian, energi, dan sumber daya dalam menyuarakan yang termarginalkan. Begitu pula dengan perhatian atas aspek perlindungan, sebab visibilitas tak selamanya berjalan linier dengan rekognisi dan keselamatan. Pada tahap ini, solidaritas dan upaya saling melindungi adalah kunci.
Tahap terakhir adalah spiritual activism atau aktivisme spiritual. Proses ini menubuh dengan pengetahuan dan pengalaman yang kita hidupi. Keenam tahap sebelumnya mempersiapkan kita menjadi pribadi yang terbuka terhadap pengalaman aktivisme yang penuh tantangan dan pelajaran. Dengan hidup di antara kerak-kerak perbedaan, para aktivis spiritual memiliki potensi dalam mengartikulasikan ragam kultur dan perspektif. Para aktivis spiritual terbentuk sekaligus membentuk dirinya sendiri; subjektivitas yang tak hanya menempatkan mereka sebagai penghubung, namun juga keberanian dalam mempertanyakan dan membongkar kekangan tradisi lama. Mereka menelusuri pelbagai celah antara kemungkinan dan imajinasi atas pilihan-pilihan baru. Kesemuanya berpotensi membebaskan mereka dari penindasan yang mengakar.
Refleksi Conocimiento untuk Perjuangan Feminis di Indonesia: Menulis sebagai Resistensi
Conocimiento dapat diwacanakan untuk merefleksikan pengalaman perempuan dan kelompok marginal. Konsep ini beresonansi pula dengan perjuangan feminisme interseksional, transnasional, anti-kolonial dan anti-kapitalis. Conocimiento merupakan ruang bertumbuh untuk saling mengenal, bernegosisasi, bertransformasi, dan bersolidaritas. Alih-alih menjadi dinding yang memisahkan, tantangan yang ada justru dapat menjadi jembatan atas pelbagai realitas pengalaman. Batas-batas yang dimiliki perempuan dan kelompok marginal di Indonesia tak dihilangkan, melainkan diakui keberadaannya dan dimanfaatkan sebagai ruang interaksi untuk menghasilkan rangkai potensi pembebasan.
Anzaldúa mengungkapkan bahwa aktivisme spiritual akan senantiasa berubah dan menemukan bentuknya sendiri. Proses tersebut dilakukan dengan mempertanyakan, memperbaiki metode-metode sebelumnya, serta menyesuaikan diri dengan konteks kultural, temporal, dan spasial. Sebagaimana Anzaldúa (2002: 1) pernah berujar, “change is inevitable; no bridge lasts forever,” perlu kesadaran merekognisi berbagai lapis kerentanan dan ketidakstabilan. Proses ini menjadikan aktivisme tak bersifat statis dan absolut, melainkan menjelma pembelajaran yang berjalan terus.
Dalam proses mencapai aktivisme spiritual, Anzaldúa percaya bahwa tujuh langkah conocimiento bukan sebuah kemutlakan. Saat kita merasa putus asa, penting untuk mengingat bahwa keputusasaan adalah bagian dari proses yang mengantarkan kita menuju perubahan. Aktivisme spiritual juga tidak dapat dihidupi dan dialami sendirian, karena ia senantiasa membutuhkan friksi agar kita tetap belajar menginterogasi.
Selain gagasan conocimiento, Anzaldúa juga mengadvokasi perempuan, queer, dan kelompok marginal lainnya untuk menulis. Melalui esainya yang terkenal, Speaking in Tongues: A Letter to Third World Women Writers, Anzaldúa membagikan pemikirannya akan praktik menulis sebagai resistensi dan reklaim pengetahuan. Ia merefleksikan bahwa tata kaidah kolonial membuat perempuan dan kelompok marginal susah untuk menulis dan takut untuk berbicara. Kuasa linguistik membuat keberanian mengartikulasikan pengalaman terhambat. Perempuan dan kelompok marginal kerap berjarak dengan keintiman pikir, perasaan, dan pengalaman yang hendak mereka ekspresikan.
Anzaldúa mengkritik tajam iklim literatur dan akademik di Amerika Serikat yang menghapus pengalaman perempuan “dunia ketiga” dan mendudukkannya sebagai daftar sumber daya demi perayaan performatif dan tokenisasi belaka (Anzaldúa, 1981: 29). Ia mempermasalahkan standardisasi metode kepenulisan yang didasarkan pada tradisi kulit putih, dengan bahasa Inggris yang mencerabut pengalaman ketubuhan sekaligus suara Anzaldúa sebagai seorang Chicana. Sistem produksi pengetahuan akademik kulit putih mengabaikan keberadaan pengetahuan kelompok indijenes dan orang-orang negara “dunia ketiga.”
Dalam konteks Indonesia, perempuan dan kelompok marginal seperti kawan-kawan disabel, masyarakat adat, minoritas gender dan seksualitas, turut terafek atas dominasi linguistik tersebut. Keputusasaan, inferioritas, dan internalisasi atas pengetahuan sistemik masih dirasakan. Ihwal tersebut sah dan wajar, sebagaimana Anzaldúa menekankan bahwa menulis bukanlah hal mudah bagi mereka yang mengalami penindasan. Terdapat sekian kerentanan yang akan hadir akibat pengalaman traumatis dan duka yang selama ini cenderung terpendam karena ketiadaan ruang untuk berbicara.
Namun Anzaldúa menguatkan kita pula bahwa peta dan kompas bukanlah abstraksi dari kaidah-kaidah akademis kulit putih, melainkan menubuh pada tiap-tiap inci diri. Anzaldúa mengajak kita untuk perlahan berani menulis, mendengar pengalaman ketubuhan secara lebih intim dan dekat, serta merekam jejak-jejak ingatan perjuangan yang telah diupayakan. Dengan memusatkan perhatian pada pengalaman hidup seraya berjejaring, perempuan dan kelompok marginal di Indonesia dapat bersama-sama menduduki ruang produksi pengetahuan. Dengan menulis, kita dapat merebut kembali narasi yang selama ini didominasi penindas dan kelompok hegemonik.
Menulis adalah hal yang paling berani sekaligus membahayakan, begitulah ungkap Anzaldúa. Sebab menulis berarti menyilakan ruang bagi reproduksi trauma, ketakutan, amarah, juga kesakitan atas lapis penindasan yang terjadi. Namun dari sana pula tumbuh kekuatan, keberanian, semangat perjuangan, solidaritas, serta kasih pada diri. Menulis ialah juga proses menuju aktivisme spiritual; keengganan dalam menerima segala yang mapan, mempertanyakan dunia sekaligus menginterogasi diri, menggugat struktur yang represif, sembari membayangkan sekian kemungkinan akan kehidupan yang lebih adil dan setara.
***
Catatan Kaki
1] Anzaldúa tidak merasa bahwa dirinya seorang perempuan. Kesakitan fisik yang ia alami membentuk jarak antara diri dan tubuhnya. Dalam wawancaranya dengan Ana Louise Keating, ia mengatakan, "I had no sexual identity because this whole part of my body was in constant pain all of the time. I couldn’t play like other kids. I couldn’t open my legs, my mother had to put a little piece of rag there. My breasts started growing when I was about six, so she made me this little girdle. I was totally alienated from this part of my body."
2] El arrebato: hancurnya subjektivitas, pengalaman, dan bentuk pengetahuan yang dianggap remeh.
3] Nepantla: liminalitas, wilayah perbatasan yang memungkinkan imajinasi dan kemungkinan-kemungkinan baru terungkap.
4] Coatlicue: upaya yang disengaja untuk mengonfrontasi kejahatan yang telah menjajah pikiran dan tubuh.
5] El compromiso: sebuah ajakan untuk mewujudkan pertalian melalui kreasi bersama narasi hibrida.
6] Putting Coyolxauhqui together: menyatukan narasi.
Kepustakaan
Anzaldúa, Cherríe Moraga & Gloria E. This Bridge Called My Back: Writings by Radical Women of Color. United States: SUNY Press, 2015.
Anzaldúa, Gloria E. Borderlands. United States: Aunt Lute Books, 2022.
________________. Light in the Dark/Luz en Lo Oscuro: Rewriting Identity, Spirituality, Reality. United States: Duke University Press, 2015.
________________. Speaking in Tongues: A Letter to Third World Women Writers, in This Bridge Called My Back: Writings by Radical Women of Color. Massachusetts: Persephone Press, 1981.
Keating, Gloria E. Anzaldúa & AnaLouise. This Bridge We Call Home: Radical Visions for Transformation. United States: Taylor & Francis, 2013.
Lara, Irene. Daughter of Coatlicue: An Interview with Gloria Anzaldúa in EntreMundos/AmongWorld: New Perspectives on Gloria Anzaldúa. Ed. AnaLouise Keating. New York: Palgrave Macmillan, 2008.
—
Tulisan ini turut dikembangkan dalam Lokakarya Kolaborasi Lab Perspektif Perempuan X Sekolah Pemikiran Perempuan yang berlangsung secara daring pada 7 Oktober 2023. Lokakarya tersebut merupakan kolaborasi SPP dengan Komite Seni Rupa Dewan Kesenian Jakarta (DKJ).