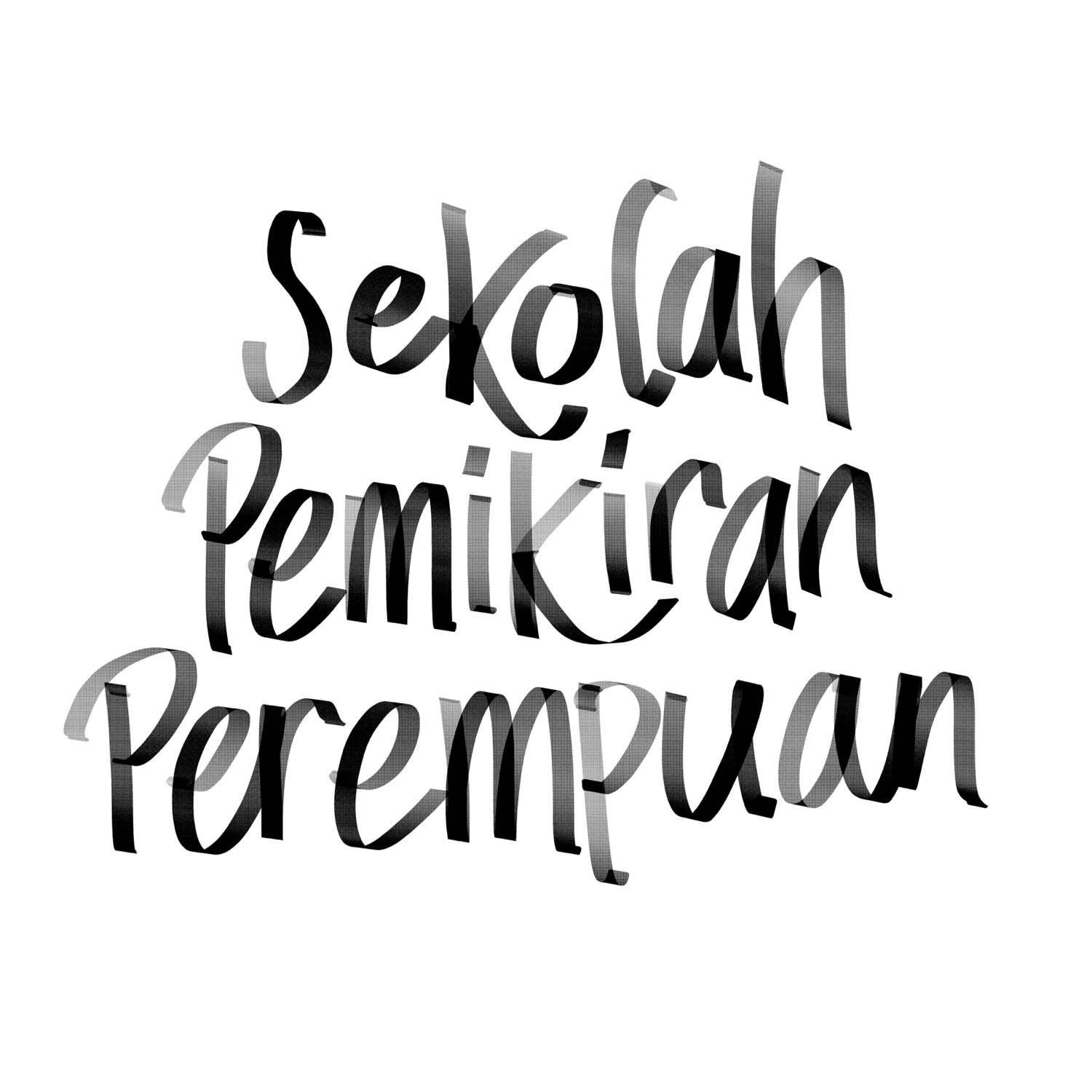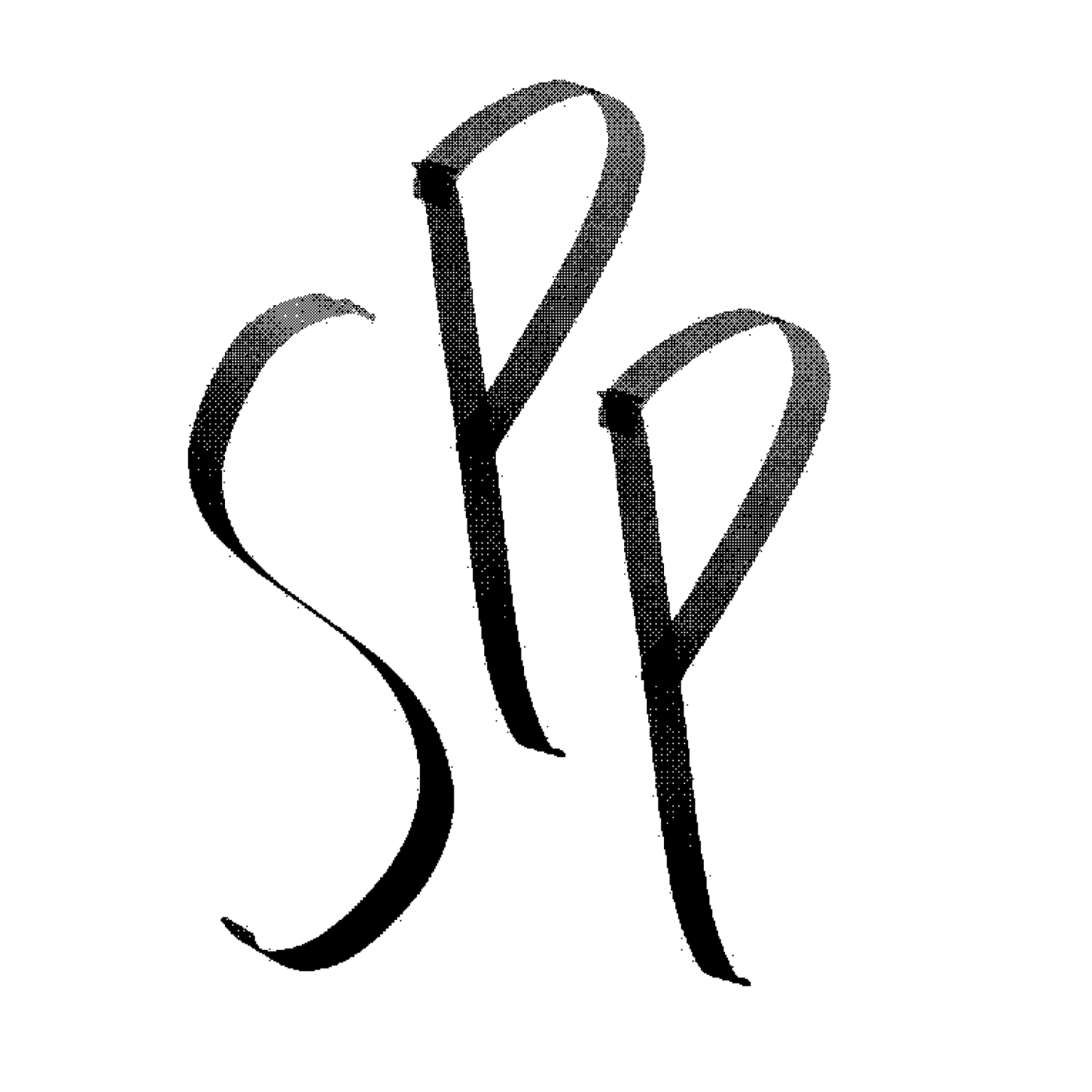Nawal El Saadawi, Pembangkang yang Membongkar Patriarki di Dunia Arab
oleh: Ayomi Amindoni, Tyassanti Kusumo Dewanti, Restiana Purwaningrum, dan Eka Wahyuni
“Mereka berkata, ‘kamu adalah perempuan yang biadab dan berbahaya,’
saya mengatakan yang sebenarnya, dan kebenarannya biadab dan berbahaya.”
― Nawal El Saadawi
Perempuan ‘Liar’ dari Delta Sungai Nil
Kutipan di atas merupakan potongan percakapan dari novel Perempuan di Titik Nol, sebuah novel kontroversial di masyarakat Mesir yang mulai ditulis pada 1974 dan dipublikasikan pada 1977 oleh sebuah penerbit di Beirut, Lebanon.1 Percakapan tersebut merupakan kenyataan yang dialami langsung oleh sang penulis saat dirinya mengangkat perjalanan hidup seorang perempuan bernama Firdaus dalam karyanya.
Nawal El Saadawi lahir di delta Sungai Nil bagian bawah, pada 26 Oktober 1931. Selain dikenal sebagai seorang sastrawan, ia juga diingat sebagai aktivis feminis Mesir yang berkontribusi besar dalam memperjuangkan kesetaraan hak-hak perempuan serta isu keadilan sosial.
Orang tua Nawal El Saadawi merupakan keluarga yang memiliki keistimewaan karena kelas sosial mereka. Ibunya, Zaynab (Shoukry) El Saadawi, berasal dari keluarga Turki Ottoman yang kaya. Ayahnya, Al-Sayed El Saadawi, adalah seorang pejabat di Kementerian Pendidikan. Nawal merupakan anak kedua dari sembilan bersaudara yang semuanya dituntut untuk berpendidikan tinggi oleh orang tuanya, sesuatu yang cukup tidak lazim pada masa itu.
Meski dituntut untuk berpendidikan tinggi, Nawal masih tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan ketidaksetaraan gender, di mana perempuan dibatasi oleh tradisi dan norma sosial. Ketidaksetaraan tersebut dialaminya sendiri saat berusia 6 tahun. Atas nama tradisi dan norma sosial yang diagung-agungkan, ia harus mengalami pemotongan klitoris tanpa persetujuannya. Peristiwa tersebut menjadi benih perjuangan panjang Nawal dalam menuntut kesetaraan hak perempuan hingga akhir hayatnya.
Tahun 1955, Nawal meraih gelar dokter di Universitas Kairo. Setelah menyelesaikan pendidikan kedokterannya, ia bekerja sebagai dokter dan psikiater di berbagai rumah sakit. Saat itulah realita kehidupan mulai tampak jelas di depan matanya. Ia melihat sendiri bagaimana penderitaan perempuan di dalam maupun di luar rumah sakit. Novel pertamanya, Memoirs of Woman Doctors (1958), merekam semua pergulatan batin dan pertanyaan-pertanyaannya terkait kesetaraan gender yang terjadi tidak hanya di lingkup pekerjaannya secara profesional, namun juga dalam struktur masyarakat Mesir pada masa itu.
Pada 1977, Nawal menerbitkan novel yang mengguncang dunia sastra dan perjuangan hak-hak perempuan, Emra'a enda noktat el sifr atau yang lebih terkenal dengan terjemahan Inggrisnya, Woman at Point Zero (Perempuan di Titik Nol). Novel ini menceritakan kisah seorang perempuan yang dihadapkan pada hukuman mati di penjara Mesir. Melalui Firdaus, sang karakter utama, Nawal menggambarkan penderitaan perempuan dan ketidaksetaraan yang mereka alami dalam masyarakat patriarki.
Karyanya menciptakan kontroversi besar, terutama di kalangan penguasa politik Mesir. Pemerintahan Anwar Sadat tidak menyukai pandangan dan aktivisme Nawal. Nawal kemudian ditangkap dan dipenjara pada 1981. Namun penjara tidak bisa menahan semangatnya. Nawal tetap melanjutkan perjuangan, bahkan setelah masa pembebasannya.
Nawal El Saadawi menjadi salah satu feminis terkemuka di dunia Arab. Ia mendirikan organisasi-organisasi seperti Asosiasi Solidaritas Perempuan Arab dan Asosiasi Hak Asasi Manusia Arab untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan sosial. Kritiknya terhadap patriarki dan tradisi, mengubah pandangan banyak orang tentang peran perempuan dalam masyarakat. Pada saat yang sama, ia juga kritis terhadap kapitalisme dan imperialisme sebagai sistem yang berkelindan dengan patriarki. Ia adalah seorang pejuang yang sangat setia pada idealisme dan kata hatinya.
Trauma yang Menjalar dan Menyalakan Api Perjuangan
Peringatan Pemicu: Tulisan ini memuat kata-kata eksplisit tentang wacana kekerasan seksual yang mungkin membuat Anda tidak nyaman atau dapat memicu trauma Anda. Silakan ambil jeda, lanjutkan, atau hentikan membaca sesuai dengan kebijaksanaan Anda.
Bocah perempuan berusia enam tahun itu terjaga dari tidurnya kala merasakan tubuhnya dibopong dari peraduan. Dalam kondisi setengah sadar di lantai kamar mandi yang dingin, dikelilingi beberapa orang dewasa yang membentangkan kedua kakinya dan memegang pahanya erat-erat, dia merasakan ujung logam yang tajam dan dingin berada di antara kedua pahanya. Tiba-tiba, dia merasakan sakit yang teramat sangat di bagian kelaminnya, sontak gadis kecil itu menjerit kesakitan. Panik melihat genangan darah di sekitar bagian bawah tubuhnya, bocah kecil itu memanggil ibunya, meminta pertolongan. Tak dinyana, ibunya sedari tadi berada di sisinya dan turut berpartisipasi dalam “penjagalan” tubuh putrinya.2
Kenangan masa kecil itu terus menghantuinya, bahkan ketika menjadi dokter di kampung halaman. Dia kerap merawat gadis-gadis muda yang datang ke klinik dengan perdarahan hebat setelah bagian dari kelaminnya dimutilasi. Sejak itu, perempuan bernama Nawal El Saadawi berjuang melawan praktik mutilasi klitoris.
Praktik sunat terhadap perempuan, atau female genital mutilation (FGM)3 adalah pengangkatan sebagian atau semua kelamin luar (vulva) untuk alasan non-medis,4 kerap dengan alat ala kadarnya dan tanpa anestesia. Sunat vulva dialami oleh 200 juta penyintas di 30 negara—antara lain Mesir, Ethiopia dan Indonesia—dengan dalih beragam,5 di antaranya identitas budaya dan gender; kontrol atas seksualitas dan reproduksi; keyakinan budaya tentang kebersihan, estetika dan kesehatan; serta tafsir agama. Nawal menentang keras, bukan hanya karena praktik itu tidak memiliki manfaat apa pun bagi kesehatan, pemotongan bagian dari vulva, juga adalah bentuk kontrol patriarki terhadap ketubuhan manusia.
Lewat karya sastra dan non-fiksinya, Nawal berpandangan bahwa mutilasi bagian vulva adalah tradisi yang turun-temurun dan bukan berasal dari ajaran Islam. Praktik tradisi tersebut jelas merugikan, mengontrol tubuh dan seksualitas, menimbulkan trauma psikologis, hingga menyebabkan kematian.
Pada saat yang sama, dia menyatakan ketidaksetujuannya kepada perempuan Barat yang menggambarkan sunat vulva sebagai bukti penindasan biadab yang hanya terjadi pada perempuan di Afrika dan Arab, “perempuan Eropa dan Amerika mungkin tidak mengalami pelukaan klitoris, namun mereka adalah korban klitoridektomi budaya dan psikologis.”6
Pada akhirnya, sunat vulva resmi dilarang di Mesir pada tahun 2008. Namun praktik tersebut masih berlanjut di belahan bumi lainnya, seperti Indonesia, dan Nawal El Saadawi terus mengutuknya hingga akhir hayatnya.
Di Indonesia, Komnas Perempuan dalam laporan Sunat Perempuan menyebut praktik itu sebagai kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya. Praktik ini juga bertalian erat dengan nilai agama—khususnya Islam—seperti yang terjadi di masyarakat adat Pelau di Maluku Tengah, Maluku. Tradisi sunat terhadap perempuan, atau Oiwaei dalam bahasa lokal, dilakukan dengan menyentuhkan gata-gata (sumpit untuk makan papeda) di atas vagina anak perempuan. Seorang perempuan dianggap belum Islam jika belum disunat.
Di Sambas, Kalimantan Barat, sunat bagi anak perempuan wajib hukumnya dan rata-rata dilakukan ketika masih bayi dengan memotong klitoris sampai habis dengan alasan agar perempuan “tidak liar dan binal”. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung sunat perempuan dengan mengatakan, “khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam.”7
Akan tetapi tidak ada dalil yang menegaskan kewajiban sunat vulva dengan mengemukakan bahwa praktik itu demi “memuliakan perempuan”. Hanya ada satu dalil yang menerangkan petunjuk dan tata cara pelaksanaannya, yang secara gamblang menunjukkan bahwa praktik itu dilakukan demi kepuasan laki-laki. “Janganlah engkau habiskan semua, karena sesungguhnya hal itu akan lebih baik bagi wanita dan lebih disukai para suami” (HR Abu Dawud). Nihilnya dalil-dalil agama yang menegaskan kewajiban sunat vulva, memperkuat kritik Nawal terhadap tindakan tersebut. Mutilasi vulva murni merupakan bagian dari upaya mengontrol tubuh dan seksualitas, serta mengukuhkan dominasi patriarki.
Melawan Lewat Sastra
"Kata-kata tertulis bagi saya menjadi tindakan pemberontakan terhadap ketidakadilan yang dilakukan atas nama agama, moral, atau cinta."
– Nawal El Saadawi, The Daughter of Isis (1986)
Karir menulis sastra Nawal El Saadawi telah dimulai sejak dini, bermula dari cerita pendek I Learned Love (1957) serta novel pertamanya Memoirs of a Woman Doctor (1958). Memoirs of a Woman Doctor mengisahkan protagonis yang melawan masyarakat patriarkis dan tradisional melalui aktivitasnya sebagai dokter—berdasar pengalamannya merawat pasien di pedesaan Mesir. Dia menerbitkan God Dies by The Nile (1974) yang mengisahkan persekongkolan laki-laki pemegang kekuasaan untuk merealisasikan tujuan mereka dengan berbagai cara. Perempuan korban jejaring patriarki ini kemudian membalas dendam terhadap para laki-laki yang menindasnya.
Nawal semakin mendapat popularitas lewat Woman at Point Zero (1977) yang mengisahkan Firdaus, pekerja seks yang dihukum mati karena membunuh muncikarinya. Pada novel terakhirnya, Zeina (2008), sang protagonis mempertanyakan cara Islam, Kristen, dan Yudaisme yang dipraktikkan di Mesir dengan interpretasi patriarki dan praktik misoginis yang membuat perempuan dianggap sebagai kaum yang “kurang intelek”.
Nawal menerbitkan lebih dari 27 buku, mulai dari non-fiksi, novel, cerita pendek, artikel, dan drama yang berfokus pada perempuan—dan kaitannya dengan tiga wacana yang dianggap tabu di dunia Arab: seksualitas, agama dan politik. Namun melalui sastra, Nawal lebih lantang bersuara. Ya, feminisme bisa pula disuarakan melalui sastra. Hal ini diaktualisasikan pula oleh pemikir feminis Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Marianne Katoppo lewat Raumanen (1977) dan Toeti Heraty lewat Calon Arang (2000).
Karya sastra Nawal menjadi “perpanjangan tangan” dari pemikiran dan perlawanannya dengan bahasa lugas namun penuh makna. Sastra memberikan ruang bagi Nawal untuk bereksperimen dalam penggunaan bahasa, gaya penulisan dan genre yang berbeda dalam setiap karyanya. Tokoh utama dalam setiap novelnya memiliki latar belakang dan kelas sosial yang beragam. Namun mereka punya satu kesamaan; perempuan yang ditindas oleh masyarakat patriarki.
Walaupun berbicara tentang realitas yang dialami perempuan Arab, karyanya tak hanya relevan bagi perempuan Arab. Sebaliknya, kita akan menyadari bahwa penindasan terhadap perempuan, tidak hanya terjadi di negara-negara Muslim, baik di Timur Tengah, Asia maupun Afrika—seperti yang kadang dipercayai oleh Barat—namun juga terjadi di semua tempat. Berkat novel-novelnya, Nawal memberikan banyak kontribusi pada sastra Arab secara keseluruhan. Lewat tulisannya, ia menawarkan pula gagasan yang berbeda tentang Islam; Islam adalah agama yang telah disalahtafsirkan dan sering disalahgunakan untuk menindas perempuan.
Membaca Nawal El Saadawi dalam konteks sejarah feminisme, humanisme, dan aktivisme perempuan Arab adalah kesempatan untuk menghilangkan beberapa stereotip pandangan yang menganggap feminisme Barat sebagai model feminisme dunia. Karya-karyanya merangkum kompleksitas perjuangan perempuan di dunia Arab, menghadirkan suara-suara perempuan yang kuat, dan merayakan keberagaman dalam perjalanan feminisme.
Nawal El Saadawi dan Feminisme Transnasional
Meskipun dikenal luas karena kampanyenya melawan mutilasi klitoris, namun pemikiran dan perjuangan yang dilakukan Nawal lebih dari itu. Dengan mendasarkan pemikirannya pada seksualitas, politik, dan agama, ia meyakini patriarki, kapitalisme, dan imperialisme adalah sistem yang saling terkait dalam menindas perempuan Arab. Lewat tulisan dan aktivismenya, Nawal membawa suara feminisme Arab ke dunia transnasional.
Nawal dikritik karena memperkenalkan feminisme—yang dicap sebagai “konsep Barat” ke dunia Arab. Namun ia mengkritik balik pemikiran yang menganggap feminisme adalah konstruksi Barat. Bagi Nawal, feminisme bukanlah konstruksi Barat, demikian halnya patriarki. Sistem patriarki yang telah terbangun di seluruh dunia harus dirobohkan oleh semua orang di seluruh dunia —tidak hanya yang berada di Barat saja.
Nawal menggambarkan dirinya sebagai seorang "sosialis-feminis" yang meyakini perjuangan para perempuan tidak dapat dimenangkan tanpa membongkar pula kapitalisme. Dia mengkritik pandangan umum dunia Barat yang memandang substansi masalah yang dihadapi perempuan Arab karena faktor agama, budaya dan nilai keislaman. Anggapan ini menafikan penyebab utama dari kesenjangan itu; imperialisme dan kapitalisme, yang membuat masyarakat di dunia ketiga berada di bawah kendali dunia Barat.
Pemikirannya sejalan dengan wacana feminisme transnasional yang memiliki premis bahwa penindasan terhadap perempuan berbeda secara global, tak hanya karena gender, namun juga kelas, etnisitas, agama dan bangsa. Sumbangan Nawal pada feminisme transnasional adalah dengan mendasarkan pemikirannya pada seksualitas, politik, dan agama. Bagi Nawal, penindasan oleh sistem yang saling terkait itu, mencegah perempuan dalam mencapai potensi penuh mereka. Solidaritas antarperempuan dapat menjadi kekuatan perubahan. Namun solidaritas itu harus dilakukan dengan pemahaman tentang apa yang sedang terjadi di negara-negara yang dianggap terbelakang, agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan yang bertentangan dengan tujuan kesetaraan dan kebebasan bagi semua orang.
Nawal mengaplikasikan perspektif feminisme transnasionalnya dengan menyuarakan hubungan globalisasi-kapitalisme dan apa yang tengah terjadi pada perempuan. Seperti kaitan antara Elon Musk dengan perempuan adat Sawai di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Perempuan Sawai semakin terimpit oleh tambang nikel—bahan baku utama baterai kendaraan listrik yang sedang digandrungi—yang menggusur kebun dan mengotori perairan mereka. Untuk memenuhi hasrat akan “green energy” ini, Indonesia mengundang produsen mobil listrik Tesla untuk berinvestasi. Elon Musk inilah pemilik korporasi otomotif ekstraktif yang merusak ekologi perempuan adat Sawai. Nasib mereka sama seperti para perempuan yang sumber daya alamnya dieksploitasi; Ibu-ibu Kendeng di Jawa Tengah, Wadon Wadas di Yogyakarta, perempuan adat Besipae di Timor Tengah Selatan—mereka berpotensi mengalami beban berlipat dengan dalih investasi global.
Suara Nawal El Saadawi adalah suara masyarakat dunia ketiga; suara tiap orang yang menginginkan dirinya bebas dari penindasan patriarki, kapitalisme dan imperialisme. Lewat aktivisme dan karya-karyanya, Nawal membongkar bagaimana penguasa menggunakan agama sebagai ideologi kekuasaan dan menarik garis penghubung antara perjuangan lokal, nasional, dan global.
Perjuangan Nawal El Saadawi melampaui Mesir, menjangkau setiap pojokan perempuan dunia ketiga yang tertindas, membantu kita semua menemukan suara kita masing-masing, memberanikan diri untuk turut bersuara lantang dan melawan. Semangat Nawal adalah sesuatu yang hidup melalui kita semua dan akan terus bernyawa lewat karya-karyanya yang abadi.
***
Catatan Kaki
1] 1974 sebagai keterangan waktu penulisan Perempuan di Titik Nol mengacu pada waktu di mana Firdaus dijatuhi hukuman mati. Catatan perihal waktu novel ini ditulis, tercantum berbeda di berbagai sumber; antara 1974 atau 1975. Namun satu yang pasti, novel tersebut terbit setelah eksekusi Firdaus. Bukan sebuah kebetulan bila novel ini diterbitkan di Beirut. Kontroversi mengenai substansi karya Nawal di Mesir, membuat ia harus mencari penerbit di luar negeri.
2] Nawal El Saadawi menjelaskan secara gamblang pengalaman traumatis mutilasi vulva yang dialami dalam The Hidden Face of Eve: Women in the Arab World (1977).
3] Istilah “sunat perempuan” (female circumcision) atau female genital mutilation (FGM) patut untuk ditilik kembali dan dikritisi. Setidaknya, ada beberapa kawan non-biner yang menjadi penyintas praktik ini (lih. misal kisah Dena Igusti), yang menggugat terminologi “sunat perempuan” atau FGM agar bisa diperluas atau diperjelas lagi. Menekankan pada istilah teknis, seperti mutilasi vulva atau sunat vulva dirasa cukup mewadahi keragaman spektrum gender. Dengan demikian, praktik ini secara medis juga bisa dibaca secara luas, alih-alih misal hanya menyebut sunat atau mutilasi klitoris sebagai salah satu bagian dari vulva. Kecuali dalam konteks yang sedari awal membutuhkan istilah “sunat perempuan” atau FGM, misalnya rujukan sejarah, penggunaan istilah tersebut akan dibatasi dan diganti dengan sunat vulva atau mutilasi vulva. Konteks kehidupan Nawal pada pertengahan abad ke-20, di mana diskursus keberagaman gender belum begitu masif, menjadi dalih bahwa perspektif yang dihadirkan dalam ulasan-ulasannya masih bersifat biner gender. Hal itu bisa dilihat dari pengatribusian pengalaman sunat vulva kepada perempuan (cisgender) saja, yang sebetulnya terus ditemui bahkan dalam konteks abad ke-21 oleh semua ragam gender. Untuk itu, ketika istilah “perempuan” digunakan di sini, ia merujuk pada tubuh biologis orang-orang yang diidentifikasikan oleh kuasa medis/kultural sebagai perempuan (Assigned Female At Birth/AFAB), alih-alih berdasarkan penghayatan identitas gendernya.
4] FGM dapat dikelompokkan menjadi beberapa tipe sesuai dengan bagian vulva yang diangkat, yakni; klitoridektomi atau pengangkatan sebagian atau total klitoris dan/atau kulup (Tipe I); Eksisi atau pengangkatan sebagian atau total klitoris dan labia minora, dengan atau tanpa eksisi labia majora (Tipe II); Infibulasi atau penyempitan lubang vagina dengan pembuatan segel penutup dengan memotong dan menempatkan labia minora dan/atau labia majora, dengan atau tanpa eksisi klitoris (Tipe III), serta; tidak diklasifikasikan (Tipe IV).
5] World Health Organization. (2023, January 31). Female Genital Mutilation, diakses 26 Februari 2023.
6] El Saadawi, Nawal. (2007). The Hidden Face of Eve: Women in the Arab World. London: Zed Books, pp. XVII – L).
7] Dalil ini termuat dalam Hukum Pelarangan Khitan Terhadap Perempuan yang dikeluarkan oleh MUI pada 7 Mei 2008.
—
Tulisan ini turut dikembangkan dalam Lokakarya Kolaborasi Lab Perspektif Perempuan X Sekolah Pemikiran Perempuan yang berlangsung secara daring pada 7 Oktober 2023. Lokakarya tersebut merupakan kolaborasi SPP dengan Komite Seni Rupa Dewan Kesenian Jakarta (DKJ).