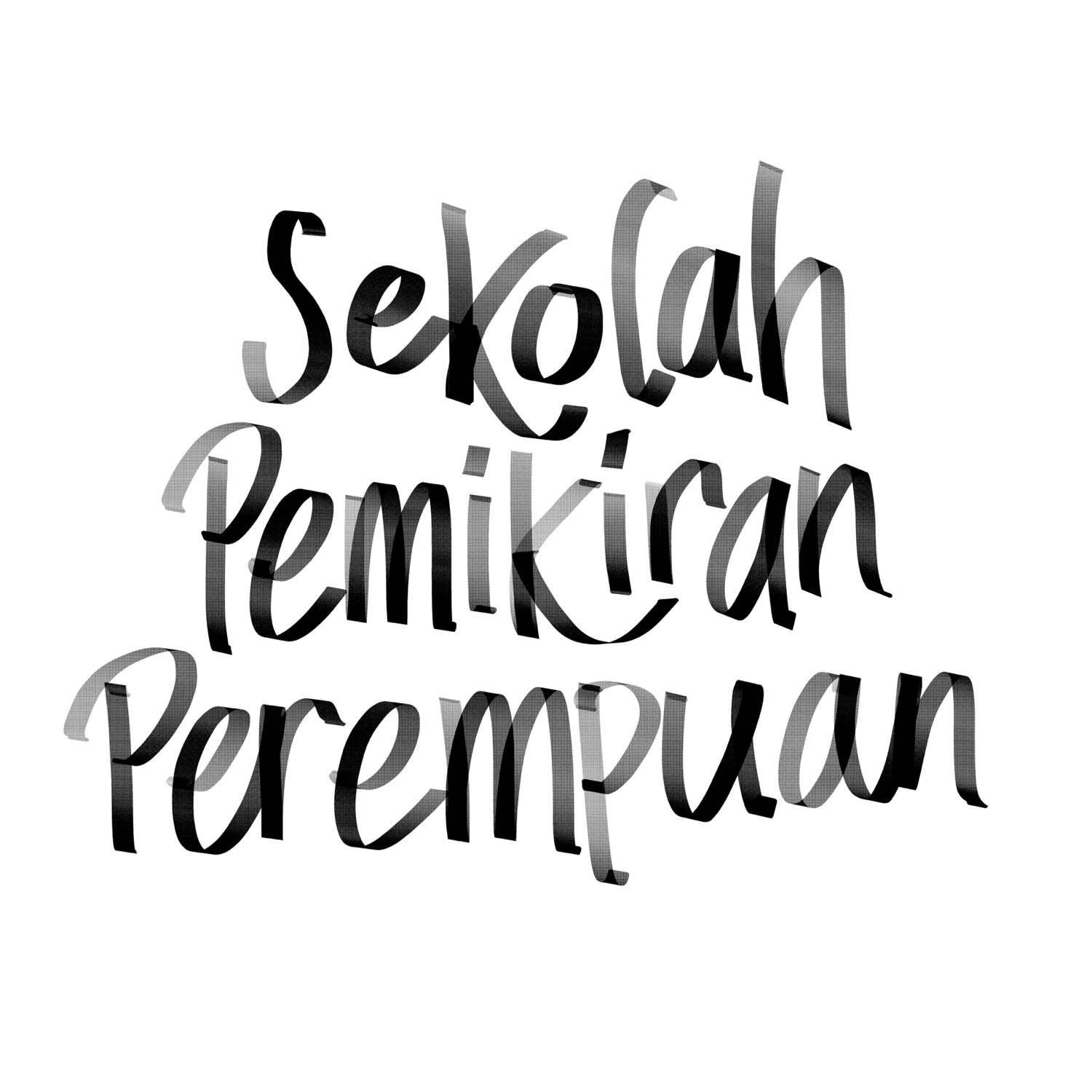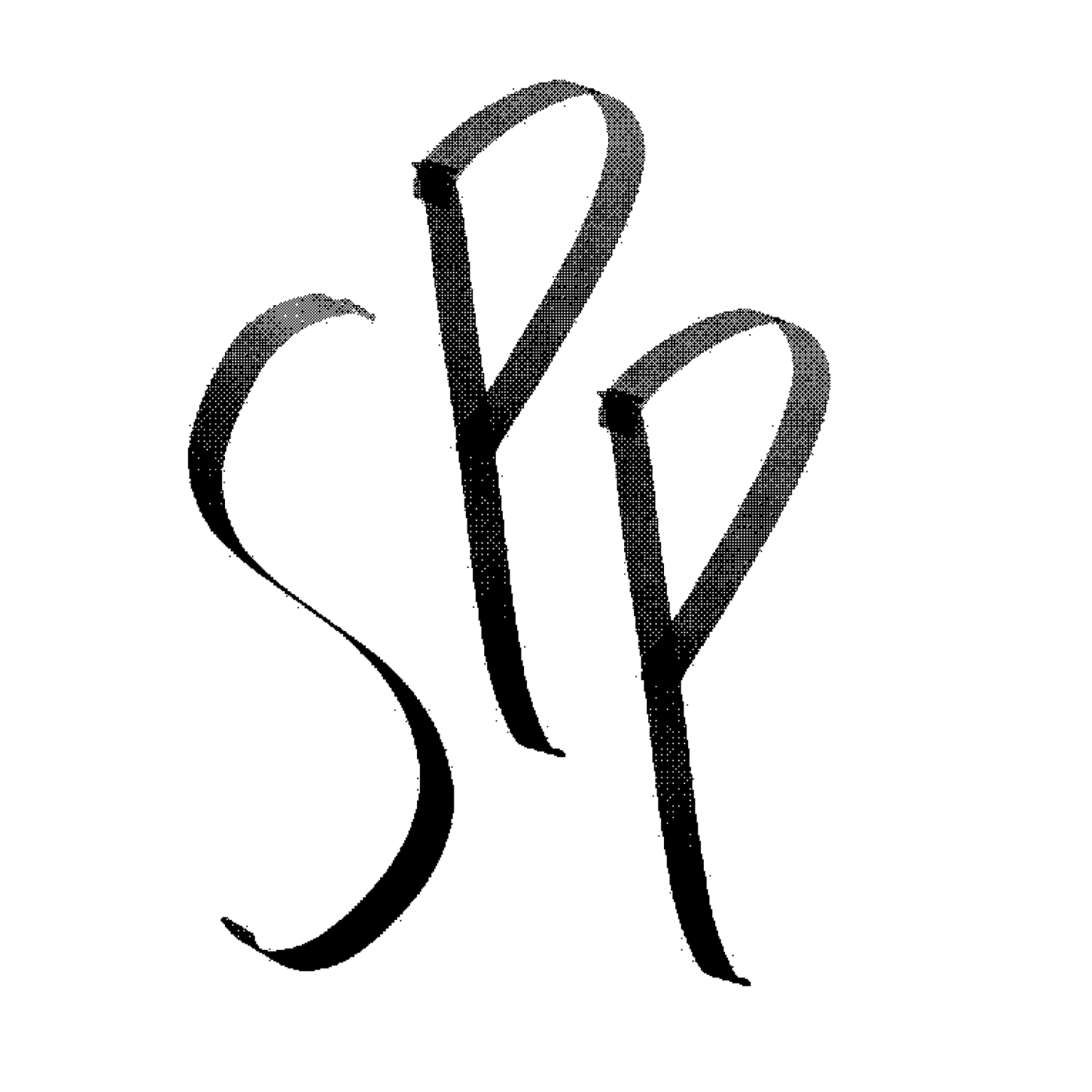S. Rukiah: Sastra dan Perjuangan Perempuan yang Tak Putus
oleh: Ama Gaspar, Asri Pratiwi Wulandari, Silvy Chipy, dan Udiarti
Tulisan ini merupakan upaya kami dalam menajamkan dua poin penting pemikiran Siti Rukiah, yakni gagasan interseksional yang melampaui zamannya dan perubahan global geopolitik di Indonesia, khususnya pada era Pendudukan Jepang dan Revolusi. Siti Rukiah lahir di Purwakarta pada 25 April 1927. Pada masa Pendudukan Jepang, Rukiah menyelesaikan pelatihannya sebagai guru. Pada 1945, Rukiah memutuskan mengajar di Sekolah Rendah Gadis sekaligus bekerja sebagai anggota Palang Merah Indonesia (PMI) di Purwakarta. Tak berhenti di situ, ia juga menulis. Rukiah merespons perjuangan anggota laskar pada 1946 dengan puisi dan dimuat di majalah Gelombang Zaman. Rukiah juga mengirimkan tulisannya ke Mimbar Indonesia dan Godam Djelata. Bersamaan dengan kepindahannya ke Jakarta pada 1950, Rukiah menjadi sekretaris majalah sastra, Pujangga Baru.
Rukiah konsisten menyuarakan gagasannya lewat tulisan. Pada 1950 novel pertamanya, Kejatuhan dan Hati, diterbitkan oleh Pustaka Rakyat. Dua tahun kemudian, buku kumpulan cerita pendek dan puisi Tandus (1952), terbit. Karya tersebut mengantarkan Rukiah sebagai penulis perempuan pertama yang mendapat penghargaan sastra dari Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional.
Kiprah Rukiah dalam dunia sastra berjalan beriringan dengan pergerakan politiknya. Bersama penulis Sugiarti Siswadi, ia menjadi delegasi Lekra pada Kongres ke-V “Himpunan Sastrawan Jerman” di Jerman Timur. Pada forum tersebut, Rukiah membacakan pidato sambutan untuk mewakili Lekra. Ia juga mengelola majalah Api Kartini yang diinisiasi oleh Gerwani, serta menggagas jurnal kebudayaan, Indonesia Irama. Rukiah tidak ingin menulis dalam kesunyian. Rukiah sadar bahwa kekuatan tulisan perlu dirawat bersama dalam ruang-ruang penulisan. Berperan sebagai editor, ia juga merawat berbagai ruang menulis lainnya, mulai dari tulisan sastra, pergerakan, hingga sastra anak.
Selain sebagai penulis, Rukiah memiliki posisi penting dalam dunia pergerakan, salah satunya sebagai anggota pimpinan pusat Lekra. Posisi penting tersebut membuat nama dan karyanya harus dihilangkan setelah pemberangusan PKI pada 1965. Cukup lama untuk kita bisa membaca karya Rukiah kembali. Tak hanya karena karyanya yang dihilangkan setelah 1965, namun juga karena ia adalah seorang penulis perempuan. Penulis perempuan kerap kali dipinggirkan dari deretan tokoh lain yang dianggap sebagai 'patron' sastra Indonesia.
Perlahan nama Rukiah bangkit kembali dengan karya-karyanya yang mulai dibaca dan ditelaah oleh penulis, peneliti sastra hingga pelaku seni pertunjukan di Indonesia hari ini. Terdapat penerbitan kembali Kejatuhan dan Hati, Tandus, serta cerita anak Pak Supi: Kakek Penggungsi oleh penerbit Ultimus. Ada pula penelitian tentang pemikiran Rukiah dalam tesis The Work of S. Rukiah (Gallop, 1985); Independent Woman in Postcolonial Indonesia: Rereading the Works of Rukiah (Wirawan, 2018); dan Mengukur Kesunyian: Kehidupan dan Kekaryaan S. Rukiah (Austriningrum, 2021). Selain penerbitan dan penelitian, karya dan pemikiran Rukiah juga dapat kita temukan dalam pertunjukan teater Sebagian Pertemuan dan Api Kartini Edisi Khusus: Mencatat Kerja dan Pemikiran Perempuan (2021-2023) karya Mirat Kolektif. Dari kerja-kerja para peneliti hingga pelaku seni pertunjukan tersebut, kita kemudian bisa terhubung dengan karya dan pemikiran Rukiah yang masih sangat relevan di hari ini.
Rukiah dan Pemikirannya dalam Tulisan
Membaca kembali karya Rukiah dan kiprahnya dalam dunia sastra dan pergerakan, membawa kami pada pernyataan “betapa maju dan terbuka pemikiran seorang penulis perempuan yang karyanya cukup terkenal pada era 1950-an.” Kami berusaha menelusuri pemikiran maju dan terbuka itu melalui tulisan-tulisannya, salah satunya pada cerita pendek yang terkumpul dalam Tandus. Selain memuat kumpulan puisi karya Rukiah, Tandus berisi enam cerpen yaitu “Mak Esah”, “Istri Prajurit”, “Antara Dua Gambaran”, “Surat Panjang dari Gunung”, “Ceritanya Sesudah Kembali”, dan “Sebuah Cerita Malam Ini”.
“...ketika orang-orang di kampungnya mulai ramai mengata-ngatakan: “negara sedang perang.” Tapi Mak Esah tidak tahu apa-apa cuma tahu beras terus mahal ketika itu, hingga dua rupiah segantang.”
(Cerpen “Mak Esah” dalam buku Tandus terbitan Ultimus, tahun 2017, hal. 71)
“...Pak, Siti masih juga belum mengerti, apakah hubungannya pemerintahan negara yang tidak dikenalnya itu dengan kebun sayuran kecil buat makannya sehari-hari.”
(Cerpen “Istri Prajurit” dalam buku Tandus terbitan Ultimus, tahun 2017, hal. 84)
Pada kisah “Mak Esah” dan “Istri Prajurit”, Rukiah menggambarkan bagaimana perubahan geopolitik menyelusup dan mengacaukan logika atas hubungan antarmanusia dan tanah kolonial. Rukiah menggambarkan bagaimana geopolitik global beserta kendali pemerintahan yang berkuasa saat itu, tidak menyisakan sebidang tanah pun bagi mereka. Gagasan antikolonialisme ia hadirkan melalui tokoh “orang-orang biasa” dalam tulisannya. Kelindan pengalamannya bersama Lekra dan gerakan perjuangan rakyat, sangat memengaruhi sudut pandang Rukiah dari kacamata "orang-orang biasa". Ia memperjelas bahwa kuasa yang silih berganti menempati Indonesia memiliki persamaan: mereka tidak melibatkan rakyat kecil, tetapi rakyat kecil mau-tak-mau selalu terlibat.
Melalui tokoh-tokoh semacam itu pula, Rukiah menggambarkan bagaimana persilangan identitas diri dapat membuat seseorang mengalami penindasan berlapis. Pada tokoh Mak Esah, Rukiah menggambarkan situasi seorang perempuan, janda, lansia, di sebuah desa, di negara yang dikolonisasi. Meskipun Rukiah merupakan perempuan yang terlibat aktif dalam politik, ia memahami bahwa pengalaman dan penindasan yang dialami perempuan beragam. Pemikiran Rukiah tersebut menunjukkan bahwa ide-ide yang bersinggungan lintas disiplin (interseksional) sudah muncul dalam karya-karyanya. Rukiah melihat jauh ke depan, di saat gagasan interseksionalitas baru mulai menguat sekitar 1980-an. Ia memahami bahwa persoalan dan ketidakadilan yang dialami perempuan harus dilihat dari sudut pandang yang lebih luas.
Pada cerpen “Antara Dua Gambaran”, Rukiah menggambarkan tokoh Ati yang tengah mengenang kekasihnya, Irwan, yang mati akibat revolusi.
“Irwan mati karena revolusi, mati seperti pemuda-pemuda lain yang dituliskan dalam cerita-cerita pendek yang bertebaran di mana-mana. Hanya bedanya di sini, Irwan bukan opsir TNI, dan aku bukan gadis PMI yang berani ikut ke garis depan—.”
(Cerpen “Antara Dua Gambaran” dalam buku Tandus terbitan Ultimus, tahun 2017, hal. 99)
Potongan kalimat di atas menjelaskan bagaimana Rukiah berpandangan tentang status seorang yang mati di tengah geliat revolusi negara. Bagi Ati, Irwan adalah sosok laki-laki biasa yang tidak masuk dalam golongan TNI atau orang penting berpangkat tinggi. Rukiah seperti hendak mengatakan, bahwa ada bentuk perlakuan berbeda yang dilakukan negara pada korban-korban revolusi. Apa yang terjadi pada Irwan setelah ia tiada, tidak ada beda. Kematian Irwan dan “orang-orang biasa” lainnya, tidak diikuti dengan nyanyian perkabungan.
Rukiah memperlihatkan pula bagaimana perempuan menerima dampak yang berat, baik secara fisik maupun mental. Posisi perempuan kerap tak dianggap, bahkan tak berhak untuk merespons peristiwa yang ia alami sendiri. Ihwal tersebut, seperti yang disampaikan tokoh Ati, “...dan aku cuma menulis tentang apa arti keaslian, sedangkan orang kosong dalam cerita yang tadi, sedikit pun tak aku bawa-bawa dalam tulisan ini.”
Penggalan cerpen di atas menandakan bahwa sebagai perempuan, Ati dinilai tak layak menyuarakan isi hatinya. Menariknya, pada akhir tulisan, tokoh Ati digambarkan sebagai sosok yang begitu berani dan nyaris frontal. Pada “Antara Dua Gambaran”, terdapat tokoh perempuan bernama Didjah yang dianggap oleh Irwan sebagai sosok yang berdosa karena menggugurkan kandungan. Namun tokoh Ati menanggapi dengan tenang, “Ya, tapi bila ada satu kejadian seperti si Didjah demikian, Engkau jangan menyalahkan pihak sebelah saja.”
Tokoh Ati sadar betul bahwa penyelesaian permasalahan seorang perempuan juga dipengaruhi dari ragam pengalaman di sekitarnya. Rukiah pada era 1950-an sudah lantang mengemukakan gagasan yang bersifat interseksional, bahwa keadaan sosial, identitas, adat istiadat setempat, etnisitas, kelas sosial, agama, juga turut memengaruhi kondisi yang dialami perempuan.
Cerpen lainnya dalam buku Tandus adalah “Surat Panjang dari Gunung”. Rukiah mengajak pembaca merasakan apa yang dirasakannya sebagai penulis perempuan di masa itu—pandangan laki-laki terhadap tulisan-tulisan perempuan.
“Sering kucari, mana kata-katamu yang menampakkan kalimat kasihmu, cintamu terhadap negara, dan rakyat?”
(Cerpen “Surat Panjang dari Gunung” dalam buku Tandus terbitan Ultimus, tahun 2017, hal. 131)
Kalimat dalam surat Ham tersebut, merupakan peristiwa yang dirasakan Rukiah selama proses kreatif menulis sajak dan prosa. Tokoh Ham hadir mewakili laki-laki yang memandang tulisan perempuan sebagai sekadar catatan perasaan yang “berlebihan”. Laki-laki patriarkis berpandangan bahwa muatan perasaan dalam karya perempuan tidak penting dan bukan suara yang perlu didengar.
“Tapi ketika kubaca cerita-ceritamu dari macam-macam majalah dalam bungkusan itu, tiba-tiba engkau berganti di mataku jadi manusia nyata pengisi kenyataan, pemegang revolusi.”
(Cerpen “Surat Panjang dari Gunung” dalam buku Tandus terbitan Ultimus, tahun 2017, hal. 132)
Dari kalimat di atas, tampak Ham—sebagai laki-laki sekaligus pejuang yang sedang bergerilya—akhirnya menyadari Isti memiliki suara dan perjuangannya sendiri tentang kondisi politik di negerinya.
Meskipun Ham masih menyelipkan kalimat, “Ah Isti, kukira seorang penulis kecil macam engkau tak akan bisa kerja berhubungan dengan soal-soal negara dan politik yang harus dipilihnya,” Ham juga menyinggung penulis lain yang menurutnya hanya menulis untuk kemasyhuran diri sendiri. Bagian ini terbaca sebagai rasa sangsi Ham akan kemampuan penulis perempuan untuk menyuarakan kondisi rakyat dan politik di masa itu. Pada akhirnya Ham mengakui dalam suratnya, tulisan-tulisan Isti bisa membuatnya terpengaruh.
Tokoh Ham menemukan narasi-narasi tentang revolusi dan pengorbanan dalam prosa yang ditulis Isti. Isti digambarkan membaca salah satu novel Huxley, yang bercerita tentang masyarakat dan kelas sosial dengan fokus utama tentang ketidaksetaraan perempuan. Pada cerpen tersebut, Isti menolak menjadi “gerombolan pengekor yang lemah”, seperti yang dibacanya dalam karya Huxley, “Aku mau jadi orang yang berpikir sendiri, lepas dari kudde-moraal atau susila kambing itu.” Isti menyatakan sikapnya yang tidak ingin menyerah begitu saja atau menunggu orang-orang di sekitarnya paham arti kebebasan dalam konteks penjajahan.
Perspektif anak di masa itu juga dimasukkan Rukiah dalam “Surat Panjang dari Gunung”. Cerpen ini tentang Mimi yang tak lagi bersekolah karena ayahnya diambil Belanda, dan Haja—kurir surat Ham untuk Isti—yang juga memilih ikut dengan Ham, berjuang sembunyi-sembunyi sebab kedua orang tuanya telah tiada. Melalui perspektif anak, kita diberi tahu oleh Rukiah bahwa pada masa itu tak ada pilihan yang lebih baik dari pilihan lainnya; pun Haja yang memilih tak lagi sekolah untuk ikut dengan rombongan pejuang yang bermarkas di hutan. Kami memandang kehadiran anak dalam cerita ini merupakan refleksi Rukiah yang dekat dengan literasi anak, sekaligus menggambarkan posisi anak-anak di tengah pergolakan masa revolusi saat itu.
Pada surat Ham yang lain, ia meminjam pandangan Voltaire tentang mempertahankan kemerdekaan; yang telah menjadi api semangat bagi rakyat yang tidak tahu apa-apa. Kemudian di akhir cerita, Isti mengumpulkan surat-surat Ham dan membakarnya. Tapi ada yang menyala dalam dadanya bahwa perempuan bukan sebuah panggung, melainkan manusia yang harus bermain dan mengambil keputusannya. Intelektualitas Rukiah tampak pada cerita pendek ini, yakni tentang bagaimana seorang perempuan penulis di masa itu sudah membaca karya-karya penulis lain, yang kemudian menjadi “bahan bakarnya” dalam menulis cerita.
Perjuangan yang Tak Putus
Meski pasca 1965 Rukiah menjadi salah satu penulis yang ditahan dan dibungkam akibat hubungan dan keterlibatannya dengan pergerakan kiri di Indonesia, karya dan kontribusinya tidak putus dari kesusastraan dan kehidupan masa kini. Tulisan-tulisan Rukiah juga mematahkan narasi tentang tulisan perempuan yang sering dikatakan sekadar autobiografi dan tidak memiliki unsur politis di dalamnya. Tulisan personal atau memoar perempuan sering kali diremehkan. Namun Rukiah mampu menggambarkan wilayah personal, sekaligus juga tegas menuliskan pilihan-pilihan politisnya.
Rukiah membuktikan bahwa tulisan perempuan dapat begitu tajam mengkritik persoalan politik di suatu negara, dan pada saat yang sama mengangkat hal-hal yang luput dibahas. Ia menulisnya pada era 1950-an, tetapi ketajaman gagasannya masih relevan sampai sekarang. Hal inilah yang membuat perjuangan Rukiah tak putus. Teknik menulis Rukiah tajam dan kritis. Kemampuannya dalam membuat narasi yang berani dan mengobarkan semangat, dapat pula menjadi rujukan penulis masa kini dalam mengkritisi situasi politik. Kita dapat mempelajari bagaimana cara Rukiah merespons suatu kondisi politik di sekitarnya.
Pengalaman menyelami pemikiran Rukiah melalui cerita-ceritanya, seperti melakukan perjalanan melintasi waktu. Meski jauh dari masa kita berada sekarang, Rukiah menyilakan kita membuka pintu pada karya-karyanya, melihat peristiwa yang dialaminya, dan merasakan dinamika perempuan saat itu. Rukiah adalah perempuan yang dibesarkan dalam kegentingan masa revolusi. Ia adalah seorang perempuan yang memiliki semangat serta cara berpikir revolusioner. Rukiah dengan jitu menggunakan cara-caranya sendiri untuk menyampaikan gagasannya tentang situasi penindasan di sekitarnya. Semangat ini masih membara melampaui zaman dan merasuki kita, para pembacanya, hingga sekarang. Membaca kembali pemikiran Rukiah melalui tulisan-tulisannya adalah upaya untuk meneruskan perjuangan seorang tokoh, guru, penulis perempuan yang tak putus dari masa ke masa.
***
Kepustakaan
Austriningrum, Giovanni Desy. Mengukur Kesunyian: Kehidupan dan Kekaryaan S. Rukiah. Dalam Ruang Perempuan dan Tulisan, Yang Terlupakan dan Dilupakan. Marjin Kiri, Jakarta, 2021.
Hidayati, Nur, Ardiani Nur Fadhila, dan Muhammad Adhimas Prasetyo. "Narasi Domestikasi Perempuan Era Kemerdekaan pada Enam Cerpen S. Rukiah yang Terhimpun dalam Buku Tandus." Dalam Jurnal Wanita Dan Keluarga 1.2 (2020): 1-15.
Mirat Kolektif. 2023. Dokumentasi Pertunjukan “Sebagian Pertemuan”. https://www.instagram.com/p/Cq1_zDqBhqX/?igsh=MWtlbmZza3RxZHBnZA==.
Rukiah, Siti. Tandus. Ultimus, Bandung, 2017.
Shackford-Bradley, Julie. Autobiographical fictions: Indonesian Women's Writing from the Nationalist Period. University of California, Berkeley, 2000.
Wirawan, Yerry. "Independent Woman in Postcolonial Indonesia: Rereading the Works of Rukiah." Dalam Southeast Asian Studies 7.1 (2018): 85-101.
—
Tulisan ini turut dikembangkan dalam Lokakarya Kolaborasi Lab Perspektif Perempuan X Sekolah Pemikiran Perempuan yang berlangsung secara daring pada 7 Oktober 2023. Lokakarya tersebut merupakan kolaborasi SPP dengan Komite Seni Rupa Dewan Kesenian Jakarta (DKJ).