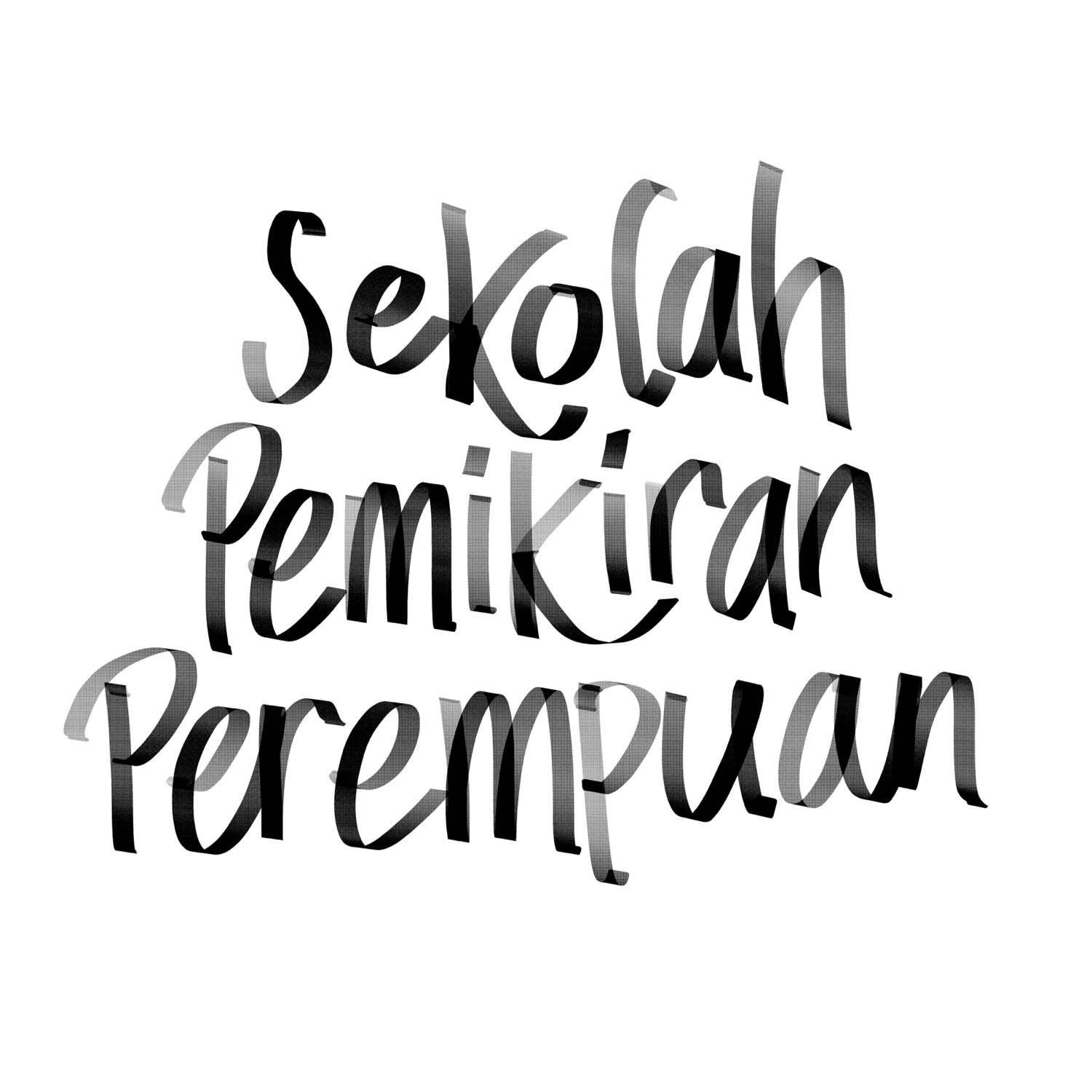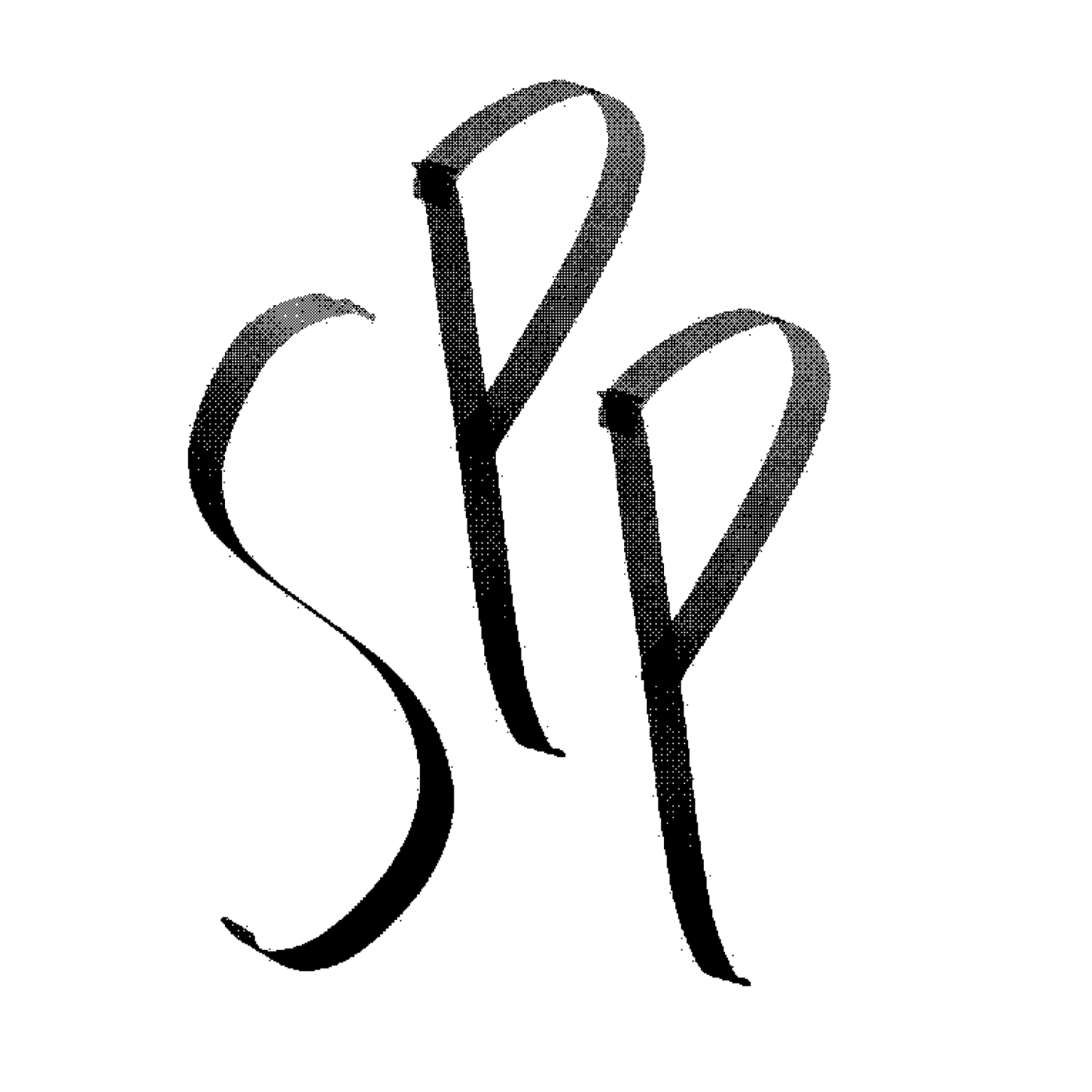Linda Tuhiwai Smith: Siasat Melawan Penghancuran Identitas Indijenes
oleh: Gema Swaratyagita, Martha Hebi, Riyana Rizki, dan Syifanie Alexander
“Kata itu, ‘penelitian’, mungkin merupakan salah satu kata paling kotor dalam kamus istilah dunia indijenes.”
Kutipan di atas adalah pernyataan seorang perempuan Māori,1 Linda Tuhiwai Smith, sebagai bentuk perlawanan indijenes (masyarakat adat) Māori, Selandia Baru terhadap hegemoni pihak luar (baca: Barat). Siapakah Linda dan mengapa dia melontarkan narasi ini?
Linda Tuhiwai Te Rina Smith (lahir 1950) adalah seorang indijenes Māori dengan perhatian pada metodologi penelitian dan aktivisme pendidikan sebagai cara untuk membongkar penindasan kolonialisme dan imperialisme. Linda yang saat ini menjadi profesor di Universitas Waikato di Hamilton, Selandia Baru menempati posisi yang krusial untuk memperjuangkan kepentingan indijenes dalam ruang-ruang akademis. Usahanya patut diapresiasi mengingat bukan perkara mudah bagi indijenes untuk memperjuangkan posisi tersebut di ruang-ruang akademis, terlebih sebagai sosok perempuan. Linda memperoleh gelar BA, MA (hons), dan PhD di Universitas Auckland, Selandia Baru. Pada 1999, ia menerbitkan buku Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples, salah satu karya terpenting dalam kajian dekolonisasi yang membuatnya dikenal lebih luas.
Berangkat dari lingkungan keluarga, Linda diajarkan untuk tidak hanya menghargai pendidikan bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi kepentingan dan komitmen terhadap pendidikan dan bahasa Māori. Ibunya, June Te Rina Mead, adalah guru dan pegawai negeri. Sementara ayahnya, Hirini Moko Mead, adalah antropolog Māori. Linda kecil pindah ke Amerika Serikat mengikuti ayahnya yang saat itu sedang menyelesaikan program doktoral di negeri tersebut. Kepindahan itu menjadi langkah awal baginya untuk melihat dunia pendidikan dengan pengalaman berbeda. Ia masuk dalam sekolah Amerika yang memisahkan antara anak kulit putih dengan berwarna. Sebagai salah satu dari enam murid kulit berwarna lainnya, pengalaman masa remaja Linda tidak mudah, terutama dalam bersosialisasi dan bersahabat. Pengalaman ini yang kemudian menjadi cikal bakal sikap radikal Linda terhadap ketidakadilan, ketidaksetaraan, dan rasisme yang juga dirasakannya saat tinggal di Selandia Baru.2
Linda memiliki ingatan masa kecil yang kuat tentang museum ketika membantu ayahnya, yang melakukan penelitian di gudang Museum Memorial Perang Auckland dan museum lainnya di Amerika Serikat. Pengalaman tersebut membawanya menjadi asisten di Museum Peabody di Salem, Massachusetts, sebagai pekerjaan pertamanya di usia 16 tahun. Linda tumbuh dalam dunia yang memungkinkan sains, praktik, dan keyakinan indijenes eksis bersamaan. Dengan latar masa kecil tersebut, ia tidak memilih menjadi antropolog seperti jejak ayahnya. Ia lebih memilih bidang pendidikan yang menurutnya lebih memuat kekayaan sejarah terkait penelitian. Penelitian inilah yang melegitimasi pandangan tentang orang-orang indijenes selama ini dengan cara antagonistik dan menurunkan derajat kemanusiaan, sehingga, karenanya, penelitian perlu untuk dilihat dengan kritis. Linda kemudian lebih banyak mendedikasikan waktu sebagai seorang peneliti, akademisi, dan aktivis.
Bagi Linda, pendidikan adalah jalan untuk keluar dari keterpurukan yang dialami orang-orang Māori, sehingga akses pengetahuan perlu dibuka seluas-luasnya dan didekolonisasi. Ia tidak ingin pengetahuan para cendekiawan indijenes menjadi tersisihkan dibandingkan dengan pengetahuan ilmiah yang dominan. Linda bersama suaminya, Prof. Graham Smith, mengembangkan kelas bertajuk “Pendidikan dan Orang Māori” pada level sarjana dan pascasarjana untuk diajarkan di Universitas Selandia Baru. Linda juga menyediakan beasiswa bagi kalangan indijenes dalam menempuh berbagai bidang keilmuan. Ia ingin indijenes tidak lagi ter(di)pinggirkan, dipandang berbeda, ataupun tidak menjadi bagian dari arus utama. Mendobrak pandangan-pandangan buruk tentang indijenes bukan hal mudah bagi Linda, tetapi ia percaya kekuatan yang terbangun dari solidaritas dapat menjaga mereka.
Mengapa Dekolonisasi?
Sepanjang membaca cuplikan kehidupan tentang Linda di atas, kita mungkin menemukan kata “dekolonisasi” dan “penelitian” bertebaran. Memang, keduanya adalah kata kunci yang mengantarkan kita pada pemikiran Linda, yang utamanya berasal dari karyanya Decolonizing Methodologies (1999). Salah satu pernyataan Linda yang paling sering dikutip dari buku ini, “kata itu, ‘penelitian’, mungkin merupakan salah satu kata paling kotor dalam kamus istilah dunia indijenes”, rasanya memang tidak berlebihan. Kemudian, pernyataan “kami adalah orang-orang yang paling sering diteliti di seluruh dunia” juga lebih dari sekadar sinisme. Pernyataan-pernyataan Linda ini tidak lepas dari kenyataan bahwa orang-orang indijenes telah dieksploitasi luar biasa bukan hanya secara fisik (penguasaan tanah, dsb) melainkan juga bahasa, budaya, hingga pengetahuannya. Di titik inilah dekolonisasi menjadi fundamental. Dekolonisasi, bagi Linda, menjadi alat untuk mendekonstruksi cerita dominan atau membongkar definisi yang telah mapan dari hasil bentukan Barat.
Dekolonisasi dalam konteks ini, sedikit berbeda dengan poskolonial. Meski keduanya sama-sama antikolonial,3 menolak konstruksi pengetahuan Barat terhadap Timur (atau, masyarakat pasca-terjajah) dan tujuan akhirnya sama-sama berupaya untuk menjadi berdaya, Linda merasa bahwa istilah poskolonial kurang tepat. Baginya, poskolonial di satu sisi bisa jadi problematik karena prefiks ‘pos’ dalam poskolonial menunjukkan seolah-olah kolonialisme telah selesai dan telah usang untuk dibicarakan—padahal kenyataannya tidak demikian.
Meski demikian, perlu dicatat bahwa dekolonisasi di sini bukan berarti menentang proses penelitian ataupun melakukan penolakan total terhadap semua teori dan pengetahuan dari Barat, melainkan berusaha memusatkan penelitian dari perspektif indijenes dan untuk tujuan atau kepentingan indijenes. Artinya, dekolonisasi berusaha untuk menemukan cara-cara baru dalam proses penelitian dan produksi pengetahuan lainnya. Cara baru ini sebagai bentuk penolakan menjadi “serangga di bawah mikroskop”.4
Mari Nona, Rebut Kembali!5
Menurut Linda, meski negara atau komunitas bekas jajahan telah merdeka, dampak kolonialisme dan imperialisme masih sangat terasa hingga sekarang. Ini yang kemudian mengantarkan kita pada gagasan kunci Linda: analisis historis!
Linda mendorong kawan-kawan indijenes untuk melakukan dekolonisasi dengan menulis (baca: meluruskan) dan mengklaim kembali pengetahuan dan sejarah dari perspektif indijenes. Caranya adalah mula-mula dengan mengenali dan menelusuri kisah indijenes di masa lalu, yang telah dikonstruksi sedemikian buruk oleh Barat. Dari penelusuran tersebut, kemudian indijenes dapat menuliskan testimoni tentang ketidakadilan di masa lalu dan membuat cerita tandingan (counter-stories) sebagai bentuk perlawanannya. Poin ini juga berarti mengubah posisi indijenes dari objek riset (pasif) menjadi subjek riset (aktif).
Meskipun cerita orang-orang indijines jarang diterima, tidak dianggap valid, dan terkadang tidak diakui dunia internasional karena anggapan bahwa mereka tidak mampu berpikir atau intelektualitasnya dipertanyakan, bagi Linda kebutuhan meriset oleh dan untuk indijenes ini merupakan perlawanan sekuat-kuatnya yang perlu diupayakan.
Gagasan kunci lain dari Linda adalah sikap kritis pada proses penelitian tersebut (sebagai bagian dari produksi pengetahuan), mengingat bahwa penelitian telah lama menjadi alat dehumanisasi atau merendahkan orang-orang indijenes. Cara utama yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis, antara lain: Siapa yang melakukan penelitian dan merumuskan masalahnya? Kepentingan siapa yang dilayani di riset ini? Apakah orang-orang indijenes mendapat manfaat dari penelitian ini? Siapa yang diuntungkan? Bagaimana relasi antara peneliti dengan indijenes, apakah setara? Bagaimana proses mendapatkan data, apakah etis? Bagi siapa penelitian ini layak dan relevan, kemudian siapa yang mengatakannya? Apakah penelitian ini bisa diakses oleh orang-orang indijenes sendiri? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini yang perlu diajukan secara terus-menerus sebagai strategi melakukan dekolonisasi.
Dengan analisis historis dan kritis semacam inilah, harapannya, indijenes dapat menentukan nasib mereka sendiri—Linda menyebutnya sebagai self-determination dalam agenda riset indijenes. Berbagai agenda riset yang sedang diupayakan oleh indijenes ini dinarasikan Linda dalam 25 metodologi/proyek penelitian pada satu bab tersendiri di bukunya.
Untuk melakukan penelitian yang berperspektif dekolonial, kita perlu menyusun kembali (reframing), menceritakan (storytelling), mengingat (remembering), menamai (naming), mengklaim (claiming), menunjukkan (representing), dst.6 Di antara strategi-strategi tersebut, gendering merupakan poin yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Pasalnya, pengalaman dan definisi ‘indijenes’ tidak tunggal atau seragam. Linda mengingatkan kita bahwa bagaimanapun pengalaman menjadi perempuan Māori itu berbeda dengan laki-laki Māori. Tentu ini tidak lepas dari sistem kolonial yang menempatkan perempuan sebagai properti milik laki-laki dan perannya dibatasi pada persoalan domestik.7 Laki-laki lebih punya privilese dalam ruang ‘publik’, misalnya terlibat pada pertemuan-pertemuan serius (perjanjian atau negosiasi perdagangan), sementara perempuan Māori disingkirkan. Pada akhirnya, mengusahakan dekolonisasi artinya pula mengusahakan feminisme dalam aktivisme indijenes.
Mencinta Adalah Juga Cara
(It is important to do this work from a place of love.)8
Lebih lanjut, yang tidak kalah menarik adalah bagaimana Linda memberi catatan bahwa perspektif penelitian dalam dekolonisasi, bukan hanya perkara kognitif (intelektualitas), melainkan juga perkara afektif (emosional). Dalam edisi terbaru bukunya,9 Linda secara khusus menambahkan poin ini. Perspektif Barat yang memang cenderung memisahkan antara emosi dengan kognisi serta melihat rasio di atas segalanya, telah mendistorsi berbagai cerita milik orang-orang indijenes. Misalnya, ide tentang cinta, kemarahan, atau kecemburuan direduksi oleh penulis kolonial dari cerita aslinya. Lebih krusial lagi, mereduksi sisi emosi di sini berarti ‘mereduksi perempuan’ dalam kisah-kisah Māori. Mengutip secara langsung dari Linda, mereka “melemahkan agensi perempuan dan orang tua, menghilangkan cara mendamaikan kemarahan, menetapkan penilaian moral baik dan buruk, [hingga] antara menyensor seks atau justru mengerotisasinya, dan menghapus semua rujukan tentang alam dan para dewa” dalam kisah-kisah orang Māori.10
Itulah mengapa, menurut Linda, urgen untuk menyoroti dan menghadirkan cinta dan kasih sayang dalam komunitas indijenes sebagai perlawanan terhadap kekerasan kolonial. Meskipun, memang Linda menyatakan bahwa bukan perkara mudah untuk mencintai diri (mencintai bahasa, pengetahuan, budaya, hingga warna kulit sebagai seorang indijenes sendiri), mengingat bahwa diskursus yang secara konsisten dibangun kolonialisme tersebut penuh dengan stereotipe, rasisme, dan kebencian yang menihilkan atau meremehkan perasaan dan kasih sayang.11
Prosesnya tidak mudah, perlu untuk dicatat bahwa pengamatan Linda tentang sisi afektif/emosional dalam dekolonisasi adalah poin yang luar biasa serius. Ini turut menggarisbawahi perspektif kolonial yang sangat male-centric, yang percaya pada objektivitas ilmu pengetahuan (anti terhadap subjektivitas), mengabaikan perasaan, dan merendahkan hal-hal emosional dengan menganggapnya sebagai sesuatu yang irasional. Hal-hal yang dianggap irasional ini, yang sering diidentikkan dengan perempuan, justru bisa menjadi kekuatan untuk merebut kembali sejarah yang tadinya penuh kekerasan dan dingin tak berperasaan (his-tory) menjadi sejarah yang penuh empati dan kasih sayang (her-story).
Menyembuhkan Luka-luka Batin—luka tapi tak berdarah12
Dampak kolonialisme dan imperialisme yang begitu kuat, juga telah menyisakan luka batin yang begitu mendalam pada orang-orang indijenes, dan luka-luka ini tak kasat mata. Kehilangan tanah, orang terdekat, bahasa, budaya hingga pengetahuan adalah kesedihan bersama orang-orang indijenes yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Pengalaman yang traumatis ini bahkan secara terus-menerus membekas ke generasi selanjutnya (inter-generational trauma), menjadi trauma yang sistemik. Ada beragam cara atau pendekatan yang dilakukan orang-orang Māori untuk menyembuhkan luka-luka batin (healing). Proses healing bisa ditemukan dalam apa saja, dalam aktivitas keseharian seperti menyiapkan makanan untuk pesta atau mengayuh kano (perahu kecil). Dapat juga ditemukan ketika menenun, melukis, memahat dan membuat barang tembikar. Proses healing ada dalam bahasa, praktik adat, makanan adat, permainan, tarian, humor, dan doa, bahkan dalam air, api, atau asap!13
Menariknya pula, menurut Linda, perspektif yang krusial dalam healing dari orang-orang Māori adalah bagaimana menyembuhkan luka secara kolektif, alih-alih individual seperti perspektif psikologi klinis Barat pada umumnya. Misalnya, sekelompok perempuan Choctaw melakukan proyek Yappalli yaitu perjalanan menelusuri “jejak air mata” (trail of tears) setiap tahunnya, sebagaimana yang terpaksa dilakukan nenek moyang mereka ke Oklahoma. Bagi mereka ini adalah cara menyembuhkan trauma historis, di sepanjang perjalanan mereka menghargai cinta, kekuatan dan perlawanan yang diwariskan nenek moyang untuk mereka. Itu mengapa perlu untuk melihat proses healing indijenes ini secara menyeluruh; menyentuh dimensi budaya, spiritual, emosional, sosial, hingga politik.14
Satu hal yang tidak kalah genting adalah bagaimana melibatkan seseorang yang mengalami trauma untuk memiliki kendali dan mengonstruksi cerita mereka sendiri. Ini merupakan tandingan dari metode psikologi klinis Barat yang cenderung mengabaikan keterlibatan “klien”-nya, misalnya dalam menulis catatan konseling. Catatan konseling tersebut ditulis dan hanya dimiliki oleh praktisi profesional yang bersangkutan. Kisah mereka diceritakan oleh orang lain, yang seringkali terjadi disalahartikan atau memiliki bias-bias tertentu. Catatan konseling yang terdistorsi ini pun kemudian bisa terus tereproduksi—bisa diberikan ke praktisi profesional lainnya. Ini berbeda dengan sekelompok perempuan Choctaw yang lebih punya kendali dalam menceritakan kisah mereka dan bahkan menciptakan cara healing versi mereka sendiri.
Belajar dari Māori: Klaim, Kuasai, dan Ciptakan!
Gerakan perlawanan Linda dalam konteks indijenes Māori, bukanlah satu-satunya isu indijenes vs kolonialisme, imperialisme dan kapitalisme di Selandia Baru. Kita dapat melihat kemiripan konflik indijenes di Kanada, Amerika Serikat, Australia, dan mungkin di banyak ruang lainnya. Kehadiran “pihak luar” dalam ruang indijenes ini, tidak lepas dari kapitalisme global yang menyusup melalui pendidikan, penelitian, perusahaan-perusahaan transnasional, dan jembatan lainnya.
Situasi-situasi semacam ini rasanya tidak asing pula kita jumpai misalnya di Papua, begitu banyak pihak berkepentingan mengeksploitasi Papua, sejak sangat lama, hingga hari ini. Mengutip Els Tieneke R.K15, bila dulunya claiming dan naming untuk menguasai indijenes (di Papua) dilakukan oleh Belanda, pada Orde Baru kolonisasi terus berlanjut melalui hegemoni budaya Jawa a la Soeharto—dan masih terus dilanggengkan hingga kini. Pernyataan ini mengingatkan kita pada argumen Linda untuk mengklaim kembali (re-claiming) dan menamai kembali (re-naming) sejarah indijenes yang direnggut oleh kolonialisme, imperialisme dan kapitalisme. Misi Linda sangat jelas, klaim (kembali) sejarah yang sudah dituliskan oleh pihak luar—artinya, indijenes menuliskan sejarahnya sendiri. Lalu, kuasai sistem (mis. metodologi penelitian), dan kemudian ciptakan metodologi baru yang berbasis nilai dan konteksnya indijenes.
Tentu, ini tidak mudah. Namun, rasanya bukan saja upaya untuk bersolidaritas terhadap kawan-kawan di Papua dan masyarakat adat lain di Indonesia—maupun di seluruh dunia—yang kita perlukan. Hal yang tidak kalah genting untuk kita lakukan di sini dan sekarang adalah bagaimana berupaya mempraktikkan (metodologi) dekolonisasi dalam keseharian, termasuk pada hal-hal yang mungkin dianggap sederhana terlebih sepele—misal, dari bagaimana gestur atau cara mata kita mengamati orang lain, terutama, yang kita anggap “berbeda” dari kita.
Bertautan dengan itu, kami pun bertanya-tanya pada diri kami sendiri: apa yang kami rasakan, pikirkan, lakukan, atau dapatkan setelah berupaya menyelami gagasan metodologi dekolonisasi? Di tataran yang lebih personal, kami dapat menguatkan diri kami bahwa pengalaman kami sebagai perempuan adalah pengetahuan yang valid, dan karenanya, kami mulai punya keberanian untuk berbicara di publik dan tidak meragukan intelektualitas kami sendiri.
Dengannya pula, kami berupaya menciptakan pendidikan versi kami sendiri, untuk anak-anak kami, tanpa harus terikat dengan institusi pendidikan. Kami juga merasa tervalidasi, bahwa berkarya (misalnya menulis puisi ataupun merangkai anting-anting) adalah proses penyembuhan jejak-jejak luka batin dan kegelisahan personal versi kami. Dalam konteks kerja-kerja penelitian, kami juga belajar dari Linda bahwa penelitian bukan hanya perihal hasil, melainkan juga proses. Proses untuk menjadi kritis dan terutama etis dalam melakukan penelitian dan aktivisme—dua aktivitas berbeda, yang perlu untuk saling berkelindan.16 Kesempatan melakukan penelitian adalah sebuah privilese, karenanya kami bisa secara langsung berupaya mempraktikkan metodologi dekolonisasi tersebut di dalam keseharian.
Namun, lebih lanjut, bila esensi dari penelitian diawali dengan bertanya atas suatu hal dan mencari tahu jawaban atasnya, maka, mestinya dekolonisasi melalui penelitian bisa dilakukan oleh siapa saja, dengan kesadaran kritis dan etis sebagai landasan berpikirnya. Mengutip pernyataan Linda, penelitian adalah “...tentang memuaskan kebutuhan untuk mengetahui, dan kebutuhan untuk memperluas batas-batas pengetahuan yang ada, melalui proses penyelidikan sistematis”.17 Dengan demikian, melalui keingintahuan dan kepekaan pada yang terpinggirkan, yang dilakukan secara kritis dan etis, maka kita bisa melakukan penelitian—tanpa terlebih dahulu risau dengan ketiadaan legitimasi institusi akademis atau pihak-pihak dominan tertentu. Maka, sebagaimana Linda dan kawan-kawan indijenes Māori, mari ciptakan metodologi kita sendiri: penelitian, dari dan untuk kita semua!
Membaca karya Linda secara kritis akan memberikan bekal untuk selalu bertanya dan mempertanyakan (indikasi) hegemoni yang mengabaikan pengalaman, pengetahuan, dan kebudayaan masyarakat. Pada akhirnya, pemikiran Linda mengantarkan kita pada pertanyaan reflektif: bagaimana dengan kondisi di sekitarmu?
*
Ucapan Terima Kasih
Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengelola Sekolah Pemikiran Perempuan yang memberikan kesempatan untuk bereksperimentasi dengan tulisan kami. Terima kasih kepada Intan Paramaditha, Lisabona Rahman, Margareth Ratih Fernandez, Amalia Sekarjati, Andy Yentriyani, Cecil Mariani, Naomi Srikandi, dan Nyak Ina Raseuki selaku pengelola SPP. Kami juga menghaturkan banyak terima kasih kepada para penanggap Brigitta Isabella dan Saras Dewi, juga kepada Els Tieneke Rieke Katmo dan seluruh narasumber pada sesi-sesi kelas SPP, serta, kepada seluruh kawan-kawan peserta Sekolah Pemikiran Perempuan yang hangat dan suportif yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu di sini.
Catatan Kaki
1] Istilah ‘indijenes’ ini merupakan terjemahan atau serapan langsung dari indigenous people(s) yang digunakan Linda dalam bukunya Decolonizing Methodologies (1999). Merujuk Linda, istilah ini muncul pada 1970-an dan dirasa mampu mewakili pengalaman, isu, dan perjuangan orang-orang terjajah di seluruh dunia. Meski demikian, istilah ini bisa jadi problematis bilamana dimaknai sebagai entitas tunggal. Oleh karena itu, perlu diperhatikan penggunaannya dan pemaknaannya pada masing-masing konteks masyarakatnya. Dalam konteks Indonesia—mengutip penjelasan Brigitta Isabella (penerjemah teks Linda)—terdapat berbagai variasi kata untuk merujuk istilah tersebut, seperti masyarakat asli, pribumi, hingga masyarakat adat. Masing-masing variasi tersebut memiliki permasalahannya sendiri jika dipadankan dalam konteks Indonesia yang beragam, sehingga kami bersepakat menggunakan serapan langsung dari istilah yang digunakan oleh Linda. Kami pun membuka ruang diskusi seluas-luasnya dari kawan-kawan pembaca bilamana ada tanggapan atau saran atas istilah yang dirasa lebih tepat untuk konteks pemikiran Linda ini.
2] Shringarpure, Bhakti. “Dekolonisasi Pendidikan: Percakapan dengan Linda Tuhiwai Smith.” Global Campaign for PEACEducation. 19 Juli 2021. Diakses pada 22 Maret 2022. https://www.peace-ed-campaign.org/id/decolonizing-education-a-conversation-with-linda-tuhiwai-smith/
3] Dalam “Postcolonial and Decolonial Dialogues”, Bhambra menjelaskan bahwa keduanya muncul sebagai perlawanan terhadap politik produksi pengetahuan yang merugikan pihak yang (pernah) dijajah. Dekolonial muncul sejak kedatangan Eropa pada abad ke-15 dan lahir dari pemikiran diaspora Amerika Selatan terhadap imperialisme Eropa, sedangkan poskolonialisme dimulai pada abad ke-19 dan ke-20 melalui pemikiran diaspora Timur Tengah dan Asia Selatan terhadap penjajahan Eropa dan Barat. Dekolonisasi dan poskolonialisme tidak hanya digunakan sebagai penghancur kolonialisme, tetapi juga sebagai perlawanan intelektual (yang dijajah) terhadap dominasi epistemologi dan sangat mampu (ia meminjam istilah Maria Lugones) untuk menghadirkan geopolitik baru pengetahuan. Lebih lanjut dalam Bhambra, Guminder K. “Postcolonial and Decolonial Dialogues.” Postcolonial Studies, 17, No. 2 (2014): 115-121, DOI: 10.1080/13688790.2014.966414.
4] “Kami punya sejarah tentang orang-orang yang meletakkan Māori di bawah mikroskop, persis seperti seorang ilmuwan mencermati serangga. Mereka yang mengamati merasa punya kekuasaan untuk mendefinisikan.” Ini merupakan pernyataan Merata Mita, perempuan Māori pembuat film, produser dan penulis terkenal di Selandia Baru. Pernyataan ini diangkat Linda menjadi sebuah narasi penting dalam bukunya untuk memetaforakan posisi indijenes dalam cengkeraman (pengetahuan) Barat.
5] Terinspirasi dari lirik lagu “Halo-halo Bandung” (Ismail Marzuki).
6] Smith, Linda Tuhiwai. Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples. London: Zed Books, 2021, 163-184.
7] Smith, Linda Tuhiwai. Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples., 173-174.
8] Smith, Linda Tuhiwai., 189.
9] Edisi pertama diterbitkan pada 1999, edisi kedua pada 2012 dan edisi ketiga (terbarunya) diterbitkan pada 2021.
10] Smith, Linda Tuhiwai., 190.
11] Smith, Linda Tuhiwai., 189.
12] Terinspirasi dari lirik lagu pop “Ajarkan Aku” (Arvian Dwi).
13] Smith, Linda Tuhiwai, 189.
14] Smith, Linda Tuhiwai. “Linda Tuhiwai Smith: Healing our Trauma.” E-TANGATA. 20 Maret 2022. Diakses pada 21 Maret 2022. https://e-tangata.co.nz/comment-and-analysis/linda-tuhiwai-smith-healing-our-trauma/.
15] Dalam sebuah kelas di Sekolah Pemikiran Perempuan, Els Tieneke Rieke Katmo, feminis asal Papua, mengorek ingatan kami (baca: sejarah) untuk melihat indijenes Papua dalam penindasan kapitalisme dan upaya penghilangan identitas yang dititipkan lewat sistem negara. Secara khusus, kami mengucapkan terima kasih kepada Els Rieke Katmo dan seluruh kawan-kawan Sekolah Pemikiran Perempuan yang memberi banyak perspektif bagi kami dan pada tulisan ini.
16] Kami memaknai bahwa metodologi dekolonisasi dalam hal ini tidak terbatas pada penelitian saja, terlebih—yang dianggap—akademis. Penelitian dan aktivisme, mestinya, tidak saling terpisah dan saling mengisi. Linda menyatakan bahwa penelitian dan aktivisme adalah dua kegiatan berbeda yang dilakukan oleh jenis orang berbeda dan menggunakan alat/cara yang berbeda untuk berbagai jenis tujuan. Peran keduanya juga sangat berbeda, meski satu orang yang sama bisa merangkap kedua peran tersebut. Namun demikian, kami sepakat bahwa keduanya memiliki visi yang serupa. Bilamana penelitian dicita-citakan dapat bermanfaat bagi masyarakatnya, maka demikian halnya cita-cita aktivisme, yang menginginkan transformasi sosial. Namun, itu kondisi idealnya. Bagi Linda, persoalannya selanjutnya adalah penelitian belum benar-benar menunjukkan kebermanfaatannya pada indijenes. Oleh karenanya, menurut Linda, peneliti maupun aktivis perlu ‘berbicara kembali’ atau ‘berbicara dengan’ kekuasaan. Poin ini dielaborasi lebih lanjut oleh Linda pada bab “Getting The Story Right, Telling The Story Well”, dapat dibaca dalam Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples (2021), 273-283.
17] Smith, Linda Tuhiwai., 222.
Kepustakaan
Bhambra, Guminder K. “Postcolonial and Decolonial Dialogues.” Postcolonial Studies, 17, No. 2 (2014): 115-121, DOI: 10.1080/13688790.2014.966414.
Shringarpure, Bhakti. “Dekolonisasi Pendidikan: Percakapan dengan Linda Tuhiwai Smith.” Global Campaign for PEACEducation. 19 Juli 2021. Diakses pada 22 Maret 2022. https://www.peace-ed-campaign.org/id/decolonizing-education-a-conversation-with-linda-tuhiwai-smith/
Smith, Linda Tuhiwai. Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples. London: Zed Books, 2021.
Smith, Linda Tuhiwai. “Linda Tuhiwai Smith: Healing our Trauma.” E-TANGATA. 20 Maret 2022. Diakses pada 21 Maret 2022. https://e-tangata.co.nz/comment-and-analysis/linda-tuhiwai-smith-healing-our-trauma/